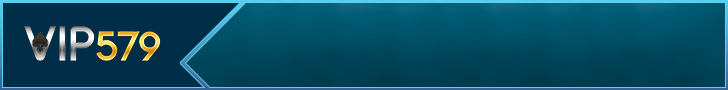Pendekar Elang Salju
Permisi suhu penggemar setia
Diawal tahun 2019 ini ijinkan nubi kembali menshare sebuah cerita silat lainnya karya GILANG SATRIA yang berjudul Pendekar Elang Salju yang nubi ambil dari website sebelah, silahkan dinikmati cerita silat ini.
Bab 1 Craakhh!! Kilatan bunga api langit meloncat memanjang, seolah-olah ingin menunjukkan sejauh mana ia bisa meloncat. Kilat bertebaran di langit yang tidak mendung. Sungguh aneh! Di dunia yang serba aneh ini, ternyata masih ada juga keanehan yang sulit diterka manusia. Kuasa Hyang Widhi memang tanpa dapat diduga atau pun ditebak oleh manusia. Tidak juga oleh laki-laki setengah baya yang berdiri tegak di bawah pohon sawo kecik itu. Tubuh tinggi kekar itu memandang kilatan-kilatan bunga api di langit dengan tatapan kosong. Raut mukanya menyiratkan kesedihan. Guratan duka di wajahnya semakin nyata dengan banyaknya kerutan diwajahnya yang bersih. Kedua tangan bersedekap seperti orang kedinginan. Laki-laki itu berbaju hitam lengan panjang dengan celana putih diikat yang diikat sabuk kain warna hijau, tampak berkibar-kibar ditiup angin. Dada bidang penuh dengan urat-urat bertonjolan, pertanda laki-laki parobaya itu bukan sosok manusia biasa, setidaknya pernah belajar olah kanuragan. Sorot matanya tampak tajam. Tarikan nafas yang pelan dan teratur seolah ingin menikmati segarnya udara siang yang tidak begitu panas. Craakhh!! Craakhh!! GLAARRR!! Kembali kilatan bunga api disertai suara guntur menggelegar dengan keras. Laki-laki paraboya itu kembali mendongakkan kepalanya. “Pertanda apa ini? Di siang hari bolong tanpa mendung ada kilat?!” batin laki-laki tersebut dengan dahi berkerut. Tiba-tiba ia teringat sesuatu saat guntur memperdengarkan suara di kejauhan. Mimpi! Ya, mimpi yang selalu mengganggu tidurnya. Mimpi yang berhubungan dengan anak yang dikandung istrinya. Anak pertama! Aneh memang, dengan usia yang sudah hampir empat puluhan tahun itu, dia belum memiliki seorang anak pun, meski sudah berumah tangga lebih dari belasan tahun lamanya. Sedangkan tetangga yang usianya sepantaran dengannya sudah memiliki empat hingga enam orang anak, bahkan ada yang sudah menimang cucu! Sungguh iri hatinya jika mendapat undangan untuk menghadiri tetangga atau pun warga desa yang istrinya melahirkan seorang bayi. Tentu saja sebagai seorang tetangga yang baik dan pula sebagai seorang kepala desa yang bijak, malu jika menampik niat baik orang yang sudah bersusah payah mengundangnya. Di saat istrinya hamil untuk pertama kali, hatinya begitu bersuka cita. Saat kandungan sang istri yang bernama Nyi Salindri berumur satu dua bulan, para tetangga kiri kanan sudah mengetahuinya, bahkan seluruh desa Watu Belah. Kemana pun dia pergi meninjau sawah dan ladang, seulas senyum sumringah tak pernah lepas dari bibir. Hatinya begitu bahagia karena apa yang sudah ditunggu puluhan tahun akhirnya terkabul juga. Doa siang malam agar dikarunia seorang momongan akhirnya didengar oleh Yang Kuasa. Tak peduli memiliki anak perempuan atau laki-laki, yang penting punya anak yang sehat dan montok. Tentu saja orang-orang desa itu senang karena Ki Ragil Kuniran, yang juga kepala desa Watu Belah, akan segera memiliki calon penerus keluarga Ragil Kuniran. Saat usia kandungan Nyi Salindri menginjak sembilan bulan, Ki Ragil Kuniran sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan dukun bayi desa itu sudah diwanti-wanti agar datang ke rumahnya untuk mengetahui kapan kira-kira bayi itu akan lahir. Saat itu, Nyi Cendani memeriksa kandungan Nyi Salindri dengan seksama. Wajahnya berkerut-merut tak karuan. Tangan keriputnya bergerak lincah kesana-kemari persis tangan maling. Pencet sana pencet sini. Urut sana urut sini. Pijat sana pijat sini. Ki Ragil Kuniran memandang dengan mata ikut jelalatan kesana kemari mengikuti gerak tangan lincah Nyi Cendani, si dukun bayi. “Bagaimana Nyi? Kapan keluar? Apakah sehat-sehat saja? Anaknya laki-laki apa perempuan?” cerocos Ki Ragil Kuniran tidak sabar. “Emmm … sebentar Ki Ragil … sebentar … ” Nyi Cendani kembali menggerayangi perut buncit Nyi Salindri. Tangan keriputan itu kembali bergerak lincah menelusuri bagian demi bagian dari perut buncit itu. Terakhir Nyi Cendani menekan pusar Nyi Salindri dengan pelan. Sreep! Tiba-tiba saja, perut Nyi Salindri menggelinjang lembut. Nyi Salindri yang sedari tadi menahan rasa geli, karena tangan keriput itu terus ‘bergerilya’ di atas perutnya. “Hi-hi-hi-hi … anakmu menendang Ki, mungkin sudah pingin keluar … ” Nyi Salindri tertawa lirih karena rasa geli itu sudah tak tertahankan lagi. Perut itu menggelinjang kembali. Wajah Nyi Cendani kelihatan puas. Mata tua itu berbinar-binar persis senthir diisi minyak kelapa. “Wah … selamat Ki Ragil! Laki-laki! Anakmu laki-laki! Sebentar lagi kau akan menjadi seorang ayah! Sekali lagi selamat, Ki!” kata Nyi Cendani dengan suara cempreng. Nyi Cendani, dukun bayi dari desa Watu Belah berusia mendekati seratusan tahun yang sudah amat terkenal, baik di desa Watu Belah sendiri, sampai di desa-desa tetangga. Kelincahan tangan dan tata cara serta ilmu pengobatan yang dimiliki terutama tentang seluk-beluk bayi sudah mendarah daging. Bahkan cara membantu persalinan bayi pun juga berbeda dari dukun bayi pada umumnya. Biasanya dukun bayi memotong pusar dengan bantuan welat, semacam sayatan bambu yang diiris melintang sepanjang jari kelingking, lalu itu welat dicuci dengan air hangat atau air panas, setelah itu baru digunakan untuk memotong pusar mau pun memisahkan ari-ari sang jabang bayi. Tapi Nyi Cendani melakukan dengan cara yang berbeda, bisa dikata amat aneh atau malah tidak lumrah. Setelah bayi lahir, tangan kirinya melakukan gerakan-gerakan melingkar di seputar perut ibu yang baru saja melahirkan. Gerakan-gerakan itu berputar dengan teratur layaknya pusaran air. Pada saat bersamaan, ibu yang baru saja melahirkan merasakan sebuah sentuhan tangan yang nyaman, menimbulkan hawa sejuk yang lambat laun menyebar ke sekujur badan. Setelah masa itu selesai, rasa lelah dan rasa sakit akibat melahirkan, baik sekitar perut dan rasa pegal-pegal di pinggang maupun di pinggul akan hilang dalam sekejap. Dan setelah itu tali pusar bayi di potong putus dengan dua jari tangan layaknya pisau tajam. Hal itulah yang membuat nama Nyi Cendani sebagai dukun bayi menjadi tersohor, bahkan sampai keluar desa Watu Belah. Puluhan bahkan ratusan orang telah ditolong lewat tangannya. Bahkan untuk mengobati orang sakit, Nyi Cendani juga mampu melakukannya. Di rumahnya yang berada persis di sisi sebelah timur desa Watu Belah, terdapat banyak empon-empon, seperti jahe merah, kunir putih dan bahan ramuan rempah-rempah lainnya. Ilmu pengobatannya juga sangat hebat, segala macam sakit akan lenyap jika sudah ditangani oleh Nyi Cendani. Kadang anak-anak desa sering bermain di rumahnya, diajari bagaimana cara meramu dan mengolah obat dari akar-akaran, daun-daunan bahkan dari getah pohon, sehingga banyak anak-anak mau pun pemuda desa yang menimba ilmu pengobatan dari nenek tua itu. Meski begitu, tidak semua orang mengetahui siapa sebenarnya nenek tua itu. Mereka hanya tahu bahwa nenek tua itu hidup sendiri, hanya ditemani oleh rempah-rempah atau empon-empon yang ada di rumahnya. Saat masih muda, Nyi Cendani yang bernama asli Dewi Cendani pernah mengangkat nama besar di dunia persilatan dengan gelaran Dewi Obat Tangan Delapan, seorang pendekar wanita mumpuni, tangguh dan memiliki ilmu kanuragan cukup tinggi dan menempatkan diri di jajaran tokoh-tokoh golongan putih, dimana sepak terjangnya selalu menentang segala macam kejahatan. Sebagai seorang murid tokoh sakti aliran sesat yang berjuluk Iblis Botak, Dewi Cendani cukup menggegerkan dunia persilatan. Bagaimana tidak, seorang tokoh hitam kelas tinggi, jika memiliki murid atau pewaris ilmu yang dimilikinya, biasanya bisa dipastikan menjadi tokoh hitam pula. Namun hal itu tidak terjadi pada Dewi Cendani yang saat itu baru berumur sepuluh tahun. Rupanya telah terjadi perubahan yang sangat mencolok pada diri Iblis Botak. Saat ia melihat gadis kecil itu, tiba-tiba kenangan indah bersama istrinya seakan terulang kembali. Kenangan yang manis, dan bocah itu seakan membawanya kembali ke masa-masa bahagia bersama istrinya. Itulah sebabnya mengapa Iblis Botak berubah haluan, yang semula menjadi dedengkot aliran sesat menjadi berbalik arah menjadi seorang tokoh yang welas asih, penyabar dan menjadi seorang yang baik serta bijak. Seluruh ilmu kesaktian diturunkan kepada murid tunggalnya, Dewi Cendani. *** “Laki-laki … ? Betul laki-laki? Nyi Cendani tidak main-main?” tanya ulang Ki Ragil Kuniran dengan mata berbinar. “I ya … laki-laki, aku yakin itu,” tandas Nyi Cendani dengan mengangguk-angguk kepalanya. “Ha-ha-ha-ha … ” “Kenapa Ki? Kok malah ketawa?” Nyi Salindri bertanya sambil berusaha duduk di pembaringan. Nyi Cendani segera membantu Nyi Salindri membenahi baju luar perempuan istri kepala desa itu. Ki Ragil Kuniran tidak menyahut, malah tertawanya makin keras, sampai air matanya keluar. Laki-laki parobaya itu tetap tertawa sambil melangkah keluar kamar dan terus menuju pendopo rumahnya. Kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi. Diambilnya napas dalam-dalam, dan dengan lantang, Ki Ragil Kuniran berteriak dengan keras, “Hooooiiii!! Seluruh warga desa Watu Belah, ketahuilah bahwa aku, Ki Ragil Kuniran akan segera mempunyai anak laki-laki, ya … anak laki-laki … !!” Suara itu menggema sampai ke pelosok desa Watu Belah. Orang-orang yang sedang bekerja di sawah atau ladang, kontan terkaget-kaget dan menghentikan sesaat pekerjaannya. Kaget, karena tidak biasanya mendengar suara sekeras dan segembira itu. Tapi setelah mendengar dengan seksama dan mengetahui siapa pemilik suara itu, mereka hanya geleng-geleng kepala. “Ki Ragil itu ada-ada saja.” “Ya tidak apa apa tho kang. Ki Ragil sekarangkan sedang bungah, berbahagia, kukira wajar kalau orang gembira meluapkan rasa gembira di hatinya itu,” sahut istrinya sambil terus memilah-milah kacang tanah ditangannya. “Lha iya, tapi mbok ya jangan teriak-teriak begitu, sudah tua kok pencilakan kayak anakmu saja.” “Terserah kakang lah … ” sahut istrinya menyerah. -o0o- Sepuluh hari kemudian … Ki Ragil Kuniran datang dengan si dukun bayi, Nyi Cendani. Tubuh kekar itu nampak berkeringat. Peluh membanjiri wajah dan tubuhnya ditambah dengan perasaan campur aduk tak karuan antara bahagia, tegang, senang dan bingung ‘tumplek blek’ menjadi satu. Ilmu lari cepatnya langsung dikerahkan semaksimal mungkin saat mendengar Nyi Salindri, sang istri merintih-rintih perutnya sakit dan terasa mulas. Dengan sigap dipondongnya Nyi Salindri, dan masuk ke dalam kamar, lalu diletakkan pelan ke atas pembaringan. “Aduh, Ki … perutku … sakit se … kali … “ Nyi Salindri berkata sambil terengah-engah. Perutnya terasa mulas sekali, mata membeliak-beliak seperti orang kesurupan setan. Ki Ragil hanya berdiri termangu-mangu. Tiba-tiba sebuah nama melintas dibenaknya. Nyi Cendani! “Tenang Nyi, sabar sebentar … aku panggilkan Nyi Cendani … ” “Cepat Ki … aku sudah tidak tahan … ” rintih Nyi Salindri sambil terus memegangi perutnya yang besar itu. Ki Ragil Kuniran segera menemui Mbok Inah, sang pelayan rumahnya. “Mbok, tunggui bendoro putrimu sebentar, aku mau menjemput Nyi Cendani!” Tanpa menunggu jawaban, Ki Ragil Kuniran langsung mblirit seperti orang dikejar setan. Gerakan langkah kakinya teratur dan mengikuti aturan-aturan tertentu. Larinya begitu ringan, laksana kapas tertiup angin. Rumah-rumah penduduk dilewati dengan cepat. Yang terlihat hanyalah sesosok bayangan hitam yang berkelebat dengan cepat. Dua penduduk desa yang dilewati seperti tersapu angin, matanya merem melek karena banyak debu yang mampir dimatanya. “Apa itu tadi?” tanya seorang penduduk dengan muka pucat. Tangan kirinya mengucal-ucal matanya yang kemasukan debu. “Entahlah … ” “Apa mungkin setan ya … ? Ataukah malah danyang desa ini?” tanya si muka pucat, matanya menjadi kemerah-merahan karena terlalu banyak debu yang masuk ke dalamnya. “Mana mungkin!! Setan tak mungkin keluyuran siang-siang begini, paling-paling cuman setan gundul, ha … ha … ha … ” bantah temannya. Sementara itu, Ki Ragil Kuniran sudah sampai di depan rumah Nyi Cendani. Nyi Cendani yang yang sedang tidur-tidur ayam sambil menikmati sepoinya angin, tentu saja kaget. Tanpa permisi, tanpa kata dan tanpa suara, tangan kanan Ki Ragil Kuniran langsung saya menyambar tubuh nenek kerempeng itu. Wutt … !! Plaakk … !! Tangan kekar itu ditepiskan dengan sebuah tepisan ringan, seperti mengibas lalat. Tangan tua itu sudah terlatih dengan gerakan–gerakan ilmu silat, tentu saja secara otomatis telah memunculkan tenaga tak kasat mata dari dalam tubuhnya yang langsung bereaksi jika ada serangan mendekat. Tubuh kekar itu terhuyung ke belakang. Tangannya seperti beradu keras dengan besi baja. Terasa ngilu dan linu sekali. “Dasar tua bangka cabul! Istri sudah bunting besar, masih coba-coba main gila dengan perempuan tua macam aku! Kurang ajar!” semprot Nyi Cendani dengan sengit. Air liur kemerah-merahan muncrat ke mana-mana, karena sambil tidur-tidur ayam tadi, nenek tua itu sedang mengunyah-ngunyah susur. Matanya melotot besar, dengan kedua tangan berkacak pinggang. “Maaf … maaf Nyi … buk … bukkkaaan … aku … ” Ki Ragil Kuniran berkata sambil tergagap-gagap. Napasnya memburu karena cemas, tegang, bingung dan kaget campur aduk menjadi satu. Cemas karena memikirkan rintihan Nyi Salindri yang perutnya terasa mulas. Tegang dan kaget karena dukun bayi itu bisa dengan mudah mengibaskan tangannya dan bisa membuatnya terhuyung-huyung beberapa langkah. Suatu hal yang aneh dan sukar diterima dengan akal. “Bukan apa? Sudah jelas kau … ” “Tunggu dulu Nyi! Sabar … sabar … biar kujelas … kan … !” “Sabar gundulmu itu!” Nyi Cendani masih terus saja bertolak pinggang, tentu saja mulutnya masih ‘bergulat’ dengan susur yang saat itu masih betah di dalam rongga mulut yang peot itu. “Istriku mau melahirkan … ” “Apaaa … ?!?!?!” Nyi Cendani berteriak dengan keras. Suara cempreng itu bagai menusuk-nusuk telinga Ki Ragil Kuniran. Kepala berdenyut-denyut, telinga berdenging, karena suara cempreng itu hanya berjarak sejengkal dari telinganya. “Kenapa tidak kau bilang dari tadi? Dasar suami edan!” “He-he-he … ” “Ditanya malah cengengesan,” sentak Nyi Cendani dengan mata melotot. Tubuh keriput itu langsung masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian sudah keluar sambil membawa buntalan kain kuning kusam. Meski sudah tua, langkah nenek itu tidak terhuyung-huyung layaknya orang yang sudah uzur. “Ayo berangkat!” “Kemana Nyi?” tanya Ki Ragil Kuniran, seakan lupa dengan tujuan semula datang ke gubuk dukun bayi itu. “Ke Akhirat! ******! Tentu saja ke rumahmu, bukankah kau datang ke sini karena istrimu mau melahirkan!?” bentak Nyi Cendani. “Oh … iya … aduh, aku lupa!” -o0o- Nyi Cendani datang bersamaan dengan Ki Ragil Kuniran, langsung menuju ke kamar dimana Nyi Salindri sedang mengerang-erang kesakitan. Perut istri lurah itu sudah membuncit besar dan kedua tangan itu terus saja memegangi perut besar berisi calon anaknya. Nyi Cendani segera memegang perut Nyi Salindri yang terasa mulas. Saat menyentuh perut besar itu, serangkum hawa sejuk menerpa perut dan pelan-pelan rasa mulas dan sakit semakin berkurang, beberapa saat kemudian hilang berganti rasa nyaman dan sejuk. Nyi Salindri sudah tidak merintih-rintih lagi. Ki Ragil Kuniran mendekati istrinya dan membelai rambut panjang yang terurai itu. “Bagaimana Nyi, apakah masih sakit perutmu?” “Tidak Kang. Perutku sudah agak baikan,” kata Nyi Salindri lirih. Ki Ragil Kuniran memegang telapak tangan kanan istrinya dengan lembut. Di bibirnya seulas senyum bahagia terpampang jelas. Sementara itu, Nyi Cendani sibuk mempersiapkan proses persalinan. Tangannya bergerak-gerak aneh seperti orang mengaduk. Jari telunjuk kiri dan kanan saling bertemu di depan dada. Matanya terpejam rapat, mulutnya komat-kamit seperti membaca mantera. Dengan gerakan pelan namun bertenaga, telunjuk yang saling merapat itu menyentuh pusar Nyi Salindri. Sebuah totokan pelan telah dilakukan. Srepp!! Tiba-tiba perut Nyi Salindri menggelinjang sendiri, seolah-olah di dalamnya ada sesuatu yang sedang menggeliat, kemudian diam tak bergerak. Nyi Cendani mengerutkan keningnya. Diulangi lagi totokan tadi, dan hasilnya seperti yang sudah-sudah. Biasanya jika sudah ditotok, perut menggelinjang keras dan tegang seperti orang mengejan, setelah itu proses persalinan akan berjalan dengan lancar sebagaimana biasa yang ia jalani. “Aneh … ” gumam Nyi Cendani. Pening kepala dukun bayi itu. Sebuah kejadian langka. Belum pernah selama ‘bertugas’ sebagai dukun bayi gagal membantu persalinan alias selalu tokcer. “Edan!” umpat Nyi Cendani, karena lagi-lagi usahanya gagal. “Edan? Siapa yang edan, Nyi?” tanya Ki Ragil Kuniran, heran. Nyi Salindri pun tertegun, pandangan matanya lincah mencari-cari sumber umpatan nenek itu. Tak ditemukan seorang pun di dalam kamar itu, kecuali mereka bertiga. “Anakmu! Anakmu itu ternyata masih betah berada di dalam perut ibunya,” terang Nyi Cendani. Mulut yang mengunyah susur itu makin lincah saja gerakannya. Mata tua itu jelalatan memandangi perut buncit Nyi lurah, seakan-akan sedang menaksir-naksir kapan isi dalam perut itu akan keluar. “Yang benar, Nyi? Nyi Cendani jangan main-main! Aku tidak suka itu!” kata Ki Ragil Kuniran agak meninggi. “Sudah jelas istriku mengandung selama sembilan bulan sepuluh hari, dan hari ini sudah saatnya melahirkan. Tapi Nyi Cendani mengatakan bahwa anakku belum mau lahir. Kenapa bisa begitu Nyi!?” Suara Ki Ragil Kuniran mulai meninggi dan matanya melotot besar. Nyi Salindri segera memegang tangan suaminya, karena dia tahu betul jika suaminya sudah berkata dengan nada meninggi dan mata mencereng begitu, ujung-ujungnya pintu regol itu bakal jebol ditendangnya. Kalau segera tidak ditenangkan, tidak hanya pintu regol, mungkin rumah pun bisa rubuh dalam sekejap mata! “Sudahlah Kang! Mungkin belum saatnya … ” “Belum saatnya … belum saatnya. Lha wong perut sudah gedhe begitu kok belum saatnya,” kata Ki Ragil Kuniran bersungut-sungut. “Ki Lurah, kita tunggu sampai besok … “ kata Nyi Cendani, dengan suara tidak enak hati. Tentu saja sebagai dukun bayi kelas kakap, gagal membantu persalinan akan mencoreng nama baik yang selama ini diukirnya. “Baiklah, kita tunggu sampai besok pagi. Silahkan Nyi Cendani istirahat di kamar depan, biar Mbok Inah yang mengatur ruangnya,” kata Nyi Salindri, dengan halus. “Kang Ragil, temani aku disini,” pinta Nyi Salindri pada suaminya. “Baiklah, aku juga sudah capek.” Hari demi hari, minggu berganti minggu, Nyi Salindri tidak juga melahirkan. Hal itu membuat Ki Lurah Watu Belah menjadi pusing tujuh keliling. Bayi biasanya akan lahir jika sudah berumur sembilan sepuluh hari, tapi bayi Nyi Salindri sampai bulan kedua belas, belum juga nongol dari perut sang ibu. Kabar tentang keanehan kandungan Nyi lurah sudah menyebar ke pelosok desa, bahkan sampai desa sekitarnya. Bahkan kepala desa Cluwak Bodas, Ki Sampar Angin, sahabat karib Ki Ragil Kuniran, seringkali bertandang ke rumah sahabatnya itu. Ki Sampar Angin datang bersama istri dan dua anak gadisnya yang sudah menginjak remaja, untuk menjenguk sahabat sekaligus memastikan kabar angin yang santer terdengar. -o0o-
Bab 2 “Apa maunya anak itu ngendon begitu lama di perut ibunya? Menyusahkan orang tua saja,” gerutu Ki Ragil Kuniran, teringat kehamilan istrinya yang sudah menginjak bulan ke tiga belas. Craakhh! Glarrr! Kilatan bunga api di langit menyadarkan kembali lamunannya. Matanya kembali menerawang ke atas, seakan-akan ingin menjenguk isi langit yang paling atas. Pandangan mata itu beralih ke arah timur, entah mengapa rasanya ia ingin berlama-lama memandang ke timur. Dari kejauhan terlihat setitik sinar putih terang, melayang ke arah barat dengan cepat. Makin lama makin kelihatan jelas bentuknya. Bayangan putih yang dilihat Ki Ragil Kuniran ternyata seekor burung elang dengan bulu putih keperakan. Besarnya dua kali elang biasa. “Elang?! Sejak kapan di Desa Watu Belah ada burung sebesar itu?!” tanya laki-laki itu dalam hati. Kepakan sayap elang itu begitu tenang dan berirama, seolah-olah sedang menunggang angin. Matanya yang tajam berputar-putar seakan sedang mencari mangsa untuk mengisi perutnya. Awwkkk! Awwkkk! Suara serak terdengar beberapa kali tiap elang itu mengepakkan sayapnya. Seluruh bulu elang berwarna putih keperakan dengan mata kemerahan bulat besar. Mata laki-laki parobaya itu berkunang-kunang karena bulu putih itu begitu menyilaukan karena memantulkan sinar matahari. Awwkkk! Awwkkk! Suara serak terdengar lagi. Elang itu berputaran tepat di atas kepala Ki Ragil Kuniran sejarak enam tombak, jarak yang cukup dekat bagi elang itu untuk melakukan sambaran terhadap mangsanya. Setelah melakukan beberapa putaran, tiba-tiba berputar balik setengah lingkaran seperti orang bersalto, lalu melesat ke arah Ki Ragil Kuniran dengan cepat. Wuss! Wutt! “Elang gila!” Ki Ragil Kuniran menghindar dengan membungkukkan badan, sambil tangan kanannya melakukan gerakan untuk menangkis serangan paruh tajam si burung elang. Wutt … ! Elang itu mengelak dengan memiringkan tubuhnya. Elang itu bergerak cepat menyelinap ke bawah ketiak kanan Ki Ragil Kuniran terus ke punggung, lalu dilanjutkan melesat ke atas melewati kepala sambil kakinya menyambar benda hijau kecil yang bergelayutan di ranting kecil tepat diatas kepala Ki Ragil Kuniran. Wess! Tap! Burung elang itu kembali melesat terbang ke atas dengan cepat. Kaki kekar itu mencengkeram makhluk kecil panjang kehijauan yang menggeliat-geliat ingin lepas. Elang itu melesat dengan cepat kearah barat sambil membawa buruannya. Aaawwkkk! Ki Ragil Kuniran terperangah. Bukan pada gerakan menyerang elang barusan, tapi benda bulat panjang kehijauan yang dicengkeramnya, ternyata adalah seekor ular berbisa! “Bukankah itu Ular Hijau Lumut yang beracun ganas? Sejak kapan pohon sawo kecik ini menjadi sarang ular?!” tanya Lurah Watu Belah dalam hati, sambil memutar badan melihat pada pohon sawo kecik di belakangnya yang cukup rimbun dan kebetulan sedang berbuah lebat. Tadinya ia mengira yang diserang elang adalah dirinya, sehingga dengan cepat menggerakkan tangan kanan untuk menangkis serangan elang. Akan tetapi begitu mengetahui serangan itu hanya untuk menyelamatkan dirinya dari patukan ular kehijauan itu, dia tidak jadi memaki burung elang tadi. Matanya yang tajam melihat kelebatan beberapa ular berwarna hijau diantara ranting dan daun pohon sawo kecik, meluncur dengan cepat. Gerakan ular itu begitu gesit bersembunyi, sebab melihat adanya bahaya dari burung elang yang menyambar kawannya barusan. “Hmmm, ular ini harus disingkirkan! Bahaya kalau sampai anak-anak bermain-main disini lalu dipatuk ular, bisa-bisa Nyi Cendani repot menyembuhkannya. Lebih baik kubunuh saja ular-ular itu,” gumam laki-laki itu sambil matanya memandang ke arah ular-ular itu. Ia lalu memandang berkeliling, mencari kerikil untuk menimpuk ular-ular yang hampir saja mencelakakan dirinya. Setelah menemukan kerikil-kerikil kecil, ia mulai menyentilkan jari tangan yang terisi kerikil ke arah ular yang ada di pohon sawo kecik itu. Ctik! Ctik! Blugh! Blugh! Dua ular terjatuh dengan kepala pecah, menggelepar-gelepar sebentar lalu mati. Ki Ragil Kuniran terus saja melakukan aksi ‘pembunuhan massal’ pada ular yang ada di pohon sawo kecik itu dengan kerikil. Sudah puluhan ekor ular jatuh ke tanah dan mati, akan tetapi ular-ular itu belum habis juga, bahkan makin lama banyak jumlahnya. “Gila! Betul-betul sarang ular pohon sawo ini, kalau begini terus bisa sampai semalaman! Kalau ada warga desa, pasti cepat beres. Tapi kalau kutinggal, jangan-jangan ular-ular itu malah pergi dan menyerang Desa Watu Belah. Wah, bisa hancur desaku! Pasti disini ada ratu atau raja ularnya. Kalau rajanya tertangkap, yang lainnya gampang diusir, lebih baik kucari saja rajanya!” gumam Ki Ragil Kuniran. Laki-laki berbaju hitam itu mengelilingi pohon sawo kecik itu dengan mata jelalatan mencari ‘pimpinan’ kawanan ular itu. Tangan kirinya masih memegang kerikil yang siap mengantar nyawa ular-ular itu ke alam kematian. Rupanya apa yang dikhawatirkan Ki Ragil Kuniran menjadi kenyataan. Di dahan yang paling besar, bertengger seekor ular hijau lumut seukuran lengan orang dewasa dengan panjang hampir mencapai tiga tombak, sedang melingkar. Matanya mencorong dengan lidah kemerahan yang selalu menjulur-julur keluar, sisiknya berwarna belang hijau kekuningan. Dikepalanya ada daging tumbuh layaknya makhota seorang raja. Ular-ular hijau lumut itu seakan menunggu titah dari ‘sang raja’ untuk menyerang lawan. Lidah raja ular kembali menjulur-julur, seakan memberi perintah dengan suara desisan yang keras. Sssshhhh!!! Seperti dikomando, ular-ular itu merayap ke bawah, bahkan yang agak besar langsung menjatuhkan diri ke tanah. Mereka berdesak-desakan keluar dan turun dari pohon sawo kecik itu. Pohon itu seakan bukan pohon sawo kecik lagi, tapi lebih mirip pohon ular hidup. Jumlah ular itu ratusan banyaknya, bahkan mungkin mencapai ribuan ekor, besar kecil saling berlomba mengejar sasaran yang sama, yaitu orang yang telah membunuh teman atau pun saudara mereka! Ki Ragil Kuniran yang tidak menyangka akan diserang ular-ular hijau lumut itu, kaget bukan kepalang. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu sudah terkepung ratusan ular yang jumlah ribuan ekor, termasuk raja ular itu juga turun dari atas dahan. “Gila! Apa-apa’an ini?” Sssshhhh!!! Sssshhhh!!! Suara mendesis ribuan ular hijau lumut seakan sebagai tanda protes atau kecaman bagi Ki Ragil Kuniran, dan mungkin juga jawaban dari pertanyaan Ki Ragil. Bersamaan dengan itu, ular-ular itu langsung menerjang maju. Ada yang langsung berusaha mematuk kaki, yang agak besar mengincar mata dan ada juga yang membokong dari belakang! Sssshhhh!!! Laki-laki baju hitam itu tidak mau dirinya menjadi santapan ular. Baru pertama kali dalam hidupnya, dia bertarung dengan ular yang jumlahnya mencapai ribuan ekor, sehingga keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tubuh kekar itu berkelebat. Ilmu silat dan ilmu ringan tubuh dikerahkan untuk menghindari serangan ular, bahkan hawa tenaga dalam digunakan mencapai sepuluh bagian. Akibatnya sungguh dahsyat. Setiap sapuan kaki atau tamparan tangan bahkan kepalan tinjunya selalu membawa maut. Wutt! Plakk!! Ular-ular yang kena tendangan, tamparan bahkan kepalan pasti mati. Kalau tidak kepalanya pecah, pasti perutnya jebol atau terbelah menjadi dua! Sungguh mengerikan pertarungan antara dua makhluk yang berbeda jenis itu. Satu manusia melawan ribuan ular beracun! “Heeaaaa … !!” Teriakan mengguntur menambah semangatnya dalam menghadapi serbuan ular-ular beracun. Tubuh kekar itu semakin cepat berkelebat. Plakk … ! Bukk … ! Prak … !! Sepuluh ekor ular yang cukup besar, mati dalam sekali kibas, tiga dengan kepala pecah, dua dengan perut jebol dan lainnya dengan tubuh terbelah dua. Tiba-tiba, sekelebat bayangan hijau panjang menerjang dengan gerakan kilat. Gerakan itu diketahui Ki Ragil Kuniran dengan sudut matanya. Dengan cepat bersalto ke belakang, sambil tangan kirinya yang penuh dengan kekuatan tenaga dalam bergerak menampar, akan tetapi bayangan hijau itu meliuk ke bawah, sambil mengibaskan ekornya ke arah kepala lawan. Melihat bayangan itu mengincar kepalanya dalam keadaan berjungkir balik seperti itu membuat Ki Ragil Kuniran gugup. Kepalanya mengegos ke kanan, tapi serangan itu masih sempat menyerempet pipi kanannya. Prattt!! “Ukh!” Laki-laki itu mengeluh. Pipinya terasa panas dan pedas, diikuti dengan rasa gatal kemudian pipinya terasa menebal. Tubuhnya melayang ke kiri akibat sampokan bayangan hijau tadi. Melihat jatuhnya tepat pada kumpulan ular yang seakan sudah menyambutnya, laki-laki parobaya itu masih dalam keadaan melayang, menggerakkan ke dua tangannya menyilang lalu menghentakkannya ke depan. Blarr … !! Serangkum hawa panas berwarna putih pekat yang bersumber dari hawa tenaga sakti itu, mengeluarkan suara keras saat mengenai kerumunan ular yang siap menyambut tubuhnya. Tanah tempat ular-ular tadi membentuk cekungan lebar yang dalam akibat terkena serangan tenaga dalam putih pekat tadi. Tubuh ular-ular itu hancur dedel duwel berserakan di tanah dan tercium bau hangus yang amis. Jleg! Tubuh kekar itu berdiri tegak, tepat di mana ia tadi membuka jalan bagi dirinya dengan melancarkan pukulan mematikan. “Ular keparat!” maki Ki Ragil Kuniran saat ia meraba pipi kanannya yang kini gembung bengkak karena racun yang ada di ekor raja Ular Hijau Lumut. Kepalanya senut-senut, gigi kiut-kiut karena saking linu dan kerasnya racun. “Racunnya cepat sekali menjalar, harus segera diatasi,” batinnya. Ia cepat mengalirkan tenaga dalam ke jalan darah di sekitar leher dan otak belakang, agar racun itu tidak menjalar kemana-mana, lalu merogoh saku baju dan mengambil sebutir pil berwarna hitam dan langsung menelannya. Rasanya pahit dan baunya sengat seperti kotoran kambing. Rupanya bayangan hijau tadi adalah ular bermahkota yang marah karena melihat ‘pasukan’-nya tidak berdaya melawan musuh. Sssshhhh!!! Kembali terdengar desisan keras, untuk kesekian kali dari ular bermahkota. Sebenarnya bisa saja Ki Ragil Kuniran keluar dari pertarungan aneh itu, tapi melihat banyaknya jumlah dan ganasnya racun ular, ia tidak ingin warga desa menjadi korban dari gigitan ular hijau lumut ini, apabila ular-ular itu menyerang desa Watu Belah, lebih baik dihadapi sendiri meski dengan taruhan nyawa. Tiba-tiba dari arah barat, terdengar suara serak yang membahana. Suara yang sudah dikenal Ki Ragil Kuniran, suara burung elang! Awwkkk! Awwkkk! Rupanya elang putih keperakan yang tadi terbang sambil membawa seekor ular hijau lumut kembali lagi. Tapi kini tidak hanya sendirian, tapi dengan puluhan bahkan ribuan kawanan elang lainnya, ada yang berwarna hitam, coklat, bahkan burung pemangsa bangkai pun ikut bergabung. Diantaranya ada seekor elang hitam berkepala botak, namun besarnya lebih kecil dari elang putih keperakan. Ular adalah musuh bebuyutan elang dan sekaligus santapan lezat bagi jenis burung pemangsa ini. Rupanya saat mengitari Ki Ragil Kuniran, elang putih keperakan melihat bahwa di pohon sawo kecik terdapat sarang ular yang jumlah ribuan ekor banyaknya. Ular bermahkota mendesis-desis. Lidah merahnya yang bercabang dua bergetar dengan hebat, melihat kawanan elang yang terbang makin mendekat. Tak ada waktu baginya untuk meloloskan diri, kecuali bertarung mati-matian! Sssshhhh!!! Ular-ular yang lain menyahut dengan mengeluarkan desisan sama. Kepala menegak dengan mulut menganga lebar, lidah menjulur-julur sambil menetes-neteskan cairan racun berwarna putih bening. Siap menerima tantangan kawanan elang! Ki Ragil Kuniran masih terpaku di tempatnya melihat kejadian itu. Sungguh menakjubkan! Awwkkk! Kembali suara serak elang putih keperakan membelah angkasa, kali ini lebih keras dari yang tadi. Kawanan elang yang di belakangnya sontak mengikuti dengan suara serak yang bersahutan, seakan menerima perintah dari atasannya. Kaakh! Kaakh! Kaakh! Awwkk! Hampir bersamaan, kawanan elang itu meluncur ke bawah, mengincar kawanan ular-ular yang mengurung Ki Ragil Kuniran. Wutt! Wutt! Crakk!! Crokk! Pletak … ! Perang campuh pun terjadi. Perang yang sungguh aneh dan mungkin paling langka di dunia pun terjadi. Pertarungan antara kawanan elang dengan kawanan ular! Saling mematuk, belitan ular yang sanggup meremukkan tulang, kelebatan cakar dan kepakan sayap elang, campur baur menjadi satu dengan suara desisan ular dan pekikan elang. Ular mengandalkan racun dan belitan yang kuat, sedang elang mengandalkan ketajaman paruh dan cakar tajam serta kegesitan terbang dalam menghindari semprotan racun. “Sungguh menakjubkan! Mungkin di dunia ini hanya aku yang melihat keganjilan seperti ini. Perang tanding yang aneh,” kata Ki Ragil Kuniran, pada dirinya sendiri sambil menggeleng-gelengkan kepala. “Lebih baik, kubantu kawanan elang itu,” katanya lagi. Kepalanya mendongak ke atas, melihat burung elang putih keperakan yang masih melayang-layang di angkasa. Mata tajam itu sedang mencari-cari sesuatu di antara kawanan ular itu. “Sobat di atas, terima kasih atas bantuannya! Biar kubantu kawan-kawanmu! Kau hadapi saja raja ular itu, kulihat dia berada di sisi kirimu,” teriak Ki Ragil Kuniran dengan keras. Tangannya menuding ke arah timur, tempat dimana ular bermahkota kini berada. Awwkkk! Awwkkk! Suara elang putih keperakan terdengar kembali, kali ini lebih pelan mungkin sebagai jawaban darinya. Elang itu segera berkelebat ke arah timur. Elang putih keperakan merangsek dari atas. Paruh setajam pedang siap di hunjamkan ke kepala lawan. Ular bermahkota tidak mau mandah begitu saja, segera menggelung tubuh dengan cepat, menyembunyikan tubuhnya yang panjang dari terjangan lawan yang menyerang dari atas. Hanya kepalanya yang menyembul keluar, sambil mendesis-desis keras diiringi dengan goyangan kepala ke kiri kanan untuk mengecoh musuh. Crass! Cakar elang putih keperakan menyerempet bagian tengkuk meninggalkan bekas sayatan memanjang. Ular itu kembali mendesis marah. Sssshhhh!!! Kepala ular bergerak menyambar kaki elang dari bawah. Sratt!! Elang putih keperakan mengelak ke kiri sambil mengepakkan sayap dengan keras ke arah mata lawan. Plakk! Kepala ular terpelanting ke kanan. Badan yang tergelung itu ikut terbawa karena kerasnya sampokan. Pertarungan antara dua makhluk berlainan jenis dan bentuk itu terus berlangsung seru. Mencakar dan mematuk silih berganti, suara desisan dan pekikan elang terdengar di arena pertarungan. Bulu-bulu elang dan bangkai ratusan ular berserakan dimana-mana. Sementara itu, Ki Ragil Kuniran yang ‘dibantu’ kawanan elang, menerjang gerombolan ular hijau lumut. Laki-laki itu tidak sesibuk sebelumnya, walau pun setiap tendangan maupun pukulan selalu membawa maut. Prak! Bugh! Empat ular berkelojotan, lalu mati dengan kepala pecah. Menjelang sore, seluruh kawanan ular telah tumpas tapis tanpa tersisa sedikit pun. Bau amis menyengat hidung Ki Ragil Kuniran. Perutnya serasa diaduk-aduk mau muntah. Pada saat yang sama, elang putih keperakan melesat ke atas beberapa tombak, lalu menukik ke bawah dengan paruh siap dihunjamkan ke arah kepala lawan. Wuss! Ular bermahkota mengelak dengan merendahkan kepala sejajar tanah, diiringi suara mendesis-desis keras. Sssshhhh!!! Serangan elang putih meleset. Elang putih keperakan langsung berbalik ke kanan dengan cepat. Ular bermahkota tidak menduga kalau lawan bisa memutar diri dengan gerakan aneh dan langsung mengincar kepala bagian belakang! Crokk! Paruh elang menancap kuat, bahkan sampai tembus ke depan. Ular bermahkota berkelejotan meregang nyawa diiringi desisan kematian. Sssshhhh!!! Tubuhnya menggulung badan elang putih keperakan dengan cepat. Elang putih itu diam saja, sambil paruhnya digerak-gerakkan ke atas ke bawah seakan mengambil sesuatu. Plasss! Elang putih keperakan mencabut paruhnya dari kepala lawan yang meregang nyawa. Diparuhnya terdapat benda bulat putih kekuning-kuningan, langsung ditelan dengan cepat. Bersamaan dengan itu, ular bermahkota juga tergeletak tak bernyawa. Mati! Kemenangan sang pemimpin, disambut dengan teriakan membahana dari kawanan elang. Awwkkk! Kragh! Kaakkhh … ! Elang putih keperakan kembali terbang ke atas dan melayang berputaran di udara, merayakan kemenangan ditingkahi suara serak yang menggelegar. Kawanan elang mengeluarkan pekikan-peikikan nyaring, sehingga suasan di sekitar di tempat itu riuh rendah tak karuan. Tiba-tiba … Wutt! Elang putih keperakan berputar cepat dan menukik ke bawah, ke arah bangkai ular bermahkota. Ki Ragil Kuniran yang merasakan angin sambaran yang kuat menerpa dirinya, segera membuang diri ke belakang. Elang putih keperakan itu menyambar bangkai ular dengan sepasang cakarnya yang tajam, lalu melesat terbang ke arah matahari terbit dengan pekikan tinggi melengking. Kawanan elang yang lain, mengikuti perbuatan sang pemimpin, menyambar bangkai-bangkai ular yang berserakan di tanah, sehingga sekitar pohon sawo kecik yang pada mulanya sebagai ajang pertarungan antara kawanan elang dengan kawanan ular, kini sebagian besar telah bersih dari bangkai ular. Sisanya masih berserakan tak karuan disana-sini. “Sobat, terima kasih atas bantuannya,” teriak Ki Ragil Kuniran, yang sesaat terpana melihat pangeram-eram yang dibuat oleh kawanan elang. “Pasti elang putih keperakan itu memiliki majikan atau suatu tempat tinggal yang setidaknya berdekatan dengan manusia. Tidak mungkin seekor burung bisa paham perkataan manusia kalau tidak ada yang mengajarinya atau setidaknya burung elang itu akrab dengan manusia. Kalau aku bertemu dengan pemilik elang itu, mungkin aku tidak bisa membalas kebaikannya,” gumam laki-laki parobaya itu. “Lebih baik kubersihkan tempat ini, perutku mual memcium bau amis yang menyengat. Kubuat saja lubang yang besar disini.” Dari arah selatan, seorang bocah kecil berumur kurang lebih sepuluh tahun berlari dengan cepat. Napasnya terengah-engah. Berbadan ceking dengan keringat bercucuran membasahi muka dan dadanya yang telanjang. Celananya hitam komprang, agak kedodoran. Dilehernya tergantung sebentuk ketapel atau blandring dari kayu jati. “Ki Ragil … Ki Ragiiil … Ragiiil … ” Laki-laki yang dipanggil, segera menoleh. Ki Ragil Kuniran kenal betul dengan suara itu, matanya memandang ke arah selatan dengan dahi berkerut. “Ada apa Gineng memanggilku? Apa kawanan ular juga nglurug ke desa?” batin Ki Ragil Kuniran, lalu melompat keluar dari lubang galian. Ia menghentikan pekerjaannya membuat sebuah yang cukup lebar dan dalam. Meski hanya menggunakan tangan, namun kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya ikut ambil bagian, sehingga setiap kedukan atau songkelan tangan ibarat cangkul dan linggis. Bocah kecil yang disebut Gineng melihat orang yang dicarinya berada di bawah pohon sawo kecik, wajahnya langsung sumringah, langsung berlari mendekat ke arah orang dicarinya. “Ada apa Gineng? Kenapa kamu berteriak-teriak seperti orang kesurupan? Apa kamu disuruh simbokmu?” tanya Ki Ragil Kuniran. “Betul, Ki! Saya disu … ruh sim … bok untuk mencari Ki … lurah,” kata Gineng sambil ngos-ngosan. “Kamu disuruh apa sama simbokmu?” tanya Ki Ragil Kuniran, sambil bersandar pada pohon sawo kecik. Mukanya licin berkilat-kilat karena mandi keringat sedangkan pipi yang terkena sabetan ekor ular sudah sembuh berkat obat anti racun yang ditelannya, meski tampak sedikit lebam. “Anu … itu … Ki … Hehh … ” “Anumu kenapa? Bicara yang jelas!” “Istri Ki Ragil mau melahirkan!” kata Gineng setelah menghela napas dalam-dalam. “Istriku mau melahirkan? Kamu jangan main-main, Gin! Apa Nyi Cendani juga ada?” tanya Ki Ragil Kuniran. Sudah seringkali dia oleh dikabari Gineng kalau istrinya mau melahirkan, tapi kenyataannya ketika sampai di rumah, istrinya tidak melahirkan, malah sedang enak-enakan ngobrol sama dukun beranak itu! “Betul, Ki! Nyi Cendani juga bilang begitu! Katanya hari ini pasti melahirkan, karena … karena … air ketubannya sudah pecah. Begitu kata Nyi Cendani yang saya dengar,” ucap Gineng nyerocos begitu saja. “Air ketubannya sudah pecah!?” gumam laki-laki parobaya itu. Tiba-tiba kepala desa Watu Belah itu teringat sesuatu. “Baiklah! Aku akan ke rumah. Semoga saja hari ini anakku benar-benar lahir! Tolong kau lanjutkan pekerjaanku, nanti upahnya seperti yang kemarin, aku ajari kau jurus silat yang baru,” kata Ki Ragil Kuniran, sambil menepuk-nepuk pundak Gineng, lalu berkelebat ke arah selatan, ke arah desa Watu Belah! Wuss! “Baik, Ki! Pokoknya beres!” seru Gineng, tanpa bertanya ‘pekerjaan’ apa yang harus dilanjutkannya. Setelah bayangan Ki Ragil Kuniran lenyap di tikungan jalan, Gineng segera berjalan mendekati lobang galian yang dibuat Ki Ragil Kuniran. “Walaah … buat apa Ki lurah membuat lubang begini besar? Apa untuk mengubur gajah, ya? “ gumam Gineng. Matanya yang besar jelalatan mencari cangkul atau linggis. Namun yang ditemukan bukan linggis atau pun cangkul, tapi ratusan bangkai ular yang berserakan tak tentu arah! “Kok disini banyak bangkai ular? Pasti ini perbuatan Ki lurah! Mungkin ini pekerjaan yang harus kulanjutkan tadi. Hemmm, baiklah!” gumamnya lagi. Ketika membungkuk, tiba-tiba perut kecilnya berbunyi. Krucukkk! Kriiyukk! “Wah, perutku minta diisi nih! Tadi aku tidak sempat makan, sudah disuruh simbok mencari Ki Ragil! Lebih baik, aku makan saja buah sawo itu, lumayan untuk mengganjal perut, baru mengurus bangkai ular itu!” katanya.
Bab 3 “Bagaimana Nyi? Sudah mau keluar?!” tanya seorang laki-laki berpakaian hitam bercelana hitam komprang dengan ikat pinggang merah menyala, saat melihat seorang wanita tua keluar dari biliknya. Laki-laki berwajah bersih berbadan kekar itu tak lain adalah Ki Ragil Kuniran, kepala desa Watu Belah. “Entahlah Ki! Aku sendiri juga dibuat bingung oleh anakmu! Seharusnya sudah keluar dari tadi, tapi sampai menjelang tengah malam begini, tidak keluar-keluar juga. Padahal air ketuban istrimu sudah pecah dari tadi. Aku takut terjadi apa pada bayimu. Ilmu pengobatan yang kumiliki juga tidak ada gunanya,” keluh Nyi Cendani. Semua orang yang berada di ruangan itu terdiam, dengan pikiran berkecamuk. Ki Ragil Kuniran kembali duduk di kursi tempat biasanya ia bersantai. Matanya menerawang jauh, entah apa yang dipikirnya. “Pasti ada hubungannya dengan mimpi itu,” gumamnya lirih. Walaupun lirih, telinga semua orang yang berada di situ, mendengar jelas gumaman laki-laki nomor satu di desa Watu Belah. Seorang laki-laki berbaju lurik dengan blangkon bertengger di kepala, mendekat dengan kening berkerut. Dialah yang bernama Ki Sampar Angin, kepala desa Cluwak Bodas. “Mimpi apa, Adi Kuniran?” tanya Ki Sampar Angin, sambil duduk di depan kursi sahabatnya. “Cuma mimpi biasa saja, Kakang Sampar Angin,” kata Ki Ragil Kuniran, pendek. “Kalau Adi Kuniran tidak keberatan, apa boleh saya tahu mimpi apa yang Adi Kuniran temui,” ucap Ki Sampar Angin, meyakinkan, “mungkin saja itu bukan mimpi biasa.” Semua orang yang ada disitu memandang laki-laki berbaju hitam itu dengan pandangan memohon. “Baiklah,” kata Ki Ragil Kuniran setelah menimbang-nimbang beberapa saat. “Akhir-akhir ini, aku sering mimpi aneh, Kakang Sampar Angin! Dalam mimpiku, aku ditemui seorang kakek yang sudah sangat tua sekali, berjubah putih berbulu, seperti bulu burung berwarna putih keperakan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keperakan, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kakek itu mengatakan sesuatu padaku, seperti sebuah syair atau sebuah pesan, tapi aku sendiri tidak begitu paham artinya.” “Apa isi dari sesuatu yang Adi sebut sebagai ‘syair’ itu tadi?” Setelah termenung beberapa saat, Ki Ragil Kuniran menjawab pertanyaan itu. “Isi seperti ini : ‘Cucuku, aku adalah Sang Angin! Aku memilih anakmu sebagai Pewaris Tahta Angin, yang akan membersihkan seluruh duri di muka bumi. Angin kecil-lah yang akan mewarisi kekuatan Sang Angin. Penunggang Angin akan menjadi pertanda kelahiran Pewaris Tahta Angin di dunia pada bulan ke tiga belas purnama sidhi. Jagalah dia baik-baik. Aku hanya bisa memberikan Telapak Tangan Bangsawan sebagai rasa terima kasihku padamu, yang akan kuberikan bersamaan dengan munculnya si angin kecil dan Penunggang Angin’. Itulah yang dikatakan kakek itu dalam mimpiku,” kata Ki Ragil Kuniran, lalu lanjutnya, “Setelah itu, kakek berjubah bulu burung itu seperti melemparkan cahaya putih keperakan dari tangan kanannya ke arah perut istriku, diiringi dengan suara deru angin membadai dan suara gelegar petir, mirip dengan deru badai yang pernah kita lihat di Pantai Selatan. Mimpi itu selalu datang padaku berturut-turut. Itulah mimpi yang kualami, Kakang Sampar Angin! Pada mulanya aku berpikir itu cuma kembang tidur saja, tapi setelah kejadian tadi siang, aku mulai memikirkan kebenaran dari mimpiku itu.” “Kejadian? Kejadian apa Adi?” desak Ki Sampar Angin. “Perkelahian antara kawanan burung dengan kawanan ular.” “Burung apa? Ular apa? Jelaskan yang benar, Ki lurah,” Nyi Cendani kini yang bertanya. “Pertarungan ganjil antara elang putih keperakan dengan ular hijau lumut.” jawab Ki Ragil Kuniran. Semua orang yang mendengar cerita tentang mimpi itu terkesima, seolah terhipnotis. Sungguh aneh dan sulit dimengerti apa arti dari mimpi Ki Ragil Kuniran itu. Semua tercenung memikirkan arti mimpi itu. Gineng yang sedari tadi duduk di pojok ruangan sambil mendengarkan cerita Ki Ragil Kuniran, manggut-manggut. Tahulah ia bahwa bulu-bulu yang ditemuinya berserakan itu adalah bulu elang, sedangkan bangkai ular yang telah dikuburkan tadi adalah bangkai ular hijau lumut! “Oh … bulu burung elang to. Kukira tadi bulu ayam, he-he-he … ” gumam Gineng. “Apa ada to, Gin, kok ndremimil kayak begitu,” ucap simboknya, lirih. Yang ditanya hanya tertawa cengengesan saja. Nyi Cendani mendengar disebutnya Ular Hijau Lumut, melengak kaget! Ular Hijau Lumut adalah ular yang selalu hidup berkelompok, jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu dalam satu kelompok. Setiap kelompok akan memiliki seekor ular bermahkota dengan panjang kurang lebih empat hingga lima tombak. Seluruh tubuh ular itu beracun ganas dan mematikan. Satu tetes racun ular hijau lumut bisa membunuh orang dalam waktu sekian detik. Apabila ular itu berada di sungai atau danau, bisa dipastikan hewan-hewan air akan mati keracunan! Untunglah gurunya, si Iblis Botak, telah membuat semacam obat pemunah untuk mengatasi ganasnya racun Ular Hijau Lumut, yang bahan utamanya dari Empedu Beruang Salju yang dikeringkan. Bahkan mustika ular yang ada di kepala ular bermahkota itu, menurut gurunya bisa menaklukkan ular dari jenis apa pun. “Apa Ki Ragil selalu membawa obat pemunah racun yang saya berikan tempo hari?” tanya Nyi Cendani, dengan mimik serius. “I … ya, Nyi! Bahkan aku telah menelannya dua butir saat bertarung dengan ular yang bermahkota,” kata Ki Ragil Kuniran. “Ular bermahkota juga ada? Dimana sekarang? Apa masih hidup?” seru Nyi Cendani, dengan wajah berbinar-binar. “Sudah mati.” “Bangkainya dimana?” kejar Nyi Cendani, seraya melangkah mendekat. “Sebagian besar dari bangkai ular sudah dibawa pergi oleh elang-elang itu, termasuk juga ular bermahkota itu,” kata Ki Ragil Kuniran. “Uh … sayang sekali!” keluh Nyi Cendani. Nenek itu terdiam. Suasana di ruangan itu kembali lengang, yang terdengar hanyalah helaan napas dalam-dalam. Ki Ragil Kuniran kembali tenggelam dalam lamunan, demikian juga dengan Ki Sampar Angin, pikirannya mengembara mencari tahu siapa gerangan kakek berjubah putih berbulu burung yang diceritakan oleh sahabat karibnya itu. “Rasa-rasanya, aku pernah mendengar ciri-ciri itu. Kakek berjubah putih berbulu burung, dengan tubuh memancarkan cahaya keperakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki!? Aku yakin pernah mendengarnya. Tapi kapan dan dimana? Andaikata guruku atau ayahku masih hidup, tentu tahu siapa tokoh yang memancarkan cahaya keperakan itu. Áh … pusing aku!” pikirnya. Di saat semua orang sedang berkecamuk dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba dari luar terdengar desau angin yang ganjil. Malam itu sedang bulan bulat penuh, yang semula sunyi sepi hanya terdengar suara jengkrik dan serangga lain, kini berubah suara dengan lirih dan akhirnya berhenti sama sekali. Angin malam semakin lama semakin meningkatkan alirannya. Suara desir yang tidak seperti biasanya, menggugah Ki Ragil Kuniran dari lamunan panjang. “Angin ini … sama persis dengan suara angin yang kurasakan dalam mimpiku,” desisnya lirih. Semua orang tercenung mendengar desisan lirih itu. Tiba-tiba saja, terdengar pekikan nyaring dari atas wuwungan rumah … Awwkkk! Awwkkk! “Pekikan elang!” gumam Ki Sampar Angin, mengenali suara nyaring melengking yang meningkahi desiran angin yang semakin meningkat tajam. Ki Ragil Kuniran segera bergegas keluar, diikuti dengan yang lain, kecuali Gineng yang sudah terlelap tidur di atas dipan. Lurah desa Watu Belah itu sampai di halaman, lalu memandang ke atas wuwungan rumah. Semua orang melihat sebentuk makhluk yang memancarkan cahaya putih keperakan karena tertimpa cahaya bulan purnama, yaitu satwa penguasa angkasa, burung elang yang berbulu putih keperakan! “Itulah elang yang kuceritakan tadi, Kakang Sampar Angin,” kata Ki Ragil Kuniran. “Elang putih keperakan yang bertarung dengan ular bermahkota tadi siang.” Elang berbulu putih keperakan itu bertengger di atas wuwungan rumah dengan gagah. Tidak seperti tadi siang yang memimpin kawanan elang saat bertarung dengan gerombolan ular, sekarang elang itu datang sendirian. Bulu putih berkilauan terkena pantulan cahaya bulan purnama. Angin yang semula meningkat tajam, sontak hilang dan berganti dengan hawa dingin menusuk tulang. hawa ini terlalu dingin untuk ukuran desa yang letaknya memang berada di kaki gunung. “Kenapa hawa jadi dingin membeku begini,” gumam kepala desa Cluwak Bodas, Ki Sampar Angin. Tanpa diperintah, seluruh hawa tenaga dalam yang dmilikinya perlahan mengaliri seluruh tubuh, mendesak hawa dingin yang semakin pekat. Sedikit demi sedikit hawa dingin membeku dapat ditekan seminimal mungkin. Tindakan Ki Sampar Angin diikuti semua khalayak yang hadir disitu. Nyi Cendani, Ki Ragil Kuniran dan dua orang Jagabaya melakukan hal yang sama. Hanya dua orang Jagabaya yang tenaga dalamnya agak rendah. Tubuh mereka berdua langsung menggigil kedinginan. Gigi berkerotokan, seluruh tulang rasanya menciut, wajahnya pias memucat. Nyi Cendani beringsut ke belakang dua Jagabaya, lalu menempelkan dua tapak tangannya ke punggung dan mengalirkan hawa panas ke dalam tubuh mereka berdua. Tak berapa lama, dua orang itu sudah bisa mengatasi hawa dingin membeku. “Terima kasih, Nyi Cendani,” ucap salah seorang diantara Jagabaya yang bertubuh gempal. Nenek dukun bayi itu hanya mengangguk pelan. Mata tuanya memandang burung elang berbulu putih itu dengan seksama, termasuk juga orang-orang yang ada di pelataran rumah. Ki Sampar Angin manggut-manggut, sambil mengelus-elus jenggot kelabunya yang panjang. “Menurutku, mungkin burung itu yang dimaksud dengan ‘Penunggang Angin’, Adi Kuniran,” kata Ki Sampar Angin tanpa menoleh ke arah Ki Ragil Kuniran yang berdiri di sampingnya. “Betul Kakang. Aku juga berpikir sama! Aku yakin bahwa yang dimaksud dengan Penunggang Angin adalah elang putih keperakan itu,” sahut Ki Ragil Kuniran. Tiba-tiba, terdengar sebuah suara tanpa wujud yang menggema di tempat itu. Suara seorang kakek! “Cucuku, Ragil Kuniran! Sudah tiba saatnya anakmu lahir ke dunia! Aku telah memilihnya sebagai pewaris Tahta Angin. Sebagai seorang pewaris, maka seluruh apa yang kumiliki akan menjadi milik anakmu. Aku minta kepadamu, jagalah pewarisku dengan sebaik-baiknya. Selain kau dan istrimu, Si Perak juga akan menjaga dan mengasuh anakmu! Dan aku minta, berilah nama anakmu Paksi Jaladara.” Suara itu menggema di seantero tempat itu. Ki ragil kuniran yang selama ini diliputi dengan rasa penasaran terhadap mimpinya, tidak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. “Maaf, jika boleh saya tahu, siapa Andika ini sebenarnya? Dan mengapa memilih anakku sebagai pewaris?” tanya Ki Ragil Kuniran, dengan rasa ingin tahu yang menyala-nyala. “Ha-ha-ha-ha … ! Sebenarnya aku malu mengatakan siapa diriku. Baiklah, karena kau yang meminta, kau boleh menyebutku Si Elang Berjubah Perak! Perkara aku memilih anakmu sebagai pewaris, hanya Hyang Widhi yang tahu! Biarlah nanti waktu yang akan menjawabnya! Sudahlah, waktuku tidak banyak! Sebagaimana janjiku padamu, terimalah ‘Telapak Tangan Bangsawan’ sebagai rasa terima kasihku. Selamat tinggal … !” Suara tanpa rupa, yang menyebut dirinya Si Elang Berjubah Perak, menghilang. Seolah tertelan kegelapan malam dan terangnya rembulan. Suasana kembali menjadi sunyi. Udara kembali normal, tidak dingin membeku seperti sebelumnya. “Si Elang Berjubah Perak,” gumam Nyi Cendani. “Rasa-rasanya aku pernah mendengar nama tokoh itu dari guruku, tapi siapa dia? Tapi aku yakin, dia adalah tokoh golongan putih. Ki Ragil, apa kau tahu siapa dia?” Yang ditanya hanya diam saja. Matanya terpejam dengan kepala tertunduk. Telapak tangannya menegang kencang terselimuti cahaya tipis kuning keemasan. Semua yang hadir di situ menjauhi Ki Ragil Kuniran sambil memandang heran. “Apa ini yang namanya ‘Telapak Tangan Bangsawan’?” gumam Nyi Cendani, lirih. Semua orang juga bertanya-tanya dalam hati, apa yang sedang dialami oleh Ki Ragil Kuniran saat ini? Dalam pada itu, Ki Ragil Kuniran merasakan hawa panas menyengat menjalar melalui telapak kakinya. Seolah-olah di bawahnya adalah tungku pembakaran yang panas membara. Tangan terkepal mengencang keras, dimana cahaya tipis kuning keemasan semakin lama semakin menebal hingga menjalar sampai pergelangan tangan dan naik sampai siku. Di dalam daya nalarnya, terngiang sebuah suara yang bernada memerintah, suara Si Elang Berjubah Perak. Rupanya Si Elang Berrjubah Perak tidak benar-benar pergi dari tempat itu, dan suaranya cuma Ki Ragil Kuniran saja yang mendengar! “Cucuku, serap hawa ‘Gaib Inti Panas Bumi’ itu dan alirkan menuju telapak tanganmu. Satukan dengan hawa sakti yang ada di pusar. Tarik terus ke atas hingga semua berkumpul di telapak tanganmu! Bagus, bagus! Ya, seperti itu!” Ki Ragil Kuniran mengikuti perintah Si Elang Berjubah Perak. Kekuatan gaib ‘Inti Panas Bumi’ terus menjalar dari pusar terus ke sekujur tubuh dan akhirnya mengalir ke telapak tangan, sehingga cahaya kuning keemasan tampak semakin jelas terlihat. “Bagus! Geser kaki kiri ke belakang dan tarik kedua tangan sampai di samping pinggang. Sekarang … hentakkan kaki kanan ke bumi dan dorong kedua telapak tanganmu ke arah pohon yang ada di depanmu!” Ki Ragil Kuniran segera saja menggeser kaki kiri ke belakang, kedua tangan di tarik ke samping pinggang. Lalu didorongkan ke depan dengan mantap, diikuti dengan hentakan kaki kanan ke bumi. Wuushh! Srakk! Srakkk … !!! Terlihat bayangan sepasang telapak tangan raksasa berwarna kuning keemasan menebarkan hawa panas membara melesat cepat bagai kilat dan menghantam pohon yang besarnya sepelukan orang dewasa hingga hancur lebur berkeping-keping. Tanah yang dilewati bayangan itu seolah diaduk dengan bajak yang ditarik sepuluh ekor kerbau! Blarrrr … !! Suara benturan itu mengguncangkan seluruh penjuru desa, guncangan itu begitu keras, seakan-akan sekitar tempat itu terkena gempa bumi yang dahsyat. Ki Ragil Kuniran terpana melihat hasil pukulannya, lalu melihat kedua telapak tangannya berganti-ganti yang masih menyisakan cahaya tipis kuning keemasan. Beberapa saat kemudian, cahaya kuning keemasan itu lenyap dari tangannya dan berganti menjadi semacam gambar atau rajah berbentuk telapak tangan berwarna kuning emas di masing-masing telapak tangan! Tiba-tiba, telinganya mendengar suara Si Elang Berjubah Perak. “He-he-he-he! Bagus, cucuku! Nah, jika kau ingin menggunakannya, gosoklah kedua telapak tanganmu tiga kali untuk menarik hawa ‘Gaib Inti Panas Bumi’, lalu alirkan hawa ‘Gaib Inti Panas Bumi’ ke telapak tanganmu. Satukan dengan hawa sakti yang ada di pusar. Tarik terus ke atas hingga semua berkumpul di telapak tanganmu! Kau pun kuijinkan mewariskan ilmu ‘Telapak Tangan Bangsawan’ pada anakmu, atau pada siapa saja dengan syarat harus digunakan untuk membela kebenaran dan keadilan! Nah, cucuku, selamat tinggal!” Semua khalayak yang hadir memandang takjub. Tontonan yang mungkin pertama kali mereka saksikan, yang biasanya hanya mendengar saja tentang kehebatan tokoh-tokoh legendaris rimba persilatan atau mungkin hanya cerita mambang tentang kesaktian para dewa. Kini, mereka berempat seolah sebagai saksi tentang munculnya sebuah ilmu pukulan yang dahsyat luar biasa sekaligus menakutkan, pukulan ‘Telapak Tangan Bangsawan’! Ki Sampar Angin dan Nyi Cendani, bergidik ngeri dan membayangkan bagaimana jadinya jika pukulan maut berbentuk bayangan telapak tangan raksasa itu mengenai tubuh manusia, pastilah tubuh hancur lebur menjadi bubur daging. Sedangkan dua Jagabaya sampai gemetar saking kaget dan takut. Tubuh mereka menggigil seperti orang kedinginan, saat menyaksikan tumpahan ilmu olah kanuragan yang baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya mereka berdua jatuh pingsan karena ketakutan yang mendera batin. Beberapa saat kemudian, dari atas langit melesat cahaya terang berwarna putih keperakan. Weessshh! Cahaya putih keperakan itu langsung menabrak burung elang putih keperakan yang sejak tadi bertengger di atas wuwungan dan melihat setiap kejadian di pelataran dengan matanya yang merah saga, dibalut bulatan coklat ditengahnya. Blasssh! Aneh, cahaya itu seakan-akan menembus tubuh elang dan langsung masuk ke dalam rumah. Tepatnya di bilik, dimana Nyi Salindri dan Mbok Inah berada. “Istriku!” seru Ki Ragil Kuniran, saat teringat bahwa di dalam bilik itu istrinya yang hamil tua berada. Blasss! Tubuh laki-laki berbaju hitam itu berkelebat cepat, diikuti dengan yang lain. Ada yang lain dari kelebatan laki-laki itu, lebih cepat dan lebih ringan dari pada biasanya. Namun karena semua diliputi ketegangan yang semakin memuncak, mereka semua tidak ambil dengan perubahan diri Ki Ragil Kuniran. Zlapp! Ketika sampai di depan pintu bilik kamar tidurnya, terdengar suara nyaring yang selama ini sangat dirindukan Ki Ragil Kuniran, suara tangis bayi! “Ooeeekhh! Ooeeekhh … !” Mendengar tangis bayi, Nyi Cendani bergegas masuk ke dalam bilik. “Laki-laki tidak boleh masuk,” katanya dengan suara cempreng, lalu menutup pintu bilik. Nyi Cendani membalikkan badan, dan saat itu matanya melotot melihat pemandangan di depannya. Sebuah kejadian ganjil kembali disaksikan untuk kedua kalinya, sedangkan Mbok Inah berdiri menggigil ketakutan, karena Nyi lurah melahirkan bayi mungil berjenis kelamin laki-laki! Sebenarnya, bukan itu saja yang membuat Mbok Inah ketakutan, bukan karena Nyi Salindri yang melahirkan tanpa bantuan seorang dukun bayi, tetapi karena keanehan yang terjadi pada bayi merah itu. Bayi montok berkulit putih bersih itu ternyata yang sudah bisa duduk, seperti bayi berumur lima enam bulan! Dan lebih anehnya lagi, tali pusarnya sudah hilang entah kemana dan tidak ada noda darah sedikitpun di sekujur badannya. Betul-betul keajaiban yang sulit di nalar dengan akal sehat. Anak Ki Ragil Kuniran memiliki mata bening, sebagaimana layaknya mata seorang bayi, namun pandangan mata bocah itu sangat tajam seperti mata orang dewasa atau setidaknya orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Sedangkan kondisi Nyi Salindri pun bukan seperti wanita yang habis melahirkan, yang tergolek lemah kehabisan tenaga sehabis melahirkan. Wajah Nyi lurah berbinar-binar penuh kegembiraan. Kemudian tangan kanannya melambai ke arah sang anak. “Sini, sayang … dekat sama Ibu … ” Bayi montok itu merangkak ke arah ibunya, dan akhirnya sampai di pelukan sang ibu. Nyi Salindri mencium anaknya dengan gemas. Nyi Cendani hanya terlongong bengong seperti sapi ompong. Peristiwa yang dialaminya hari ini, betul-betul mengejutkan. Nyi Cendani mendekati ranjang Nyi Salindri. “Nyi lurah, bagaimana keadaanmu?” tanya Nyi Cendani. “Entahlah, Nyi Cendani, aku sendiri juga bingung dengan kejadian yang baru saja kualami,” kata Nyi Salindri masih memeluk bocah itu. Nyi Cendani hanya manggut-manggut saja. Tiba-tiba saja, daun pintu diketuk dari luar. Tok! Tok! Tok! “Nyi Cendani, bagaimana keadaan istri dan anakku? Apa baik-baik saja? Tolong buka pintunya, aku ingin masuk.” Nyi Cendani bergegas membuka pintu, dan tampaklah Ki Ragil Kuniran dengan wajah harap-harap cemas. Laki-laki itu masuk diiringi Ki Sampar Angin. “Silahkan masuk, Ki Ragil! Istri dan anakmu tidak apa-apa,” kata Nyi Cendani, sambil menunjuk ke arah Nyi Salindri. “Nyi, bagaimana kea … ” Suara Ki Ragil tercekat di tenggorokan melihat pemandangan yang terpampang di depan mata, melihat istrinya sedang menyusui anaknya yang baru saja lahir ke dunia. Matanya di kucal-kucal untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan mimpi. Ki Sampar Angin juga mengkerutkan kening, dengan pandangan tidak percaya. “Apa benar yang kulihat ini,” pikirnya. Ki Ragil Kuniran menoleh ke arah Nyi Cendani dengan pandangan mata bertanya. “Jangan tanya aku, Ki! Aku sendiri juga bingung dan heran melihat kelahiran anakmu! Anak baru saja lahir sudah bisa merangkak. Ini sudah diluar nalarku sebagai manusia!” kata Nyi Cendani, menjawab pandangan mata laki-laki itu. Sementara itu, Mbok Inah sudah mulai bisa menenangkan diri. Dirinya tidak ketakutan seperti sebelumnya. Bibi tua itu segera mendekati majikannya, dengan takut-takut. “Maaf … Ki lurah, saya … saya … ” “Tidak apa-apa Mbok! Terima kasih simbok telah menjaga istriku dengan baik. Oh ya … Mbok, mungkin Mbok Inah bisa menceritakan kejadian yang sebenarnya,” tanya Ki Ragil Kuniran. Laki-laki itu duduk di sebelah kiri ranjang dan mulai mengelus-elus kepala anaknya. Bocah kecil itu hanya menoleh sekilas, sambil tertawa riang memamerkan mulutnya yang bergigi dua. Ki Ragil Kuniran membalas dengan senyuman. “Begini Ki Lurah, waktu itu saya dan Nyi Lurah sedang ngobrol. Tiba-tiba terdengar ledakan keras seperti suara petir yang menggelegar. Entah suara apa saya tidak tahu. Terus rumah ini seperti dilanda gempa bumi, seperti mau kiamat. Setelah guncangan itu reda, tiba-tiba melesat cahaya putih dari atas. Cahaya itu berputar-putar di dalam bilik ini. Lama-kelamaan seperti membentuk bayangan burung, entah burung apa saya tidak tahu. Lalu bayangan itu melesat masuk ke dalam perut Nyi lurah yang sedang tiduran di ranjang. Nyi lurah tidak bisa menghindar karena gerakan cahaya itu cepat sekali. Setelah cahaya itu masuk, tiba-tiba Nyi lurah merasakan perutnya mules, mungkin karena kemasukan cahaya itu. Baru saja saya akan menyentuh perutnya, tiba-tiba … tiba-tiba … “ “Tiba-tiba apa Mbok?” potong Nyi Cendani dengan cepat. “Tiba-tiba bayi itu … keluar sen … diri, Ki Lurah,” ucap Mbok Inah dengan terbata-bata. “Hahhh!?” kali ini Ki Sampar Angin yang kaget. “Ngomong yang benar, Mbok!” Mbok Inah sampai terlonjak kaget! “Be … benar, Ki Sampar Angin, saya tidak bohong. Tanya saja Nyi lurah, kalau tidak percaya,” kata Mbok Inah, sambil mengelus dada karena dibentak Ki Sampar Angin. Semua mata memandang ke arah Nyi Salindri. Bayi ajaib itu kini tertidur pulas di pelukan ibunya setelah kenyang. “Betul kata Mbok Inah,” sahut Nyi Salindri, pendek. “Mbok, lebih baik simbok istirahat saja di kamar.” “Tapi, Nyi … ” “Nggak apa-apa, saya sudah baikan,” kata Nyi Salindri dengan halus. Mbok Inah hanya mengangguk pelan, lalu keluar dari bilik Nyi Salindri. Sementara itu, Ki Ragil Kuniran masih mengelus-elus kepala anaknya dengan rasa sayang sebagai seorang ayah. Kepalanya manggut-manggut mendengar cerita Mbok Inah. “Persis dengan apa yang kulihat dalam mimpiku,” pikirnya. Memang Ki Ragil Kuniran sengaja tidak menceritakan mimpinya secara lengkap, takut jika mimpi itu hanya kembang tidur saja atau malah takut perkataan dianggap cerita bohong. Sekarang mimpi itu telah menjadi sebuah kenyataan yang memang harus diterimanya dengan ikhlas. Kini lengkap sudah kebahagiaan yang selama ini diimpikan. Meski kebahagiaan itu diikuti dengan beban berat yang belum terjawab dengan kelahiran anak laki-lakinya itu. Tiba-tiba tangan yang mengelus itu menyentuh sesuatu yang aneh di bagian dahi. “Apa ini?” Ki Ragil Kuniran menyibak rambut anaknya dengan pelan, supaya bocah itu tidak terjaga dari tidurnya. Matanya yang tajam mengamati sebentuk gambar yang tertera di dahi anaknya. “Rajah kepala elang,” gumamnya. Nyi Cendani dan Ki Sampar Angin beranjak dari tempatnya semula, mendekati Ki Ragil Kuniran dari sisi kiri. Nyi Salindri juga melihat gambar yang diraba oleh suaminya. “Ada apa, Adi?” tanya Ki Sampar Angin. “Coba Kakang Sampar Angin lihat, apa ini benar rajah bergambar kepala elang atau tanda lahir anakku?” kata Ki Ragil Kuniran. Nyi Cendani dan Ki Sampar Angin mengamati gambar itu dengan seksama. “Itu rajah, bukan tanda lahir,” kata Nyi Cendani dengan yakin. “Apa Nyi Cendani yakin?” “Yakin sekali! Kalau tanda lahir biasanya berwarna hijau keabu-abuan atau coklat, sedangkan yang dimiliki anakmu berwarna putih. Itu hal yang tidak lazim sebagai tanda lahir. Dan saya yakin bahwa tanda itu memilki arti tertentu,” terang Nyi Cendani. Semua khalayak mengangguk-anggukkan kepala. Mereka bertiga keluar dari ruangan itu, dan duduk di kursi yang ada di pendapa, sedangkan Nyi Salindri sudah memeluk anaknya dengan kasih sayang seorang ibu. “Hemmm, pusing kepalaku,” desah Ki Sampar Angin, sambil meletakkan pantatnya di kursi. Laki-laki parobaya yang usianya sepantaran dengan Ki Ragil Kuniran itu melepas blangkon, kemudian mengusap-usap kepalanya untuk mengurangi rasa pening. “Pusing kenapa, Ki Sampar Angin?’ tanya dukun bayi itu, heran. “Bagaimana tidak pusing, semua kejadian malam ini sungguh di luar dugaanku! Luar biasa! Saat aku diberitahu Gineng bahwa istri sahabatku ini mau melahirkan, aku tidak berpikir bahwa peristiwanya akan menjadi seperti ini. Munculnya suara gaib si Elang Berjubah Perak, lalu Adi Ragil yang kinayungan pukulan ‘Telapak Tangan Bangsawan’, sampai cerita si kecil keluar sendiri dari rahim ibunya. Lalu rajah putih berbentuk kepala elang di dahi. Semua itu tidak bisa diterima oleh otakku yang sudah karatan ini,” cerocos Ki Sampar Angin, sambil geleng-geleng kepala. “Hi-hi-hi-hik, kau kira hanya kau yang pusing! Aku pun juga mumet! Masa’ bayi yang seharusnya kutangani kelahirannya, malah keluar dengan sendirinya,” ucap Nyi Cendani dengan terkekeh-kekeh. “Ha-ha-ha-ha!” Tawa Ki Ragil Kuniran dan Ki Sampar Angin hampir bersamaan. “Yahhh, memang begitulah kalau Yang Di Atas sudah berkehendak, kita sebagai manusia hanya bisa menerima saja, bukankah begitu, Kang?” ucap Ki Ragil Kuniran menimpali. “Betul … betul sekali, Adi! Aku setuju dengan pendapatmu!” Nyi Salindri berjalan mendekat tiga orang yang sedang ngobrol sambil menggendong bayinya, lalu duduk di sebelah suaminya. Ki Ragil Kuniran menggeser duduknya ke kanan. Nyi Salindri mengulurkan tangan yang menggendong bayi ke arah suaminya. Ki Ragil Kuniran menerima lalu menimang-nimang bocah yang lahir dengan segudang keanehan itu. “Tapi, ngomong-ngomong, anak laki-lakimu ini kau beri nama siapa, Kakang?” tanya Nyi Salindri, setelah duduk di samping suaminya. Ki Ragil Kuniran menoleh ke arah istrinya, lalu menoleh pada Ki Sampar Angin dan Nyi Cendani. Kedua orang itu hanya mengangguk saja. “Nyi Cendani dan Kakang Sampar Angin, biarlah kalian berdua sebagai saksinya. Mulai hari ini, saat ini juga, anakku ini aku beri nama … Paksi Jaladara!” kata Ki Ragil Kuniran. Sekejab setelah kata-kata Ki Ragil Kuniran selesai, dari dahi bayi mungil yang kini bernama Paksi Jaladara itu memancarkan cahaya putih terang keperakan, seperti pertanda bahwa dirinya menerima nama yang kini disandangnya. Paksi Jaladara! Yang melihat hanya berdecak kagum melihat keanehan pada diri putra Ki Ragil Kuniran. Bersamaan itu pula, elang putih keperakan yang sedari tadi bertengger di atas wuwungan, terbang berputaran di atas rumah dengan suara melengking nyaring. Aawwwkkk! Aawwwkkk! Semua khalayak yang ada disitu hanya memandang burung elang yang berputaran itu. “Elang siapa itu, kakang?” tanya Nyi Salindri, heran. “ … setahuku, di desa kita tidak ada burung elang, sarangnya pun juga tidak ada.” “Oooh … itu miliknya Paksi, anakmu,” sahutnya Ki Ragil Kuniran, pendek. Tangannya masih menimang-nimang Paksi Jaladara dengan pelan, sementara bocah mungil itu tertidur lelap dalam buaian sang ayah. Dahi Paksi Jaladara sudah tidak lagi memancarkan cahaya terang. Bocah itu tertidur pulas ditimang-timang oleh ayahnya. “Milik Paksi?” “Iya … milik Paksi!” “Kok bisa? Kapan kakang memeliharanya?” Kemudian, Ki Ragil Kuniran menceritakan seluruh rentetan peristiwa yang terjadi hari ini, dari awal pertarungannya dengan ular hijau lumut sampai terjadinya guncangan hebat akibat pukulan yang dilontarkannya, yang diterimanya langsung dari si Elang Berjubah Perak secara gaib. Bahkan sampai mimpi yang dialaminya, semua diceritakan dengan lengkap, tidak ada yang tercecer sedikitpun. Sebagian mimpi yang pernah didengar Ki Sampar Angin dan Nyi Cendani, dilengkapi oleh Ki Ragil Kuniran sampai sedetail-detailnya. Semua yang mendengar uraian mengangguk-angguk pelan. Sekarang pahamlah mereka tentang segala rentetan peristiwa yang terjadi. “Bukan main, aku yakin putramu kelak akan menjadi seorang tokoh besar, Adi.” ucap Ki Sampar Angin, sembari menoleh pada Paksi Jaladara yang kini tertidur. “Dengan patokan serentetan kejadian yang kalian alami, aku bisa menyimpulkan bahwa anakmu mengemban tugas khusus. Tugas yang mulia. Entah tugas seperti apa yang dibebankan pada Paksi Jaladara oleh kakek berjubah yang mengaku si Elang Berjubah Perak itu.” Semua khalayak tercenung mendengar uraian Ki Sampar Angin, orang nomor satu dari desa Cluwak Bodas. Memang laki-laki yang selalu memakai blangkon itu patut diacungi jempol, otak encernya dalam menganalisa setiap masalah, selalu memberikan pikiran atau ide-ide cemerlang dan sukar dibantah kebenarannya. “Kakang Ragil, bagaimana kalau kita bertanya pada ayah atau Kakang Jalu? Mungkin beliau tahu siapa adanya si Elang Berjubah Perak itu,” usul Nyi Salindri, menimpali. “Iya … betul! Kenapa aku sampai lupa pada ayah?!” seru Ki Ragil Kuniran sambil menepak jidat dengan keras. “Iya … ya, kenapa kita tidak berpikir ke sana! Mungkin Ki Ageng Singaranu mengetahui siapa tokoh misterius yang bernama si Elang Berjubah Perak itu,” kata Nyi Cendani manggut-manggut. “Baiklah, aku akan bertanya pada ayah,” kata Ki Ragil Kuniran, memutuskan. “Kira-kira kapan kakang akan berangkat?’ “Yahhh … mungkin kalau umur Paksi sudah cukup, sekalian saja diajak. Hitung-hitung … biar Paksi tahu kakeknya,” kata Ki Ragil Kuniran sambil menimang-nimang anaknya itu. Paksi Jaladara menggeliat lucu. Tangannya diangkat tinggi-tinggi sambil menguap. Semua mata memandang bocah ajaib ini dengan pandangan penuh misteri. Pandangan yang menorehkan harapan besar pada bocah yang memiliki rajah kepala elang!
Bab 4 Lima tahun kemudian … Seorang bocah berusia lima tahun lebih sedang bermain-main di pelataran yang cukup luas dan asri, karena banyak pepohonan tumbuh dengan subur. Bocah itu memakai ikat kepala merah dengan baju dan celana biru muda yang diikat sehelai sabuk kain yang juga berwarna merah. Wajahnya yang bersih tampak kemerah-merahan tertimpa sinar matahari pagi. Meski masih bocah, namun tampak gurat ketampanan yang tersirat di wajahnya. Mata bening kecoklatan dengan alis menukik seperti sayap elang. Bibir mungilnya selalu tersenyum-senyum riang. Badan dan tulangnya kokoh dengan kulit putih bersih. Kaki-kakinya yang kecil pendek melompat-lompat mengejar burung putih keperakan yang terbang rendah. Burung itu hanya terbang berputaran di sekitar halaman itu, dialah kawan main si bocah berikat kepala merah. Tangannya berusaha menangkap burung itu, sambil tertawa-tawa riang. “Ha-ha-ha-ha, Perak! Sini … sini … kutangkap kau … ” Sabuk merahnya berkibaran saat melompat ke atas. Walau pun lompatannya tidak terlalu tinggi, nampak bahwa itu bukan lompatan seorang bocah biasa, tapi bocah yang sudah terbiasa dengan ilmu silat atau setidaknya terlatih menggunakan ilmu meringankan tubuh. Burung putih keperakan yang tak lain adalah burung elang, yang dulu pernah bertarung dengan ular hijau lumut lima tahun silam. Sedangkan bocah kecil berikat kepala merah itu tak lain adalah Paksi Jaladara. Gerakan Paksi Jaladara kadang melompat, menyambar bahkan menubruk Si Perak yang selalu bisa berkelit setiap kali Paksi berusaha menangkapnya. Aaawwwkk! Si perak berteriak nyaring, memberi semangat pada Paksi Jaladara. “Wah, kamu susah sekali ditangkap,” ucapnya sambil tersenyum-senyum. Kali ini gerakan bocah kecil itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya, bahkan kini meniru-niru gerakan Si Perak, sehingga nampak Paksi seolah-olah sedang berlatih silat dengan meniru gerakan elang! Jika elang itu bergerak ke kiri dengan sayap dimiringkan, Paksi mengikuti dengan memutar badan ke kiri dengan tangan kiri melambai seperti sayap elang. Gerakan elang perak semakin lama semakin cepat, dan Paksi pun semakin lama semakin cepat pula menggerakan tangan dan kakinya, hingga Si Perak melenting tinggi seperti bersalto dan hinggap di atas palang kayu tempat mengikatkan kuda. Awwwkkk! “Hoi … kok berhenti? Main lagi dong!” seru Paksi Jaladara, sambil mengikuti gerakan melenting dan berdiri diatas palang kayu! Tap! Awwkkk! Awwkkk! Elang putih keperakan itu berteriak serak sambil menggeleng-gelengkan kepala ke kiri dan kenan, sembari mengepakkan sayap. “Oh … kau ingin aku mengulangi gerakanku tadi?” tanya bocah kecil itu. Putra tunggal Ki Ragil Kuniran itu jongkok sambil mengelus-elus kepala Si Perak. Elang putih keperakan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang sungguh aneh, kalau bocah sekecil itu sudah bisa paham bahasa isyarat, apalagi bahasa satwa pemakan daging itu. Si Perak menggerakkan sayap kanan berkali-kali, menyuruh Paksi mengulangi gerakan yang ditirunya. “Baiklah,” ucap Paksi. Paksi Jaladara melenting ke atas sambil berjungkir balik tiga kali. Saat menyentuh tanah, tubuhnya sudah bergerak cepat ke kiri dan ke kanan, dengan kaki bergeser menyamping. Bocah cerdas itu terus menggerakkan tubuh meliuk-liuk. Kedua tangan bergerak gemulai bagai sayap elang, kadang lembut kadang keras, sedangkan kakinya menendang-nendang udara kosong. Kedua tangan kadang membentuk cakar, mencengkeram dengan kokoh. Sepenanakan nasi kemudian, Paksi telah selesai mengulang semua gerakan Si Perak dengan tuntas. Napasnya keluar dengan teratur, tidak terengah-engah seperti layaknya orang yang berlatih silat. Tubuhnya lalu melenting tinggi dan kembali berdiri tegak di atas palang kayu! “Perak, bagaimana? Sudah betul belum?” tanya bocah itu sambil berjongkok dengan satu kali. Kerrkk! Kerrk! “Oh … begitu! Jadi gerakan kakiku kurang cepat ya? Tenagaku juga perlu ditambah? Baiklah, kulangi sekali lagi!” ucap Paksi Jaladara. “Heaaa … ” Diiringi teriakan keras, tubuh Paksi melenting tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya, lalu berjungkir balik beberapa kali. Gerakannya persis seperti sebelumnya, hanya kali ini lebih cepat dan lebih bertenaga. Setiap tendangan, sampokan tangan dan cakaran menimbulkan desiran angin tajam. Di pelataran rumah yang cukup luas itu seperti dilanda angin ribut kecil, karena gerakan Paksi dilambari dengan kekuatan tak kasat mata yang keluar tanpa disadari oleh bocah itu. “Heyyaaa … ” Saat akan mengakhiri gerakannya, Paksi melenting tinggi ke atas, berbalik membelakangi sambil kaki kiri dijulurkan dengan hentakan keras. Wessshh! Dharr! Terdengar ledakan kecil saat kaki pendek itu menghantam tanah, sehingga yang membentuk cekungan sedalam seperempat tombak dalamnya. Lalu tubuh kecil itu melenting ke atas dan berdiri tegak di atas palang kayu, tempat dimana Si Perak bertengger! Paksi Jaladara tertegun melihat cekungan dalam di tanah akibat tendangannya tadi. “Wah … bisa seperti itu ya?” gumamnya. Awwkk! Kwwaak! Burung elang berteriak nyaring sambil mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. “Gerakanku sudah betul? Tapi tenaganya perlu ditambah lagi?!” jawab si bocah sambil manggut-manggut. Paksi tidak tahu, bahwa gerakan yang dikiranya main-main dan hanya meniru gerakan Si Perak adalah salah satu rangkaian ilmu silat yang dinamakan jurus ‘Kelebat Ekor Elang’, sebuah jurus yang mengandalkan gabungan kecepatan serangan dan ilmu meringankan tubuh. Setiap serangan kaki yang dilambari dengan hawa tenaga dalam yang tinggi bisa menghancurkan tebing. Belum lagi dengan desiran angin tajam yang timbul akibat kecepatan serangan yang menggesek udara kosong bisa merobek kulit. Semua kejadian itu tidak lepas dari pandangan mata seorang laki-laki yang sejak tadi mengamati si bocah tampan dari teras rumah. Laki-laki dengan kumis tipis menghias bibir, berbaju hitam lengan panjang dengan celana putih diikat dengan sabuk kain warna hijau. Dialah Ki Ragil Kuniran, kepala desa Watu Belah! “Bukan main! Anak yang cerdas! Hanya dengan sekali lihat, bisa menyerap gerakan elang dan hapal di luar kepala. Tanpa seorang guru pun dia bisa belajar ilmu silat, bahkan sudah paham ilmu ringan tubuh dan mencerna hawa tenaga dalam. Untuk bocah seukuran dia, Paksi cukup hebat. Untunglah jiwanya bukan jiwa perusak. Semoga saja kelak dia menjadi orang berguna, seperti yang dikatakan si Elang Berjubah Perak dulu,” pikir Ki Ragil Kuniran. Kemudian, laki-laki berbaju hitam lengan panjang itu mengambil sebuah buntalan kain kuning dan berjalan ke halaman depan, melewati palang kayu dimana Paksi dan elang kesayangan ‘sedang ngobrol’, sebab memang dialah seorang yang paham bahasa Si Perak. Di sana telah menanti kereta kuda dengan dua ekor kuda penariknya, memasukkan buntalan kain kuning ke dalam kereta kuda. Beberapa saat kemudian, keluar seorang wanita berparas cantik mengenakan pakaian ringkas merah muda, seperti pakaian seorang pesilat. Dibelakangnya, mengiringi seorang pemuda remaja berkulit sawo matang dengan baju buntung warna coklat dengan celana pangsi berwarna putih sambil menenteng buntalan yang cukup besar, lalu buntalan itu dimasukkan di belakang kereta kuda. Di pinggang sebelah kiri terselip sebilah pisau panjang dengan sarung dari kayu dewandaru. Yang paling belakang, seorang perempuan tua dengan kemben lurik berjalan dengan santai, karena tidak membawa barang sedikit pun, juga menuju ke arah kereta kuda. “Simbok benar tidak mau ikut?” tanya Ki Ragil Kuniran pada perempuan tua itu. “Benar Ki Lurah! Biar saya saja yang menunggu di rumah. Saya cuma titip si Gineng ini,” kata perempuan tua, yang tak lain Mbok Inah. Pemuda remaja berusia lima belas tahun berbaju buntung coklat itu tak lain adalah Gineng, telah menjadi seorang pemuda berbadan tinggi besar dan kekar. “Ya sudah! Biar Gineng ikut kami. Hitung-hitung cari pengalaman di luar. Siapa tahu, waktu pulang malah bawa mantu buat simbok,” kata wanita berpakaian ringkas merah muda, yang tak lain Nyi Salindri. “Nyi lurah ada-ada saja,” jawab Gineng, pendek. “Ha-ha-ha-ha! Betul, Nyi … betul! Bukankah di padepokan ayah juga banyak murid-murid gadisnya yang cantik-cantik? Atau malah si Gineng ini sudah kecantol sama Sariti, putrinya Kakang Sampar Angin?” seloroh Ki Ragil Kuniran. Gineng semakin tersipu malu. “Ha-ha-ha-ha … !” Semuanya tertawa melihat tingkah polah pemuda itu yang kikuk. Nyi Salindri segera naik ke dalam kereta kuda diikuti dengan Ki Ragil Kuniran. Sedangkan Gineng mendekati simboknya, lalu meraih tangan dan mencium tangan Mbok Inah dengan takzim. “Gineng, hati-hati di jalan, yo le! Jaga bendoromu dengan baik,” ucap Mbok Inah. “Inggih, Mbok.” Gineng balik badan dan berjalan ke arah bagian depan, lalu dengan sigap duduk di depan bangku pendek, meraih tali kekang kuda, karena dia ditugasi kusir kereta. Ki Ragil Kuniran melongok keluar lewat jendela, lalu berkata, “Paksi, kamu ikut ke rumah kakek tidak?” “Ayah, Paksi ikut ke rumah kakek! Si Perak boleh diajak?” “Ajak saja, biar tidak kesepian kalau ditinggal di rumah!” ucap Nyi Salindri. “Ayo, Perak! Ikut ke rumah kakek,” kata Paksi Jaladara. Wutt!! Bocah berikat kepala merah itu melenting ke atas sambil jungkir balik ke arah kereta. “Paksi! Awaass!” Nyi Salindri berteriak kaget melihat gerakan jungkir balik itu, sedangkan suaminya hanya tenang-tenang saja melihat gerakan Paksi. “Tenang saja, Nyi! Tidak apa-apa!” kata laki-laki itu sambil menenangkan istrinya. Hampir saja istrinya berlari menyongsong Paksi, jika saja tangannya tidak dipegangi oleh suaminya. Jleg! Setelah melayang beberapa saat di udara dengan tangan terkembang, kaki kiri Paksi terlebih dulu menyentuh bangku kosong di dekat Gineng, sedangkan Si Perak sudah terbang berputar-putar di atas kereta kuda, sambil berteriak nyaring. Aawwwkk! “Ilmu ringan tubuh yang bagus,” pikir Gineng, saat melirik majikan kecilnya duduk di bangku sebelah kirinya. “Ayah, Paksi di depan saja, menemani Kakang Gineng,” kata Paksi sambil melongok ke dalam kereta. Saat melongok tadi, ibunya melotot besar. Yang dipelototi hanya tersenyum-senyum sambil mengedip-ngedipkan matanya. “Boleh! Gineng, jalankan kereta!” “Baik, Ki!” Gineng segera menghela kereta kuda. “Heeaaa! Heeeaaa … ” Kereta kuda melaju dengan kencang, bagai anak panah lepas dari busurnya, meninggalkan rumah kediaman Ki Ragil Kuniran. Kuda dihela dengan tenang dan pelan, namun sudah melaju dengan kencang. Sementara itu di dalam kereta, Nyi Salindri masih kaget saat menyaksikan Paksi jungkir balik di udara. Wanita cantik itu lalu menoleh ke arah suaminya dengan pandangan bertanya. “Bukan aku yang mengajarinya,” jawab Ki Ragil Kuniran, dengan kepala menggeleng-geleng, seolah sudah tahu pertanyaan lewat pandangan mata itu. “Lalu siapa?” “Si Perak!” “Si Perak? Mana mungkin seekor burung bisa mengajari ilmu silat pada anak manusia, masih bocah lagi. Kakang Ragil jangan bohong!” “Siapa yang bohong?” Ki Ragil Kuniran menceritakan apa yang dilihatnya pagi tadi, saat Paksi Jaladara bermain dengan elang kesayangannya, semua diceritakan kepada istrinya dengan panjang lebar. “Aku yakin, Si Perak pasti mengajari sesuatu pada Paksi tanpa sepengetahuan kita berdua … ” kata Ki Ragil Kuniran. “ … apalagi dengan adanya tanda lahir di kening berbentuk rajah kepala elang putih dan proses kelahirannya yang aneh itu, aku yakin anak itu memiliki keistimewaan terpendam yang lain, yang belum kita ketahui. Sementara ini yang kita tahu secara pasti adalah bahwa Paksi bisa bercakap-cakap dengan segala macam bangsa burung.” Nyi Salindri mengangguk-anggukkan kepala. Sedang bocah yang dibicarakan kedua orang tuanya, sedang asyik ngobrol ngalor ngidul dengan Gineng, yang berada di depan sebagai kusir. Bocah berikat kepala merah berbaju biru yang selalu riang dan tertawa-tawa, seperti layaknya bocah pada umumnya. “Gerakan Den Paksi tadi hebat, lho … ” “Masak cuma jungkir balik saja sudah hebat? Pasti lebih hebat Kakang Gineng, karena Kakang diajari langsung sama Ayah. Sedangkan aku hanya meniru gerakan Si Perak saja,” ucap bocah itu sambil memperhatikan cara Gineng mengendalikan kereta. “Oh … begitu! Lalu sama Si Perak, Den Paksi meniru gerakan apa saja? Yang paling hebat aja dech … ” tanya Gineng, ingin tahu lebih dalam. Bocah itu terdiam beberapa saat, menimbang-nimbang jawaban yang ingin diberikan. “Emmm, tapi jangan bilang sama ayah, ya? Janji?” kata si bocah sambil mengajukan jari manis sebelah kanan ke atas. Seperti orang mau janjian saja. Gineng hanya tertawa saja, lalu mengajukan jari manis kirinya, terus kedua jari berbeda ukuran itu saling bertaut, sambil berkata, “Aku berjanji sama Den Paksi.” Kemudian Paksi beringsut mendekati telinga kiri Gineng, dan membisikkan sesuatu. Gineng hanya mengkerutkan alis, lalu Paksi kembali duduk ke bangku kembali. “Den Paksi tidak berbohong?” tanya Gineng, seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja didengarnya. Paksi hanya menggeleng-gelengkan kepala. “Yakin bisa melakukannya?” ulang Gineng bertanya. Paksi menganggukkan kepala sebagai jawaban. “Ha … ha … heh … ” Gineng tertawa lebar sambil memandang majikan muda untuk mencari kepastian. Di mata bocah itu, yang terlihat sebuah kepastian bahwa dirinya bisa melakukan hal itu. “Bisa terbang? Mana ada manusia yang bisa terbang? Punya sayap pun tidak,” kata hatinya dengan ragu. “Tapi, kalau melihat tatapan matanya, Den Paksi tidak berbohong. Ahhh … entahlah. Namanya juga bocah, pasti khayalannya kemana-mana.” Kereta kuda melaju dengan kencang ke arah matahari terbit, sementara elang putih keperakan mengikuti laju kereta dari atas. Setelah melewati dua bukit yang dipisah oleh aliran sungai yang cukup lebar, mereka beristirahat sejenak untuk melepaskan lelah. Gineng melepaskan kuda dari kereta, dan membiarkan kuda itu merumput di tepi sungai. Nyi Salindri membuka perbekalan, sedangkan Paksi ngobrol dengan ayahnya dan juga Gineng. Sementara Si Perak, elang putih keperakan itu bertengger di atas sebuah batu, sambil menikmati daging asap yang diberikan Nyi Salndri. Mereka berlima, termasuk Si Perak, makan minum dengan nikmat. Ki Ragil Kuniran dan Nyi Salindri sangat senang melihat kerukunan antara Paksi Jaladara dengan Si Perak dan juga Gineng, yang oleh suami-istri itu sudah dianggap sebagai anak sendiri! Setelah cukup beristirahat, dan kuda-kuda itu kenyang merumput, perjalanan dilanjutkan kembali. Perjalanan mereka tidak banyak mengalami hambatan, bisa dikatakan berjalan mulus. Saat memasuki padukuhan Selo Gilang, hari sudah menjelang malam. Ki Ragil Kuniran mencari sebuah penginapan dan mereka berlima menginap di padukuhan Selo Gilang. Keesokan harinya, setelah mandi sehingga badan segar dan mengisi perut, rombongan keluarga kecil itu melanjutkan perjalanan ke Padepokan Singa Lodaya yang berada di kaki Gunung Singa Putih, yang jaraknya tinggal beberapa ratus tombak saja dari padukuhan Selo Gilang. Memang, pada awalnya Nyi Salindri ingin langsung saja menuju ke padepokan, tapi Ki Ragil Kuniran menyarankan bahwa tidak baik bertamu terlalu malam. Akhirnya Nyi Salindri hanya pasrah saja dengan keputusan suaminya. Padepokan Singa Lodaya, adalah sebuah perguruan ilmu joyo kawijayan guno kasantikan (olah kanuragan) yang dipimpin oleh Ki Ageng Singaranu, seorang tokoh sakti yang pada masa itu jarang memiliki tandingan. Seorang dedengkot golongan putih yang usianya mendekati sembilan puluh tahun, seluruh rambut di kepala dan jenggot sebagaian besar sudah memutih. Kakek itu gemar sekali mengenakan baju abu-abu dipadu dengan celana biru tua. Sepak terjangnya di rimba persilatan dalam memerangi kebatilan dan membela kebenaran benar-benar menggegerkan. Kawan maupun lawan segan padanya. Ilmu Silat ‘Singa Gunung’ itulah yang membuatnya dijuluki sebagai Dewa Singa Tangan Maut. Belum lagi dengan ilmu kebal ajian ‘Kulit Singa’ dan pukulan ‘Telapak Singa Murka’ yang pernah menggegerkan rimba persilatan puluhan tahun yang silam. Bahkan seluruh murid-murid Ki Ageng Singaranu diharuskan bisa menguasai ilmu kebal ajian ‘Kulit Singa’ sebagai tahap awal, karena ilmu kebal ini merupakan dasar-dasar dalam mempelajari Ilmu Silat ‘Singa Gunung’. Bisa dikatakan bahwa seluruh murid Padepokan Singa Lodaya memiliki ilmu kebal, meski pun berbeda tingkatannya antara satu murid dengan murid yang lain. Semakin tinggi kekuatan tenaga dalam yang dikuasai, maka semakin hebat pula ilmu kebal yang dimiliki. Ki Ageng Singaranu memiliki dua orang anak, yaitu Jalu Lampang dan Salindri. Jalu Lampang sendiri lebih suka berkelana di rimba persilatan daripada berdiam diri di Padepokan Singa Lodaya. Sedangkan Salindri, setelah menikah dengan pendekar muda yang bernama Ragil Kuniran, diboyong oleh suaminya ke desa asalnya, Desa Watu Belah. Jarak antara Desa Watu Belah dengan Padepokan Singa Lodaya dapat ditempuh dengan kereta kuda selama sehari semalam. Kereta kuda yang dikusiri oleh Gineng dengan ditemani putra majikannya, Paksi Jaladara, memasuki pintu gerbang padepokan. Diatas pintu tertulis sebuah papan besar berwarna hitam dengan tulisan putih : PADEPOKAN SINGA LODAYA. Di kiri kanan pintu gerbang, terdapat dua patung singa raksasa dari batu hitam dengan posisi siap menyerang. Dua orang murid penjaga bergegas berdiri saat melihat sebuah kereta kuda yang cukup mewah mendekat. “Hooopppss!” Gineng menarik tali kekang kuda dengan sentakan ringan. Meski kelihatan ringan, tenaga tarikan itu sudah cukup membuat kaki kuda terangkat ke atas, dan berhenti tepat di depan pintu gerbang. Seorang dari penjaga berbaju hitam-hitam menghampiri Gineng. Di dada kirinya tersulam gambar kepala singa mengaum. Wajahnya kelihatan dibuat sangar dengan cambang melintang. Di pinggang terselip sebilah golok berwarna hitam legam. “Maaf kisanak, boleh saya tahu kisanak hendak kemana? Dan siapa kisanak ini?” tanya si cambang, dengan suara sedikit serak. Tangan kirinya mengelus-elus golok, sedang kawannya yang bertubuh gempal memegang tombak, hanya melirik-lirik dengan waspada seperti mata maling. Matanya yang tajam memandang Gineng dan Paksi bergantian. Menyelidik. Gineng tidak menjawab, malah balik bertanya, “Apakah ini Padepokan Singa Lodaya?” “Betul! Kisanak ada perlu apa?” ulang si cambang, dengan nada meninggi. Agak meradang juga saat pertanyaannya tidak digubris, malah yang ditanya balik bertanya. Gineng menggangguk-anggukkan kepala. Pemuda remaja itu melongok ke dalam kereta, sambil berkata, “Bagaimana Nyi? Kita sudah sampai, apa mau turun disini?” Yang di tanya hanya menggangguk, lalu berkata, “Kita turun disini saja.” Nyi Salindri keluar dari kereta diikuti dengan suaminya, Ki Ragil Kuniran. Pasangan suami-istri itu melangkah berdampingan. Melihat Nyi Salindri dan Ki Ragil Kuniran, dengan tergopoh-gopoh kedua penjaga itu mendekat dan menyambut dengan wajah dan suara berbeda saat berbicara dengan Gineng. Lebih halus dan lebih sopan. “Oh … maaf … maaf … rupanya Den Ayu Salindri dan Den Ragil yang datang. Saya kira siapa?” kata si cambang dan si gempal sambil membungkukkan badan. “Huh, dasar manusia bermuka kadal,” pikir Gineng. “Apa Ayah ada?” tanya Nyi Salindri, pelan. “Ada … ada … silahkan masuk … Den Jalu juga ada.” “Kakang Jalu juga disini?” timpal Ki Ragil Kuniran. “Betul, Den! Den Jalu sudah berada di padepokan satu purnama lebih,” sahut si gempal yang membawa tombak. Wajah pasangan suami-istri itu cerah, keduanya saling pandang sambil mengangguk pelan. “Mungkin Kakang Jalu sudah bosan berkelana, kakang,” kata Nyi Salindri. Ki Ragil Kuniran hanya mengangguk-anggukkan kepala sambil tertawa. “Gineng, masukkan kereta, letakkan saja di istal, itu … samping kiri gerbang ini!” kata Ki Ragil Kuniran, setelah menepuk-nepuk pundak penjaga berbaju hitam itu. “Baik, Ki!” Kemudian pasangan suami-istri itu bergegas masuk melewati pintu gerbang. Si gempal berjalan di depan sebagai penunjuk jalan, sedangkan si cambang membuka pintu gerbang lebih lebar, untuk memberi jalan Gineng memasukkan kereta. Paksi Jaladara membantu Gineng memasukkan kereta kuda ke istal kuda yang terletak sisi kiri pintu gerbang, sedangkan Si Perak yang sedari tadi terbang rendah kini hinggap di atas wuwungan yang ada di atas pintu gerbang, tepat di atas papan nama padepokan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, mereka berdua menyusul masuk ke dalam. Paksi berjalan sambil melambaikan tangan ke arah elang kesayangannya. Elang itu segera melesat terbang ke arah Paksi dan langsung menerobos masuk ke dalam dan hinggap di palang kayu yang ada di pendapa padepokan. Mereka melewati tanah lapang yang luas dan asri, tempat di mana biasanya para murid padepokan berlatih silat. Sedangkan di kiri kanan terdapat pondok-pondok kecil, tempat tinggal murid Padepokan Singa Lodaya. Di bagian ujung tanah lapang itu ditanami dengan sayur-mayur dan buah-buahan. Beberapa orang murid yang sedang berkebun dan mencangkul tanah, menghentikan pekerjaannya sementara, di saat melihat si gempal mengiring masuk pasangan suami-istri dan dua orang laki-laki beda usia. Seorang kakek berbaju abu-abu menyambut di depan pintu sambil tertawa lebar, diikuti seorang laki-laki kekar bertubuh tinggi menjulai yang juga tersenyum ramah. Laki-laki itu mengenakan sepasang gelang akar bahar yang melingkar di kedua pergelangan tangan. Matanya tajam mencorong seperti mata kucing dalam gelap. Baju buntung tanpa lengan berwarna putih itu sangat kontras dengan kulitnya yang sawo matang dipadu dengan celana putih komprang yang diikat dengan sabuk putih pula. “Ayah!” “Ha-ha-ha-ha! Rupanya kalian yang datang! Pantas saja burung prenjak sejak tadi berkicau terus tanpa henti! Ada tamu istimewa rupanya,” kata si kakek yang ternyata Ki Ageng Singaranu, ayah kandung Nyi Salindri. Seperti gadis kecil saja, Nyi Salindri berlari-lari kecil dan langsung memeluk ayahnya dengan suka cita. Rasa rindu dan kangen tumplek-blek menjadi satu. Sang ayah memeluk putrinya yang sudah lama tidak dijumpai dengan wajah cerah, secerah matahari yang bersinar di pagi itu. Jalu Lampang membiarkan adik dan ayahnya saling berpelukan melepas rindu, lalu menghampiri adik iparnya dan saling berjabat tangan erat. “Bagaimana kabarnya, Dimas Ragil? Baik-baik saja!?” ucap Jalu Lampang. “Kami sekeluarga baik-baik saja, bagaimana dengan kakang sendiri? Sehat-sehat, bukan?” “Ha-ha-ha-ha, seperti yang kau lihat … !” “Saya dengar kabar slentingan dari jauh kalau kakang Jalu sudah beristri. Apa benar?” seloroh Ki Ragil Kuniran. “Ha-ha-ha, bujang lapuk seperti aku ini mana laku di mata para gadis! Paling-paling juga nenek-nenek!?” canda Jalu Lampang. “Ha-ha-ha-ha-ha!” Tawa dua orang itu berderai sampai terkial-kial. Mereka berempat duduk memutari meja bundar yang ada di pendapa. Meja dari kayu jati alas yang sudah sangat tua, namun sangat kokoh. Konon, meja itu usianya hampir sama tuanya dengan usia Ki Ageng Singaranu, karena meja jati itu dibuat bersamaan dengan lahirnya Ki Ageng Singaranu. Beberapa saat kemudian, keluarlah seorang perempuan berkebaya sambil membawa baki berisi makanan kecil dan minuman. Nyi Salindri mengkerutkan alis melihat perempuan berkebaya itu, namun dia diam saja. “Srinilam, duduk sini,” kata Jalu Lampang dengan mesra. “Kakang Jalu, siapa dia? Kok aku baru tahu?” tanya Nyi Salindri. “Ohh … aku lupa, ini istriku! Maaf, aku lupa mengenalkannya pada kalian,” jawab Jalu Lampang. “Srinilam, kenalkan, ini Salindri, adikku yang paling bawel dan laki-laki ganteng itu adalah suaminya, Ragil Kuniran.” “Ooohhh, jadi ini mbakyuku tho?” sahut Salindri, sambil menjabat erat tangan Srinilam. Ki Ragil Kuniran beringsut mendekati Jalu Lampang, yang berada di sisi kirinya, sambil berbisik-bisik, “Jadi ini ‘nenek-nenek’ itu? Cantik amat?!” “Ha-ha-ha-ha-ha!” Kembali Jalu Lampang dan Ki Ragil Kuniran tertawa berderai, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Jalu Lampang malah sampai mengeluarkan air mata. “Kalian ini, kalau ketemu pasti kumat urakannya, seperti anak kecil saja,” gerutu Ki Ageng Singaranu. Walau dalam mulut menggerutu, namun dalam hatinya sangat gembira dan bahagia karena antara mantu dengan anaknya sangat rukun satu sama lain. “Maaf, saya mau ke belakang,” kata Srinilam, sambil beringsut berdiri. “Mbakyu, boleh saya temani?” Srinilam hanya menganggukkan kepala. Dua perempuan itu berjalan beriringan menuju ke dalam, tepatnya menuju ke dapur. Nyi Salindri sangat senang melihat kakak iparnya yang manis itu, tapi lebih senang lagi karena kakaknya Jalu Lampang telah beristri seorang wanita cantik dan menarik hati. “Hebat juga pilihan Kakang Jalu,” puji Nyi Salindri dalam hati. Srinilam yang mulanya agak rikuh dengan adik iparnya, tapi rasa rikuh sirna setelah melihat keceriaan Salindri. Keduanya terus ngobrol ngalor ngidul tak karuan juntrungannya. Setelah dua orang wanita itu berlalu, seorang bocah berikat kepala merah berlari-lari kecil dari arah halaman menuju ke pendapa. Bocah yang tak lain Paksi Jaladara itu langsung menghampiri ayahnya dengan senyum tersungging di bibirnya yang kecil. “Ayah, Paksi boleh main sama Si Perak? Habis … Kakang Gineng malah ngobrol dengan dua paman di depan itu,” kata Paksi sambil memegang tangan kanan Ki Ragil Kuniran. “Boleh, tapi beri salam dulu sama kakek dan pamanmu,” kata Ki Ragil Kuniran, sambil mengelur-elus kepala anak laki-lakinya, sambil menoleh ke arah Jalu Lampang dan Ki Ageng Singaranu. Paksi menghampiri dua orang itu dengan sikap tenang dan langkah kaki yang ringan, lalu meraih tangan kanan kakeknya dan menciumnya. “Ha-ha-ha, jadi ini cucuku? Sini cah bagus, sini … kakek pengin menggendongmu.” Ki Ageng Singaranu langsung meraih Paksi dalam pelukannya. Paksi pun juga merangkul leher orang tua itu dengan kedua tangan kecilnya. Sudah lama Paksi mendengar tentang sang kakek dari ibunya. Senang sekali Ki Ageng Singaranu dapat menimang cucu di usianya yang sudah senja itu. “Cah bagus, namamu siapa?” tanya Ki Ageng Singaranu. “Nama saya Paksi, Kek.” “Oh … nama yang bagus! Sebagus orangnya,” puji Ki Ageng Singaranu. Kemudian kakek berpakaian abu-abu itu melepaskan pelukannya. Paksi menghampiri Jalu Lampang, lalu meraih tangan kanan laki-laki itu dan menciumnya, seperti yang dilakukan pada kakeknya. Jalu Lampang tersenyum sambil mengelus-elus kepala Paksi. “Ha-ha-ha-ha, ternyata keponakanku sudah sebesar ini! Oh ya, kau boleh panggil Paman Jalu saja,” kata Jalu Lampang, sambil tersenyum. Bocah itu hanya memandang muka pamannya dengan seksama, lalu tersenyum penuh arti. Setelah itu, Paksi kembali ke depan ayahnya, sambil berkata, ”Ayah, Paksi mau main sama Si Perak, di halaman saja.” Bocah itu menuding halaman yang luas, tempat dimana biasanya para murid berlatih silat. “Boleh, tapi jangan jauh-jauh.” “Ya, Ayah.” Bocah itu berlari keluar pendapa. Langkah kakinya ringan dan teratur, diikuti dengan suitan nyaring. Suitt!! Suitt!! Dari arah barat, melesat sesosok bayangan putih keperakan menghampiri Paksi. Bocah itu tertawa-tawa riang, lalu duduk bersandar di sebatang pohon. Dua makluk beda jenis itu asyik berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami oleh mereka berdua.
Bab 5 Ki Ageng Singaranu memandang bocah itu dengan kepala manggut-manggut. Mata tuanya melihat bakat luar biasa pada diri Paksi Jaladara. Saat memeluknya tadi, tangan tuanya bisa merasakan kekokohan susunan tulang, di tambah lagi dengan melihat cara berjalan dan berlari bocah itu, sudah bisa menebak seberapa bagus susunan tulang tubuh Paksi Jaladara. Apa yang dipikirkan Ki Ageng Singaranu sama dengan apa yang ada di otak Jalu Lampang. “Bakat yang luar biasa,” gumam Jalu Lampang. “Hemm, susunan tulangnya sangat bagus! Ragil, apa kau yang mengajari anakmu ilmu silat dan ringan tubuh?” tanya Ki Ageng Singaranu, menebak. Ki Ragil Kuniran sudah menduga apa yang akan dilontarkan oleh ayah mertuanya begitu melihat Paksi. Itulah yang menjadi sebab kedatangannya ke Padepokan Singa Lodaya, tentang keanehan yang disandang putra tunggalnya, Paksi Jaladara! “Bukan, ayah! Saya belum mengajari Paksi apa pun,” jawab Ki Ragil Kuniran, pendek. “Bukan kau?” kali ini Jalu Lampang bertanya. “Lalu siapa? Apa Salindri yang mengajarinya?” Lagi-lagi yang ditanya hanya menggelengkan kepala. “Lalu siapa?” tanya Ki Ageng Singaranu, penasaran sekali. Baru kali ini tebakannya meleset. “Ayah, apakah ayah mengenal tokoh sakti atau seorang pendekar yang bergelar Si Elang Berjubah Perak?” balik tanya Ki Ragil Kuniran. Ki Ageng Singaranu menjungkitkan alis. Nama yang disebut itu sangat mengagetkan dirinya, meski tidak diperlihatkan secara nyata. Tapi pandangan mata Ki Ragil Kuniran tidak bisa ditipu, meski hanya sekilas dapat melihat kekagetan ayah mertuanya. Jalu Lampang pun terlengak kaget mendengar pertanyaan adik iparnya. “Untuk apa Dimas Ragil menanyakan tokoh golongan putih itu?” pikir Jalu Lampang. “Si Elang Berjubah Perak? Untuk apa kau bertanya tentang tokoh itu?” kata Ki Ageng Singaranu, menyelidik. “Ayah, tokoh atau orang yang bergelar Si Elang Berjubah Perak sangat erat hubungannya dengan pertanyaan yang ayah ajukan pada saya … ” jawab Ki lurah Desa Watu Belah. “ … Saya sangat membutuhkan keterangan tentang siapa adanya tokoh sakti itu, Ayah.” “Ada hubungannya dengan pertanyaanku tadi? Jelaskan padaku, apa maksud semua ini?” ganti balik bertanya Ki Ageng Singaranu. “Dimas Ragil, darimana Dimas mengetahui nama si Elang Berjubah Perak?” kali ini Jalu Lampang yang bertanya, menyusul pertanyaan ayahnya. Ki Ragil Kuniran menceritakan serangkaian kejadian yang dialaminya tentang proses kelahiran Paksi Jaladara yang aneh dan unik, juga tentang segala kejadian yang berhubungan dengan mimpi yang pernah diterimanya, yang dianggap sebagai sasmita. “Saya hanya mendengar suaranya saja, sedangkan wujudnya tidak kelihatan. Dia mengaku berjuluk si Elang Berjubah Perak dan memilih anakku sebagai pewaris Tahta Angin dan mengaku pula bahwa dirinya adalah Sang Angin! Kemudian tokoh gaib itu juga mengatakan bahwa Penunggang Angin akan menjadi pertanda kelahiran anakku tepat di bulan ke tiga belas. Kemunculan diiringi dengan suara deru angin membadai dan gelegar petir. Nama anakku pun, beliau pula yang memberi, bukan saya sebagai ayahnya.” “Apakah dalam mimpimu, dia berjubah bulu burung keperakan?” tanya Ki Ageng Singaranu, menegaskan. “Betul, Ayah.” “Siapa si Penunggang Angin itu? Apa Dimas sudah mengetahuinya?” tanya Jalu Lampang. “Sudah, Kakang! Bahkan sekarang pun ada disini. Ternyata yang dimaksud si Penunggang Angin adalah burung elang itu,” jawab Ki Ragil Kuniran, sembari telunjuk kanannya menuding ke arah Paksi dan elang kesayangannya bermain. Ayah dan anak itu memandang ke jurusan barat. Pada awalnya Ki Ageng Singaranu hanya menganggap sebagai elang biasa, hewan peliharaan menantunya dan juga teman bermain anaknya supaya tidak nakal. Mata tua itu memandang tajam ke arah Si Perak, seakan sedang menerka-nerka. Sedang yang diperhatikan, masih asyik dengan si majikan muda. Sambil bermain berkejar-kejaran, Paksi menirukan gerakan-gerakan elang putih itu. Ki Ageng Singaranu kaget melihatnya. “Mustahil!” ucap Ki Ageng Singaranu. “Bagaimana mungkin bocah sekecil itu bisa menirukan gerakan hewan sehingga nyaris sama dengan gerakan hewan itu sendiri?” “Itulah sebabnya saya berkunjung ke sini untuk mencari keterangan siapa adanya si Elang Berjubah Perak.” kata anak mantunya. Sejenak Ki Ageng Singaranu terdiam, seolah sedang mengingat-ingat sesuatu. Keningnya berkerut. Jalu Lampang dan Ki Ragil Kuniran memperhatikan Ketua Padepokan Singa Lodaya dengan raut muka sedikit tegang, terutama Ki Ragil Kuniran, karena dirinyalah yang bersangkutan dengan masalah ini. Lalu, Ki Ageng Singaranu berkata, “Kalau mengetahui betul, aku juga tidak yakin. Dari cerita mendiang Guru yang pernah kudengar, ratusan tahun silam muncul seorang pendekar yang berjuluk Si Elang Berjubah Perak. Dia seorang pendekar pilih tanding di rimba persilatan. Tidak ada yang tahu dari mana asal-usulnya. Dia seperti orang kabur kanginan, tidak diketahui siapa orang tuanya, gurunya, semua serba misterius. Waktu itu guruku baru berumur lima belasan tahun. Yang mengetahui secara pasti hanyalah Eyang Guru. Guru pernah berjumpa dengan si Elang Berjubah Perak beberapa kali. Terakhir kali yang kudengar, Eyang Guru bertemu di Gunung Tambak Petir. Saat itu guruku sudah berusia hampir tiga puluh tahun ketika bertemu dengan si Elang Berjubah Perak … “ “Gunung Tambak Petir? Dimana letak gunung itu?” gumam Jalu Lampang, seolah-olah memotong pembicaraan. “Ya, Gunung Tambak Petir! Aku sendiri juga tidak tahu dimana letak gunung itu. Ketika akan berpisah, laki-laki berjubah bulu burung itu menepuk punggung Guru sekali, dan mengatakan dirinya menitipkan sesuatu untuk diberikan ke seseorang. Entah siapa, Guru juga tidak mengatakannya. Bahkan bentuk titipannya seperti apa, Guru juga tidak tahu. Mungkin hanya Eyang Guru yang tahu, tapi Eyang Guru juga tidak mengatakan sesuatu pada muridnya,” kata Ki Ageng Singaranu lebih lanjut. “Aneh, yang dititipi juga tidak tahu apa bentuknya dan kepada siapa titipan itu akan diberikan,” kata Ki Ragil Kuniran, dengan pelan. “Lalu, lanjutnya bagaimana, Ayah?” Setelah berhenti sejenak dan meminum air jahe yang ada di cawan tanah itu, Ki Ageng Singaranu melanjutkan ceritanya. “Sampai Guru menjelang ajal, beliau pun juga menepuk punggungku sekali, dan mengatakan bahwa diriku sebagai pengemban titipan itu dan harus memberikan titipan itu pada orang yang berhak. Aku pun bingung, pada siapa titipan itu harus kuberikan, sedangkan bentuk titipan itu pun aku tidak tahu. Bahkan saat almarhum adik seperguruanku ingin melihat bentuk titipan itu di punggungku, tidak terlihat apa-apa dan dia tidak menemukan apa-apa di punggungku. Aneh, bukan?” jelas Ki Ageng Singaranu. “Jadi, almarhum paman Gagak Sempana juga tidak melihat apa-apa di punggung Ayah? Hemmm, betul-betul membingungkan,” kata Jalu Lampang sambil menghela napas. “Apa paman Rangga Jembangan juga tidak mengetahui, Ayah?” “Tidak … Rangga Jembangan bahkan menggunakan ilmu ‘Netra Benggala’ untuk menembusnya, juga tidak melihat apa-apa. Gagal total.” Ki Ragil Kuniran terdiam. Semua keterangan yang didengarnya masih samar-samar. Lalu berkata, “Apa Ayah juga tahu tujuan pertemuan antara Eyang Guru dengan si Elang Berjubah Perak? Mungkin pernah menyinggung nama tempat? Atau tokoh-tokoh tertentu?” Ki Ageng Singaranu terdiam sejenak, alisnya berkerut-kerut seakan mengingat sesuatu. Laki-laki tua itu memeras otaknya. Keringat sampai bercucuran dalam mengingat sebuah tempat yang sudah puluhan tahun dilupakannya. “Kalau tidak salah, beliau pernah membicarakan tentang sebuah perkumpulan pendekar aliran putih yang berpusat di Istana Elang. Ya … Istana Elang!” kata Ki Ageng Singaranu dengan yakin. “Istana Elang?” Ki Ragil Kuniran bergumam. “Dimana letak Istana Elang itu, ayah?” tanya Jalu Lampang, yang sedari tadi diam sambil mendengarkan keterangan ayahnya. Semua perkataan ayahnya dicerna dengan sebaik-baiknya. Namun, selama melanglang buana di rimba persilatan belum pernah mendengar tentang si Elang Berjubah Perak dan Istana Elang. “Entahlah, aku juga tidak tahu. Hanya itu yang kudengar dari mendiang guruku,” katanya. Lagi-lagi mereka menemui jalan buntu! Ki Ragil Kuniran mencerna keterangan itu dengan seksama. Ada dua tempat penting dalam keterangan ayah mertuanya, yaitu sebuah gunung yang bernama Gunung Tambak Petir dan Istana Elang! “Bagaimana dengan Kakang Jalu? Bukankah selama ini Kakang telah malang melintang di rimba persilatan, mungkin saja pernah mendengar slentingan tentang tokoh misterius itu?” tanya Ki lurah desa Watu Belah. “Entahlah … aku sendiri tidak tahu, Dimas Ragil,” jawab Jalu Lampang, dengan nafas terhmbus pelan, “ … Andaikata sahabatku ada disini, mungkin bisa mendapatkan keterangan yang lain dari dirinya tentang Istana Elang dan si Elang Berjubah Perak itu.” “Siapakah nama sahabat Kakang itu?” “Orang persilatan sering menyebutnya si Kutu Buku Berbambu Ungu,” jawab Jalu Lampang. “Hemm, si Kutu Buku Berbambu Ungu? Aku pernah mendengar tentangnya. Kabar yang berhasil kusirap, si Kutu Buku Berbambu Ungu memiliki ilmu yang dinamakan ‘Terawang Gaib Masa Lalu’, ilmu yang bisa melihat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau, bahkan kudengar bisa mengetahui kejadian yang akan terjadi di masa datang. Apa benar begitu, Kakang Jalu?” “Benar, Dimas Ragil. Ilmu itulah yang dimilikinya.” “Lalu, apakah Kakang Jalu juga tahu dimana adanya orang itu sekarang?” tanya Ki Ragil Kuniran pada kakak iparnya. “Kabar terakhir yang kudengar, di sedang berada di Perguruan Gerbang Bumi, atas undangan Ketua lama Perguruan Gerbang Bumi untuk menyaksikan pemilihan sekaligus pengangkatan ketua baru untuk menggantikan kedudukan Ketua lama. Tapi, sekarang apa masih ada di Perguruan Gerbang Bumi ataukah sudah pergi melanglang buana mengikuti langkah kakinya, aku pun tidak tahu dimana dia berada,” jawab Jalu Lampang. Tiga orang itu kembali terdiam. Ki Ragil Kuniran kembali duduk tercenung menganalisa keterangan ayahnya, sedangkan Jalu Lampang juga tidak berbeda dengan adik iparnya. Otaknya memilah-milah hal-hal yang mungkin saja terlewat untuk diceritakan, namun sampai kepalanya pening, tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Beberapa saat kemudian, Ki Ageng Singaranu menghela napas sambil berkata, ”Sudahlah, mungkin suatu saat rahasia itu akan terkuak, siapa tahu malah Paksi sendiri yang bisa memecahkan misteri yang menyangkut dirinya itu.” Kemudian kakek tua Ketua Padepokan Singa Lodaya itu bangkit berdiri dan masuk ke ruang dalam, sehingga tinggal Jalu Lampang dan Ki Ragil Kuniran yang berada di pendapa. Mereka pun berbicara panjang lebar sampai hari menjelang senja. Tentu saja pembicaraan yang sifatnya ringan dan sedikit menyerempet-nyerempet rimba persilatan saat ini. Ketika senja telah berganti dengan malam, dan bulan sabit telah keluar dari peraduan, dibuncahi malam cerah penuh bintang, mereka sekeluarga berbincang-bincang di ruang dalam. Semua duduk melingkari meja besar yang di tengahnya tertata rapi makanan dan buah-buahan segar. Ki Ragil Kuniran duduk bersebelahan dengan Jalu Lampang, sedangkan Salindri berdampingan dengan Srinilam, istri Jalu Lampang. Paksi Jaladara malah enak-enakan duduk di pangkuan kakeknya sambil menggerogoti jambu biji. Sesekali terdengar suara tawa saat mendengar celoteh bocah kecil itu. Tentu saja Ki Ageng Singaranu yang paling senang, bisa melihat cucu satu-satunya dan bahkan sedang duduk di pangkuan. Sedangkan Gineng, duduk di tangga pendapa, sambil melihat-lihat ratusan murid padepokan yang sedang berlatih silat di tanah lapang yang cukup luas. Pemuda remaja itu masih mengenakan baju buntung tanpa lengan kesukaannya dan sebilah pisau panjang terselip di pinggang. Semua murid memakai baju biru, hijau, dan ungu, kecuali dua orang yang berbaju hitam, sedang mengawasi mereka yang sedang berlatih. Ada yang bertangan kosong, memainkan jurus-jurus golok, tombak, pedang dan juga trisula berpasangan. Dua orang yang berbaju hitam itu adalah murid padepokan yang paling lama menimba ilmu di padepokan, sehingga oleh Ki Ageng Singaranu dipercaya melatih Ilmu Silat ‘Singa Gunung’, ilmu khas Padepokan Singa Lodaya. Tataran ilmu mereka berdua hanya terpaut dua tiga tingkat saja dari Jalu Lampang, sehingga bisa dikatakan cukup mumpuni dalam hal olah kanuragan dan jaya kawijayan. “Heeeaaa … Haaattt … Ciatttt … ” Murid-murid yang berlatih itu memiliki gerakan mantap dan teratur. Pergeseran kaki, liukan tubuh, kelebatan tangan dan tendangan serta sorot mata tajam mereka, mengingatkan Gineng pada seekor singa jantan yang sedang mengintai dan siap mencabik-cabik mangsa. “Jurus yang hebat, aku yakin jika dilambari tenaga dalam yang tinggi, pasti akan menghasilkan daya hancur yang dahsyat. Apa ini yang dinamakan Ilmu Silat ‘Singa Gunung’ yang pernah dikatakan oleh Ki lurah padaku,” bathin Gineng, sambil matanya memandang jurus-jurus silat yang sedang dilatih para murid Padepokan Singa Lodaya. Gineng kemudian memperhatikan jurus silat yang menggunakan pedang, karena jurus itu mengingatkan pada dirinya pada jurus pisau yang dimilikinya. Hampir sama persis dengan apa yang pernah dipelajarinya dari Ki Ragil Kuniran. “Jurus pedang itu mirip sekali dengan jurus pisauku,” gumamnya. Namun, malam yang cerah itu, tiba-tiba dibuncah suara ledakan keras. Brakk! Dhuuarrr … !! Pintu gerbang padepokan yang terbuat dari kayu jati tebal itu, hancur berantakan diiringi suara benturan keras memekakan telinga. Benturan keras itu menimbulkan kepulan asap pekat dan bau hangus terbakar. Seluruh murid padepokan terlonjak kaget, bahkan ada yang terjerembab saking kagetnya. Mereka cepat berlarian menyingkir dan ada yang sebagian berdiri di belakang dua murid utama itu. Dua murid utama juga kaget, namun segera menguasai diri dengan baik. “Siapa kalian? Berani sekali membuat onar di Padepokan Singa Lodaya!?” bentak salah seorang murid berbaju hitam yang kanan. Murid berbaju hitam yang sebelah kiri memutar tubuh, kemudian tangan kanannya mengibas ke depan dengan cepat. Selarik cahaya hijau terang melesat cepat dan menerjang kepulan asap yang masih mengepul. Dari balik kepulan asap, selarik cahaya merah pekat memapaki sinar hijau dan bertemu di udara kosong. Bhummm! Terdengar ledakan keras, bumi serasa diguncang gempa kecil. Murid yang melontarkan pukulan tenaga dalam warna hijau terang sampai terjajar beberapa langkah, dan akhirnya jatuh terduduk. Brugh! Dari sudut bibirnya menetaskan darah segar. Dadanya sedikit terguncang karena akibat dari lontaran tenaga dalam yang dilepaskannya membentur seleret pukulan tenaga dalam warna merah pekat yang dilepaskan dari balik kepulan asap. “Pulanggeni, kau tidak apa-apa?” tanya kawannya, sambil membantu laki-laki yang bernama Pulanggeni, berusaha bangkit berdiri. “Aku tidak apa-apa, Galang Seta! Uuhh, hebat juga mereka! Dadaku sampai terguncang begini,” kata laki-laki yang bernama Pulanggeni. Laki-laki yang bernama Galang Seta itu membantu Pulanggeni berdiri, dengan mata tetap menatap ke arah pintu gerbang padepokan yang hancur. Semua mata memandang ke arah kepulan asap. Sedikit demi sedikit asap menipis dan akhirnya, tampaklah beberapa sosok bayangan yang membentuk sosok manusia! Terlihat tiga sosok bermuka bengis, pertanda bahwa diri mereka bertiga bukan orang baik-baik atau setidaknya datang dengan tujuan yang tidak baik. Dibelakangnya berdiri puluhan orang bertampang sangar dengan berbagai macam golok, pedang, trisula dan segala macam senjata berada di tangan. Bisa dipastikan mereka gerombolan brandal kecu yang kejam, berteriak-teriak keras sambil mengeluarkan kata-kata kotor! Orang pertama adalah laki-laki berbadan gempal, bahkan cenderung gemuk dengan tinggi badan sedang. Seluruh tubuhnya penuh bulu-bulu lebat, muka lebar berminyak dengan satu biji mata yang selalu melotot liar. Badannya tidak berbaju, sehingga kekekaran otot nampak terpampang jelas, menandakan memiliki ilmu silat yang cukup tinggi atau setidaknya akrab dengan kekerasan. ‘Tenaga Sakti Serigala Iblis’-nya sudah cukup tinggi, terutama di antara dua saudaranya yang lain. Dialah Ketua Serigala Iblis, yang oleh kalangan sesat dijuluki Serigala Hitam Bermata Tunggal! Yang kedua adalah seorang laki-laki bermuka lancip seperti tikus mengenakan baju besar kedodoran yang tidak dikancingkan, sehingga tampak tulang dadanya yang menonjol seperti penggilasan padi. Di pundak kiri kanannya terselip semacam pisau-pisau panjang berjajar masing-masing berjumlah tiga dengan panjang hampir mencapai satu tombak, Cakar Serigala namanya. Sekilas memang tampak seperti bentuk clurit panjang berwarna hitam kemerah-merahan, mengeluarkan bau busuk menyengat. ‘Tenaga Sakti Serigala Iblis’ yang dimilikinya hanya terpaut satu tingkat saja dari Serigala Hitam Bermata Tunggal. Laki-laki bermuka tikus itu sering dipanggil dengan nama Cakar Iblis Taring Serigala. Yang paling akhir adalah seorang laki-laki berbadan kurus seperti cecak kering. Tubuh yang tinggi menjulai dibalut kain hijau tua. Tubuhnya lebih kurus dari Cakar Iblis Taring Serigala, dengan tinggi badannya mencapai dua tombak lebih. Bicaranya selalu gagap, sehingga selalu dicemooh oleh ke dua saudaranya. Diantara mereka bertiga, dialah yang memiliki ilmu meringankan tubuh paling tinggi, karena ‘Tenaga Sakti Serigala Iblis’ yang dikuasainya selalu dipusatkan pada sepasang kakinya yang panjang, sehingga ilmu ringan tubuhnya melampaui dua saudara tertuanya. Meski ilmu silatnya biasa-biasa saja, namun dia pulalah yang paling jago dalam melempar senjata rahasia. Tangan Kilat Kaki Bayangan itulah julukan yang pas untuknya! Murid-murid Padepokan Singa Lodaya segera bersikap waspada melihat kedatangan tamu-tamu tidak diundang itu. Beberapa orang berlarian ke dalam barak senjata, kemudian beberapa saat kemudian sudah kembali dengan senjata terhunus. Sementara itu, di saat mendengar ledakan keras membahana, Ki Ageng Singaranu, Jalu Lampang dan Ki Ragil Kuniran segera bergegas keluar dari dalam pondok menuju ke arah suara berasal, sedangkan Nyi Salindri dan Srinilam menyusul di belakangnya. Paksi pun berlari-lari kecil mengikuti sang bunda. Pada mulanya ibu muda itu menyuruh Paksi sembunyi di dalam kamar, tapi karena rasa ingin tahu seorang bocah, membuat Paksi mengikuti dengan sembunyi-sembunyi. “Siapa kalian? Untuk apa berbuat onar di tempat kami?” bentak Galang Seta, matanya memancarkan kemarahan karena sahabatnya terluka meski pun tidak begitu parah. “Ha-ha-ha … kau mau tahu siapa kami? Apa kalian pernah mendengar nama Gerombolan Serigala Iblis?! Kalau kalian belum pernah mendengarnya, sekarang kalian bisa melihatnya disini,” jawab laki-laki bermata satu itu dengan pongah. “Apa tujuan kisanak datang kemari?” kali ini Ki Ragil Kuniran yang bertanya. “Hemm, tujuanku kemari adalah … Kau!” Laki-laki tak berbaju dengan celana hitam kelam itu menuding ke arah Ki Ageng Singaranu! Sedangkan yang dituding melengak kaget. “Aku!? Untuk apa kisanak mencariku?” tanya Ki Ageng Singaranu, heran. “Singaranu! Yang kubutuhkan bukan tua rongsokan seperti kau, tapi sebuah benda pusaka yang diberikan oleh gurumu, si Ki Dirgatama yang berjuluk Singa Putih Berhati Iblis kepadamu!” sambung laki-laki bermata satu itu. “Serahkan benda pusaka itu padaku atau padepokanmu ini akan kujadikan karang abang, kuratakan dengan tanah!” “Benda pusaka apa? Guruku tidak pernah memberikan benda pusaka apapun padaku!” jawab Ketua Padepokan Singa Lodaya, dengan tegas. “Bohong!” bentak laki-laki bertampang lancip seperti tikus. “Aku yakin kau memiliki benda pusaka yang diinginkan kakangku! Lekas serahkan pada kami!” “Kak … ka … kang … buub … buuattt … appp … appa ban … banyak omm … oomong … sikk … sikaatt … saj … ja … ” kata orang ketiga yang sejak tadi hanya diam. “Diam! Kalau tidak bisa ngomong, jangan banyak ngomong!” bentak Serigala Hitam Bermata Tunggal. Si cecak kering itu langsung terdiam dengan kepalanya ditundukkan. “Singaranu, apa kau memang menginginkan padepokanmu ini aku ratakan dengan tanah?! Baik, kalau itu maumu!” bentak Cakar Iblis Taring Serigala, dengan mata melotot beringas. Terdengar suara gigi gemeletuk mengisyaratkan kemarahan. Sifatnya memang mudah marah dan tanpa banyak pikir panjang. “Huh, kalian kira kami takut dengan gertak sambal kalian?” bentak Jalu Lampang. “Begundal-begundal tengik seperti kalian memang seharusnya dienyahkan dari muka bumi!” “Bangsat! Anak-anak, seraaang … !” Tanpa diberi aba-aba untuk kedua kalinya, pengikut Gerombolan Serigala Iblis langsung menerjang maju. Mereka berteriak-teriak seperti kesetanan dengan senjata-senjata telanjang yang saling beradu cepat mencari mangsa. “Hyyyaaa … Ciatttt … ” Murid Padepokan Singa Lodaya juga langsung masuk ke gelanggang pertarungan yang setiap saat bisa merenggut nyawa. Namun, dengan mengandalkan ilmu kebal ajian ‘Kulit Singa’ yang mereka kuasai, tanpa kenal takut memapaki serbuan pengikut Gerombolan Serigala Iblis dengan berani. Dalam waktu singkat, halaman padepokan yang biasanya tenang itu berubah drastis menjadi ajang pertarungan hidup mati antara murid Padepokan Singa Lodaya dengan para pengikut Gerombolan Serigala Iblis yang beringas. “Lebih baik Ayah menonton saja di beranda! Biar saya dan Dimas Ragil yang menangani. Tolong jaga Srinilam dan Salindri,” kata anaknya, Jalu Lampang. “Hemmm, ya sudah, tapi hati-hati dengan laki-laki tinggi besar itu.” “Baik, Ayah!” Jalu Lampang segera berkelebat cepat dengan ilmu meringankan tubuh yang langsung dikerahkan dengan lambaran hawa tenaga dalam yang kuat. Dan langsung menuju ke satu sasaran, yaitu Serigala Hitam Bermata Tunggal! Dari atas, tubuh kekar itu langsung menghantam dengan pukulan jarak jauh ke arah lawan! Debb! Debb!! Weess!! Serangkum cahaya hijau pupus yang berasal dari hawa tenaga dalam itu melesat cepat ke arah laki-laki bermata satu itu. Laki-laki itu mendengus keras, lalu tubuhnya bergeser setengah tombak ke kiri, diikuti dengan berputarnya tubuh besar itu sambil tangan kanannya di dorong ke depan. Serangkum cahaya hitam kelam membentuk bayangan kepala serigala dengan mulut terbuka lebar, memapaki serangan tenaga dalam berwarna hijau pupus milik Jalu Lampang. Blaaammm!! Ledakan keras mengiringi bertemunya dua tenaga dalam yang beda warna sehingga di sekitar tempat itu bagai diguncang prahara kecil. Jalu Lampang terpental ke belakang, namun masih bisa berjumpalitan dan jatuh ke tanah dengan kaki terlebih dahulu, sedangkan Serigala Hitam Bermata Tunggal juga terpental ke belakang dan lalu mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Jleg! Dua lawan saling bertemu pandang, saling menilai seberapa kuat lawan yang dihadapinya, saling mencari letak kelemahan dan kelengahan masing-masing. Beberapa saat kemudian, seolah dikomando, keduanya langsung serang dan saling terjang. Perkelahian pun berlangsung dengan sengit. Jalu Lampang mengerahkan kekuatan hawa tenaga dalam yang memancarkan cahaya hijau pupus dan seolah-olah membentuk bayangan singa raksasa. Semakin lama, seluruh tubuh memancarkan cahaya hijau pupus menyilaukan, di samping juga memainkan Ilmu Silat ‘Singa Gunung’, sehingga gerakannya mirip seekor singa jantan yang cukat trengginas berusaha menggencet lawan. “Heaaa … ! Hiaaa … !” Serigala Hitam Bermata Tunggal juga tidak mau kalah mengerahkan hawa ‘Tenaga Sakti Serigala Iblis’. Perlahan namun pasti, tenaga dalam itu membentuk bayangan khayal serigala yang seolah-olah membayangi gerak Serigala Hitam Bermata Tunggal. Mereka bertarung dengan gerak cepat, laksana seekor singa dan serigala yang saling berebut mangsa. Pertarungan itu makin seru karena masing-masing telah mengeluarkan ilmu andalannya. Akan halnya Ki Ragil Kuniran sudah menghadapi si Cakar Iblis Taring Serigala yang sudah siap dengan senjata andalannya, Cakar Serigala. Cakar besi itu terus menerus mengeluarkan bau busuk karena mengandung racun ganas, kini telah terselip di kedua tangan, bagaikan sepasang taring-taring hewan pemangsa itu. Tubuh kurusnya mengimbangi gerakan lawan dengan kecepatan kilat. Ketika jarak tinggal dua tiga tombak, Si Cakar Iblis Taring Serigala menerjang maju dengan mengibaskan ke dua tangan bersilangan dengan cepat, mengerahkan jurus ‘Cakar Maut Membelah Angin’ sehingga membentuk kibasan rapat membelah udara berwarna abu-abu memanjang, melaju cepat ke arah Ki Ragil Kuniran. Ki Ragil Kuniran tetap tenang. Tangan kana kiri yang bersenjatakan sepasang pisau panjang bergerak mengibas ke depan dengan bersilangan sambil tubuh berputar ke kiri, mengerahkan jurus ‘Kelebat Guntur Menari’. Seleret udara mampat berbentuk kilatan bunga api berloncatan bergerak cepat, menyongsong serangan lawan. Dhaarr! Dharr!