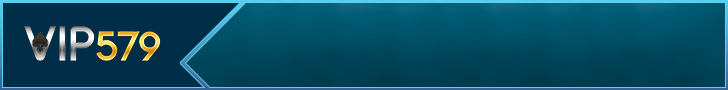neoKORTEKS
PROLOG Empat koma enam milyar tahun lalu, ada sejumlah gas yang terkondensasi di antara kegelapan semesta. Dari benturan antar unsur-unsurnya, antar molekul-molekulnya, bahkan antar partikel tuhan di dalamnya, akhirnya terbentuklah banyak bola panas yang sangat radiatif. Sebuah padatan yang berkilau dan berenergi besar. Itulah yang salah satunya disebut matahari. Matahari memiliki energi dan juga memberi gaya tarik besar yang nantinya dikenal dengan nama gravitasi. Di sekelilingnya, melayang-layang debu dan puing tanpa punya arah, lalu kemudian menjadi memiliki jalur akibat gravitasi tersebut. Debu dan puing itu sendiri kemudian tarik-menarik, karena mungkin memang terbentuk pula gravitasi di antaranya. Lama kemudian, jadilah rumah kami para manusia. Bumi namanya. Dikirim oleh pemilik matahari. Galileo terkenal karena mengemukakan matahari adalah poros tata surya, secara tidak langsung muncul pernyataan bumi itu bulat, namun dia harus berbeda pandangan terhadap hukum gereja. Terima kasih kepada Galileo, Colombus akhirnya berani turun ke laut dan tak sengaja menemukan Amerika. Menuju luar angkasa, Clyde Tombaugh telah menemukan Pluto sebagai planet ke sembilan, dalam tata surya, namun masih diperdebatkan pada kala itu. Kembali ke bumi, Cavalier-Smith sudah mengemukakan teori kalau makhluk hidup di bumi ini termasuk di dalam delapan hirarki kerajaan, tapi banyak pula yang tak percaya Darwin karena mereka salah paham atas teori itu. Itulah pikir mereka yang sesat pikir sebab tidak paham akan sains. Di dalam kerumitan dunia itu, mamak dan bapakku telah sepakat bahwa aku akan ada, dan diberi nama Nando Hutria Walace, meski usai hari itu mamakku menjadi tidak ada.
2 0 1 8 Perdebatan soal konspirasi evolusi berawal sejak Darwin membuat gebrakan luar biasa. Banyak orang pada masanya membuat sang Charles Darwin seolah-olah mengatakan manusia berasal dari monyet. Orang-orang itu terus ada, mengatakan Pithecantropus erectus dari Trinil itu bohong. Orang kerdil di Flores itu propaganda. Orang pendek di pulau kami ini dongeng. Sejauh yang kutau, orang pendek memang hanya fiksi. Itulah salah satu cerita rakyat turun temurun untuk melindungi hutan kami di negeri Minangkabau. Tapi, bukan itu intinya. Ini tentang orang yang mengatakan bahwa sains adalah fiksi, penganut teori bahwa bumi ini datar, dan bagi yang sesat pikirnya soal konsep evolusi. Umurku lima tahun sejak pertama kali pikiranku mengawang-ngawang tentang apa itu manusia, kenapa manusia bisa lebih bermartabat dibanding hewan, dan macam-macamnya. Datuak guru mengajiku di surau itu berkali-kali mengulang titah bahwa manusia diturunkan sebagai pemimpin, yang akhirnya berujung pada bapakku yang kena tegur karena aku masih gagal paham. Sekarang, pertanyaan mendasar itu bertambah. Apa itu yang bukan manusia? “Malam.” Kakaknya Erna baru pulang. “Malam, Wan.” Jawabku. “Apa kabar Erna hari ini?” “Mau diajak ngobrol sedikit.” Aku sadar diri telah menumpang gratis dan lama di rumah ini. Menyiapkan makan sehari-hari adalah balas budi yang bisa kulakukan. Kalau saja bukan karena hanya aku yang rela memulihkan Erna cuma-cuma, Erwan dan ibunya mana mau mengizinkan orang asing tinggal di rumah mereka.. Jadi, kusajikan apa yang bisa kumasak selama siang tadi. Seekor ayam yang telah menjadi potongan benda mati itu tersedia di atas piring, di atas meja makan. Ada sayapnya, ada pahanya, ada kepalanya, dan ada kakinya yang lebih sering dibuang kalau di restoran cepat saji. Ada pepaya muda untuk sayurnya. Cukup itu untuk hari ini. Untuk rumah yang penghuninya hanya empat orang. “Wan, gue panggil Erna dulu ya.” Aku pergi dari hadapan Erwan. Kemudian, aku pergi ke depan pintu kamar Erna untuk mengetuknya supaya berbunyi dan diperhatikan. Pertanyaan yang mengawang di kepalaku kembali. Apa itu yang bukan manusia? Apakah mereka yang tidak berakal, tidak berpakaian, seperti makhluk lainnya selain Homo sapiens? Tapi kalau terbukti ada makhluk yang lebih berakal nun jauh di angkasa sana, bagaimana? Apa itu yang bukan manusia? Apakah mereka yang tidak beradab sehingga dianggap lebih hina dari anjing? Sehingga mereka menyebabkan Erna seperti ini? Tapi mereka tetap Homo sapiens juga, kan? — 1 9 9 9 “Nando, bawalah kopi semua ni ke depan untuak tamu bapak.” Mak etek memanggil. Mak etek adalah istilah yang sama dengan tante, jadi artinya dia lebih tua dan aku harus menuruti kata-katanya barusan. Mak etek ini adik perempuan bapak yang terpaut jauh usianya, tapi aku tak peduli. Aku tetap harus menuruti perintahnya. Kuantarkan 6 gelas kopi hitam ke ruang besar di atas nampan, beserta piring-piring kecil. Aku seringnya disuruh begitu, karena kemudian aku selalu melihat orang-orang meminum kopi yang dituangkan dari gelas ke piring itu. Kukira karena untuk mempercepat kopinya dingin, tapi bapak bilang itu tentang kenikmatan. Aku disuruhnya menunggu cukup umur supaya bisa menikmati kopi. Hari ini panas meski rumah kami di kaki gunung. Tapi, alas rumah kami selalu sejuk karena ada semilir angin yang berhembus dari bawah, dari sela-sela papan kayu. Untuk tempat duduknya supaya agak nyaman digelarlah tikar pandan, terkhusus saat ada tamu seperti sekarang. Atau saat aku mau tidur-tiduran. Aku seringkali ketiduran di atas tikar itu saat siang. Lalu ketika bangun, separuh wajah hingga tanganku berceplak anyaman tikar. Rasanya lumayan gatal, apalagi kalau tikarnya sudah lama tidak dijemur. “Tarimo kasih.” Kata salah satu tamu bapak yang berewok. “Gaya banget pake bahasa minang segala. Baru juga dua hari di sini.” Ledek temannya yang lain. Bapak-bapak itu lalu tertawa dengan sopan. Bapak berewok juga ikut tertawa, paling lebar. Kukira bapak berewok itu seram. Kulitnya lumayan gelap dan badannya paling besar di antara yang lain. Lihatlah rambut, kumis, dan jenggotnya yang menyatu di area dagu dan formasinya yang berantakan. Tapi pada nyatanya beliau sangat menyenangkan buatku dan justru sangat lucu di antara kawan-kawan bapak yang lain. Kemudian, aku dihasut oleh kawan-kawan bapak untuk memanggil bapak berewok itu menjadi om berewok. Begitulah aku harus memanggil seterusnya. Dia pun tidak seram, jadi aku tidak sungkan memanggilnya begitu. “Hahaha, om berewok.” Ledek temannya yang lain. “Wis, ini aset lah.” Jawab om berewok, sambil menggaruk-garuk janggutnya Kemudian, aku kembali ke belakang untuk kembali kepada Mak Etek. Masih ada pisang goreng yang harus disajikan. Tadi pagi ada dua sisir Mak Etek beli dari balai. “Mak Etek kenal kawan-kawan bapak?” Tanyaku. “Mereka kawan lama bapak dari Jawa waktu merantau dulu.” Jawab Mak Etek. “Mau apo kemari?” Tanyaku lagi. “Penelitian katonyo. Masuak rimba.” Aku lalu diam dengan banyak makna di dalam kepala. Mereka mau apa masuk ke hutan. “Bawalah ni pisang goreng.” Perintah Mak Etek. — Di negeri kami, orang cerdik pandai selalu menjadi tokoh masyarakat yang disegani. Derajatnya sama dengan kepala desa dan ustadz. Maka itu, setiap guru ngaji di surau tidak pernah memarahi bapak berlebihan akibat aku terlalu banyak bertanya hal-hal yang mereka tidak bisa jawab. Kenapa gula itu manis dan garam itu asin, misalnya. Atau bagaimana rangkong bisa terbang, tapi ayam tidak bisa. Padahal, rangkong dan ayam sama-sama punya sayap. Cuma bapak yang selalu punya jawabannya, karena beliau orang cerdik pandai. Bapak selalu berdalih kepada orang-orang bahwa Nando itu sedang berumur lima tahun. Itulah masanya anak-anak ingin tahu segala sesuatu. Kemudian, di waktu yang lain, bapak juga beralasan bahwa beliau habis bercerita, atau aku habis membaca buku milik bapak. Jadinya, Nando banyak bertanya. Semua menjadi lingkaran yang berulang. Aku bertanya, mereka tidak bisa menjawab, bapak punya alasan, aku punya pengetahuan baru lagi, aku jadi berpikir, aku bertanya lagi, dan bapak beralasan lagi. Tidak ada yang bohong dari semua alasan bapak. Tapi sepertinya kebanyakan orang tidak begitu suka, karena aku banyak bertanya dan mereka tidak bisa menjawab. Pada akhirnya, aku mulai paham kenapa semua anak-anak lain tidak mau main ke ladang denganku. — Tiga hari kemudian, bapak pulang bersama kawan-kawannya dari hutan. Kata Mak etek, mereka menuju banyak bukit di dalam hutan sana. Jadi perlu waktu yang lama untuk menjelajah. Aku menunggu mereka tepat di depan pintu rimba selama setengah hari, dan mereka baru muncul mendekati matahari terbenam. Pastinya bapakku kaget ada aku di sana, sendirian tanpa ditemani Mak etek. “Apo pulo sendirian di sini ni?” Kata bapak. “Bapak pulang, bapak pulang.” Itu aku berbahagia. Tidak ada yang lebih senang melihat orang tuanya pulang dari mana. Om berewok pun tertawa paling keras melihat tingkahku yang sangat bahagia dan tidak menjawab pertanyaan bapak. Mereka penuh peluh, tapi masih membawa barang-barang yang berat, dan… apa itu, ada oleh-oleh dari hutan. “Apa itu? Apa itu?” Aku memencet tas-tas mereka. “Nando, idak sopan.” Tegur bapak. Malam hari hingga dua hari kemudian, banyak sekali kegiatan di rumahku. Tapi bukan pesta. Di atas lantai kayu, ada berbagai bangkai makhluk hidup yang dibawa om-om ini. Banyak tumbuh-tumbuhan kering di dalam kertas koran, ada macam-macam ular dan tikus di dalam botol cairan yang baunya sangat menyengat, ada serangga yang sudah ditusuk-tusuk jarum. Ada juga botol-botol berisi tanah dengan segala jasad reniknya. Mak Etek bahkan sampai mengungsi menginap di rumah saudara karena tak tahan dengan perubahan aroma di rumah kami. Bapak juga tidak ada waktu bercerita macam-macam padaku seperti biasanya. Akulah yang pelan-pelan punya pertanyaan sendiri. Makhluk apa saja itu? Kenapa diperlakukan seperti itu? Kemudian akan diapakan itu? Pokoknya hal yang macam-macam. Setelah pertanyaan satu-satu terlontar, aku menjadi sangat bahagia dengan respon kawan-kawan bapak. Tidak seperti orang dusun, mereka mau menjawab semuanya! Bahkan aku bisa paham apa yang mereka katakan, khususnya om berewok. “Ini namanya herbarium. Nanti disimpan sampai ratusan tahun untuk bukti bahwa tumbuhan ini pernah ada.” Kata om berewok. “Ini cairan formalin namanya. Hewan yang sudah mati harus diawetkan pakai ini supaya gak busuk.” Kata kawan bapak yang gendut. “Ini nanti akan dibawa ke pulau Jawa. Koleksi kita ada di sana semua dari zaman Belanda.” Kata om berewok lagi. Saat itu aku akhirnya punya dua cita-cita. Satu, masuk ke dalam hutan untuk melihat bentuk asli makhluk-makhluk yang mereka bawa. Bukan yang sudah mati seperti itu. Dua, merantau ke Jawa. Katanya di sana ada pusat koleksi makhluk hidup yang diawetkan dari seluruh Indonesia. Lalu, aku sangat beruntung di usiaku yang baru lima tahun. Waktu itu, belum umurku untuk masuk bersekolah. Aku masih bebas diajak ke manapun. Mereka akan masuk hutan lagi dan aku diajak. Itu pun melalui perdebatan yang lumayan alot. Om berewok meyakinkan aku bisa ikut karena apa-apa yang mereka cari di sana tinggal sedikit, dan menjaga satu anak kecil dari adanya Harimau masih mudah. Di hutan, aku menginap satu malam. Bapak bertanggung jawab mendirikan tenda di salah satu puncak bukit yang masih belum punya nama. Benar pula, di saat pertamaku masuk hutan, aku melihat banyak hal. Termasuk bayangan harimau yang lewat sekitar tenda. Sangat tak terlupakan. “Itu harimau, pak?” Tanyaku. “Ssst.” — Dua minggu kemudian, cita-citaku yang satunya lagi terkabul. Pergi ke Jawa. Cepat sekali! Berdoa supaya cita-cita terkabul saja belum sempat. Bapak diajak pergi ke Jakarta oleh kawan-kawannya, dan aku bisa ikut. Dua minggu kami boleh tinggal di sana. Kami pun meninggalkan Mak etek yang harus menjaga rumah meski rumah kami masih bau cairan formalin. “Pak, Jawa sebelah mano, Pak? Kenapo lamo nian.” Aku bertanya berulang selama perjalanan. Lama sekali untuk sampai tujuan. Dua hari dua malam kami habiskan di atas bis. Ini pun kali pertamanya aku naik kapal laut besar. Mobil bisnya bisa masuk ke dalam perut kapal, lalu kapal berlayar di atas air yang sangat luas wilayahnya. Sesampainya di Jawa, hari sudah malam menjelang pagi. Aku dan bapak tinggal di rumah om berewok. Tepatnya di kota Bogor. Tidak begitu dingin hawanya dibanding di dusun, namun tetap menarik. Aku tak sabar besok akan diajak pergi ke mana. Sisa malam itu sepi. Bapak menyuruhku untuk cepat tidur. — Ini pagi hari sepertinya. Aku terbangun akibat suara berisik melengking anak perempuan. Dia teriak-teriak, tapi bukan menangis, tapi senang karena orang tua laki-lakinya sudah paling dari Sumatra. Dari dusunku. Dari kamar, aku keluar. Di depan tivi, aku melihat om berewok mengelitiki anak perempuannya berulang kali. Kemudian berhenti setelah melihat aku berdiri di depan pintu kamar. “Nando, kemari lah. Kenalan.” Panggil om berewok. Aku datang, tidak dengan malu-malu, karena aku tidak pernah merasa sungkan untuk menemui hal baru. Apalagi ini di tempat baru. “Siapa namanya?” Om berewok mendikte anaknya. “Nando.” Jawabku “Niken.” Sahut si perempuan. Niken lebih tinggi dariku. Pasti dia lebih tua. Dan dia menarik perhatianku. Kami hendak bersalaman. Tapi, tiba-tiba telapak tanganku terasa digigit semut banyak sekali. Sepertinya Niken juga begitu, karena kami berdua sama-sama menarik tangan kembali. “Aduuh, semut apiii!” Teriak niken. Dia lalu berlarian ke kamar mandi untuk cuci tangan. Sedangkan aku hanya mengusap-usap tanganku ke celana. “Semut? mana coba lihat?” Om berewok meminta tanganku. “Ini.” “Gak ada semutnya kok.” Om berewok juga melihat celanaku dan lantai sekitar. Beliau memastikan apakah benar ada semut atau tidak. Tapi, tidak selesai karena ada suara motor yang datang di luar. rumah “Nah itu bapaknya Nando datang.” Om berewok pergi ke depan. Bapak pulang membawa sarapan dan kue-kue ditemani ibunya Niken. Kemudian, motor dibawa pergi lagi sama om berewok untuk pergi ke mana membawa awetan tumbuhan dan hewan di dalam tas-tasnya. Aku bercerita kepada bapak kalau tadi tanganku digigit semut. Bapak menjawab itu karena aku belum gosok gigi. Memang tidak nyambung, tapi aku menurut untuk disuruh gosok gigi sekaligus mandi, supaya bisa menikmati kue. Di depan kamar mandi, Niken baru saja keluar sambil masih menggaruk-garuk tangannya. “Gateeel.” Gumamnya. Setelah semua kenyang, berganti pakaian, menonton rangkaian kartun, dan om berewok telah kembali dari mana dengan tas yang sudah kosong. Kami pun diajak pergi ke Kebun Raya Bogor. Ini hari Minggu dan Niken bisa ikut, karena rupanya dia sudah sekolah kelas 2 SD. “Aku ikut!” Pinta Niken. “Iya, ikut.” Sahut bapaknya, om berewok.
Kebun Raya Bogor buatku terdengar seperti kebun berisi deretan cabai dan singkong di dusun, tapi rupanya tidak begitu. Itu tempat wisata. Di sana banyak orang lain yang datang selain kami. Semakin siang, semakin ramai. Om berewok bilang, bertahun-tahun ke depan tempat ini pasti ramainya akan minta ampun. Apalagi ini Bogor, dan bogor menjadi kota yang akan semakin mudah diakses dari Jakarta. Tapi bukan itu yang membuatku tertarik, melainkan cerita om berewok tentang kebun ini yang dibentuk sejak masa penjajahan Belanda, sekitar tahun 1700an. Kebun Raya ini dibangun dari bentukan taman buatan peninggalan kerajaan Siliwangi, ceritanya. Aku tidak suka penjajahan, tapi apa yang dilakukan orang-orang lampau itu hebat karena peduli juga dengan hutan. Kemudian, aku tidak bisa diam dan jadi banyak bertanya lagi. Itu membuat om berewok harus mengajakku keliling ke tempat-tempat yang sepi. Karena, di sanalah ada pohon-pohon yang umurnya sudah ratusan tahun, yang dikoleksi dari pulau-pulau lain. Peserta tur dadakan yang ikut akibat keingintahuanku adalah aku sendiri, bapak, om berewok, dan Niken. Ibunya Niken tetap tinggal di tempat kami duduk-duduk karena repot dengan rantang makan siang. “Ada yang unik, ayo lewat sini.” Om berewok memimpin jalan. Ada satu pohon yang dianggap unik oleh pengunjung, tapi sebenarnya biasa saja buat om berewok. Pohon jodoh namanya. “Kenapa pohon jodoh, Om?” Tanyaku. “Ini pohon kebetulan aja sebelahan, yang satu beringin, satunya lagi kenari.” Jawab om. “Umurnya berapa?” Tanyaku lagi. “Berapa ya, seratus tahun lebih lah. Mungkin 130 kali ya hahaha.” Aku kemudian takjub. Kepalaku menengadah ke atas dengan mulut yang menganga. Mataku mencari-cari ke mana saja arah batang itu melebar. Di manakah letak daun-daunnya. Lalu kepalaku turun ke pangkal batangnya. Batang itu melebar dan memipih dahulu sebelum masuk ke dalam tanah. Besar sekali. “Ayo kalian foto lah di sini.” Suruh om berewok. Kami kemudian berfoto menggunakan kamera tustel milik om berewok. Pertama, aku dan bapak. Lalu ditemani Niken. Kemudian, bapak bertukar memegang kamera, lalu aku berfoto dengan om berewok dan Niken. “Nando foto lah dengan Niken berdua.” Suruh om berewok. Om berewok tidak peduli itu pohon punya misteri apa. Pohon adalah pohon, perlu dilindungi, tapi tidak perlu dipuja-puja. Aku sekarang berdiri dengan kakunya di samping Niken. Kulihat dia menggenakan celana pendek yang menyatu menjadi semacam rompi. Bajunya garis-garis pink tersembunyi di balik rompi itu. “Kenapa jauh-jauhan begitu. Peganganlah tangan kalian.” Om berewok memberi arahan. Niken dan aku dipaksa pegangan tangan. Tepat sekali waktunya ketika rasa digigit semut yang banyak itu datang lagi bersama dengan cahaya putih dari kamera menghantam mata. Mataku silau sekali… Semuanya memutih… “Apo ni?” Aku hanya melihat warna putih. Apakah ini? Aku di mana? suaraku membesar? Kenapa telanjang begini ? Dan… Aku entah ada di mana dengan latar ruang lebar merwarna putih bersih. Lalu ada suara melengking perempuan dari arah belakang. “AAAAAK!” Itu perempuan asli. “AAAAAK!” Aku juga ikut teriak. Aku dan dia berhadapan sebentar sekali. Lalu kami kembali saling membelakangi satu sama lain. Aku melihat perempuan dewasa telanjang untuk pertama kali! Ih. Aku pun bukan seperti aku. Kenapa aku bisa jadi orang dewasa secepat ini? Kapan aku pernah sekolah SD, SMP, sampai kuliah? Banyak sekali yang aku lewatkan sampai bisa tumbuh besar begini!? “Kamu siapa?!” Tanya perempuan itu. “Kau siapo?!” Tanyaku balik. “KAMU SIAPA?!” Bentak dia. Aku harusnya yang bertanya. Memangnya siapa lagi. Siapa juga perempuan itu bisa membentakku. “KAMU SIAPA??!” Perempuan itu bertanya lagi. “Kamu siapa?!” Aku tanya balik. Lalu semua memutih lagi.
Siapa?
BERSAMBUNG
Episode 2
Ular Apa? 2 0 0 2 Membaca adalah jendela dunia. Itu kata pepatah lama. Kamu bisa melihat segala isi dunia, bumi, semesta, galaksi lain, dimensi lain, dan apapun yang lain dari membaca. Sayangnya, aku sudah terlanjur suka membaca buku tanpa perlu dinasehati pepatah seperti itu. Buku pertamaku adalah buku bergambar untuk anak-anak. Kisah-kisah yang bersangkutan dengan agama itulah yang wajib dibaca anak-anak dusun kami. Setelah dibaca, lalu dilaporkan ke datuak di surau selepas maghrib. Ada rapor yang perlu ditandai setelahnya. Ketertarikanku soal membaca makin menyeruak ketika bapak mulai mengizinkan aku membuka-buka lemari buku miliknya. Kata bapak, itulah buku-buku pemberian om berewok selama bapak merantau ke Jawa sekian belas tahun lalu. Buku-buku bapak tidak banyak gambar dan lebih banyak tulisan, jadi aku tertantang untuk bisa membaca. Waktu itu ada buku besar dengan sampul berwarna mayoritas biru. Judulnya Kepulauan Nusantara. Penulisnya tertulis besar-besar bernama Alfred Russel Wallace. Itulah titik pertamaku mau bisa membaca. “Yakin kau mau belajar membaca sekarang?” Bapak bergurau. “Yakin!” Jawabku mantap. Sejak itu, bapak suka pulang lebih awal dari ladang atau dari mana. Semua demi mengajariku membaca dan menulis sebelum waktunya matahari turun lagi ke arah barat. Seperi kemarin-kemarin. Sampai suatu hari, bapak pergi di hari minggu untuk ke balai. Kemudian, bapak kembali bersama tiga poster yang akhirnya tertempel di dinding rumah, di dekat televisi. Ada satu poster alfabet, satu poster bahasa arab, dan satu lagi poster nama sayur-sayuran. Dua bulan kurang, katanya, aku sudah mahir mengeja huruf. Sebulan kemudian, sudah lewat pula masa mengejaku. Tepat di bulan saat aku didaftarkan sekolah dasar, aku bisa membaca dan menulis lancar sekali. Aku menjadi perhatian satu orang dusun sekaligus menjadi bahan iri mereka untuk anak-anaknya. Wali kelas saat itu juga bangga. Tapi lambat laun beliau sepertinya kerepotan. Aku terus meminta buku-buku bacaan yang harusnya dibaca anak kelas empat. Kegembiraan menyertaiku setelah bisa membaca. Banyak hal untukku mengisi waktu luang saat kawan-kawan masih menulis huruf A besar dan kecil sebanyak satu halaman. — Tidak banyak yang tau, kecuali bapak, bahwa aku memerhatikan poster sayur-mayur dengan seksama setiap harinya. Bersama buku-buku dari kelas empat itu, aku semakin penasaran dengan yang namanya ilmu pengetahuan alam. Lama-lama aku merasa tidak cukup dengan tulisan. Maka, hampir setiap hari aku pergi ke ladang hingga ke pintu rimba. Kadang, aku juga berani menerobos hujan kalau sedang tidak ada angin kencang. “Hoi, Nando! Hendak kamano??!” Ada suara memanggil. Aku menoleh ke sumber suara yang serak itu. Beliau yang memanggil rupanya datuak, sang kepala dusun. Kepala datuak menyembul dari jendela rumah panjang miliknya. Sebagian rumahnya itu sudah direnovasi menjadi semen dan sebagian lagi masih berupa kayu. Di bawah rumah beliau banyak sekali ayam. Beliau itu memang suka menjual ayam di balai, maka uangnya selalu banyak untuk memberi jajan anaknya yang enam orang. Padahal umurnya terlalu tua untuk punya anak yang mayoritas masih sekolah. Anak pertamanya sering kupanggil Uda Mirza. Uda Mirza satu-satunya anak datuak yang sudah merantau ke Bukittinggi. Itulah satu-satunya kota besar yang menjadi tujuan merantau umat dusun kami. Tidak menyeberang ke Jawa, bahkan tidak pindah nagari, karena sebagian besar orang masih punya saudara di sana. Jadi, tidak perlu takut kelaparan ketika tidak punya uang. Anak terakhir datuak itu satu kelas denganku. Novia panggilannya. Sama juga seperti anak-anak yang lain, dia dilarang untuk sering-sering main denganku. Anjuran itu pasti disuruh ibunya, atau bapaknya, atau kedua-duanya. “Ka ladang!” Aku teriak dari jalan. Tak perlu malu untuk teriak, karena sebenarnya kami bukan teriak. Beginilah budaya kami orang-orang pulau Sumatra, kata beberapa orang tua yang kucuri dengar. Tapi untuk yang satu ini aku sengaja berteriak karena tidak mau lama-lama terhenti oleh datuak. Bapak kepala dusun yang satu itu sudah sering menyapaku sejak pulang dari Jawa tahun lalu. Tapi aneh rasanya. Aku punya perasaan tidak enak dari perilaku orang-orang dusun setelah dari Jawa itu. Lalu, kuabaikan datuak. Di ladang, aku selalu mengingat-ingat apa yang kupelajari dari poster sayur. Selain itu, ada juga informasi yang aku peroleh dari buku-buku sekolah. Maka, kucari tumbuhan-tumbuhan mana saja yang bentuknya sama seperti di semua gambar. Aku menggali tanah untuk melihat seperti apa bentuk kentang yang masih ditumbuhi daun-daun. Aku membongkar kembang kol untuk mencari tau kenapa kembang kol tidak seperti kembang lainnya. Pada hari lain, aku belajar tentang hewan-hewan. Burung, cacing, capung, sampai tupai. Semuanya aku cari supaya bisa melihat bentuk asli mereka. Tapi nyatanya yang satu ini sulit, karena mereka cepat kabur segera setelah kedipan pertama. Kecuali cacing, tapi cacing membosankan. Butuh berhari-hari buatku untuk bisa membedakan jenis kupu-kupu dari warna-warna sayapnya yang mirip. Butuh satu minggu lebih untuk terbiasa membedakan warna bulu burung yang sedang terbang di atas kepala. Bahkan, butuh hampir satu bulan untuk mencari sarang seekor bajing. “Nando! Nak!” Itu suara datuak lagi. Aku sedang mengamati bajing yang sedang makan buah ketika kepala dusun datang menghampiri sambil berteriak-teriak. Alhasil, bajing itu lari ke pucuk-pucuk pohon paling atas. Dia melompat dari satu pohon ke pohon yang lain hingga akhirnya menghilang dari pandanganku. Aku menggerutu. Kenapa datuak ke sini. Apa urusannya. “Yaaah. Apo pulo Datuak ni. Lari lah bajing tu, ha.” Aku kesal, jadi kusalahkan kepala dusun tua itu karena menganggu pengamatanku semau-maunya. Tapi, karena datuak orang tua, beliau langsung memarahi balik diriku dengan alasan macam-macam. Awalnya, aku dimarahi akibat pulang sekolah langsung pergi main tanpa ganti baju. Tadi, berubah alasan lagi karena aku berada di depan pintu rimba sendirian. Aku sudah sering sendirian di pintu rimba. Bahkan aku pernah satu kali masuk ke dalam hutan sana saat kawan-kawan bapak pergi berkunjung. Kalau dibandingkan, memangnya datuak sudah sebanyak apa masuk ke dalam hutan. Aku yakin beliau masih kalah sering menjelajah dibanding bapak. “Pulang!” Bentak datuak. Itulah tipikal orang tua. Kalau orang tua sudah marah, apa bisa dikata. Sebaiknya memang aku menyudahi jelajah hari ini. Sesampainya di rumah, terjadi debat antara datuak dan bapak. Seorang kepala dusun dan orang cerdik pandai beradu mulut. Ini pertama kalinya pula aku melihat bapak tidak mau berdamai setelah tiga atau empat kalimat. “Tau anak wa’ang main ke pintu rimba hampir setiap hari, tapi idak dilarang. Orang tua macam apo, wa’ang, ha?!” Hardik datuak Bapak jadi ikut marah karena dibilang tidak becus mendidik anak. “Nando itu anak awak! Awak paham caronyo!” Bapak membela diri. “Lalu, Nando kena sakit ayan itu karena wa’ang pandai mandidik?!” Ayan. Epilepsi. Bapak pernah bilang bahwa epilepsi yang kualami di tanah Jawa itu di luar dugaan. Kata Mak Etek pun, tidak ada riwayat penyakit epilepsi sejak aku lahir. Penyakit itu murni muncul sekali-sekalinya hanya saat di Kebun Raya Bogor tahun lalu. Selanjutnya, aku sehat-sehat saja. Siapa yang tau juga penyakit epilepsi bisa terjadi bersama-sama terhadap aku dan Niken. Lagipula antara bapak dan om berewok tidak ada yang mempermasalahkan kejadian waktu itu. Sayangnya, kabar apapun pastilah jadi heboh ketika masuk dusun. “Nando sehat sampai sekarang! Idak ado masalah!” Bela bapak lagi. “Wa’ang harus tau, itu penyakit dari penunggu pohon! Datangnya dari iblis!” Bentak datuak. Aku diam menelan bulat-bulat banyak kalimat datuak yang masuk ke dalam telinga. Selain kata iblis barusan, semua kata-kata datuak berisi penghinaan kepada bapak, seorang cerdik pandai. Padahal, bapaklah orang pertama dari dusun yang berani merantau ke Jawa. Bapaklah yang kembali pulang ke dusun membawa pengetahuan dan perubahan bagi dusun supaya adatnya mau terbuka dengan dunia luar. “Datuak memang tidak suka dengan bapak, Nando. Idak usah didengarkan.” Mak Etek berbisik. Aku menoleh sebentar. “Lain kali kalau hendak pergi ke luar, minta temani Mak Etek atau bapak.” Begitu pesan Mak Etek. Perdebatan hari itu akhirnya berakhir karena suara panggilan istri sang datuak. Sepertinya sang istri malu karena kelakuan pemimpin dusun. Itu tampak dari kedua kulit pipinya yang turun pertanda murung. Apalagi, di luar rumah semakin banyak orang yang berkumpul. Aku masih tidak terima dengan cercaan datuak kepada bapak. Sampai malam, masih banyak kata-katanya yang tak mau hilang dari dalam kepalaku. Sampai-sampai, aku tak selera untuk membaca buku seperti biasanya. Malam itu pulalah aku putuskan untuk tidak menyukai datuak. Semua yang berhubungan dengan bapak tua itu tidak boleh aku tanggapi sebagai bentuk protes. Lagipula aku sudah biasa hidup tanpa kawan. Novia bukan pula kawanku. — Hari-hari berikutnya, aku tetap pergi ke pintu rimba. Tapi, kali ini selalu ditemani bapak, atau kadang aku lari sendirian akibat rasa penasaran yang tak bisa ditahan. Saat sendirian itu, aku lebih memilih ambil jalan memutar melewati ladang cabai Mak Tuo Sulo di dekat sungai. Itu supaya aku tidak melewati rumah sang kepala dusun. Awalnya, aku cukup khawatir karena ternyata Novia suka bermain masak-masakan dengan kawan-kawannya di sana, di atas batu gadang. Aku sempat curiga dia akan melapor kepada orang tuanya yang berujung perdebatan orang tua kami lagi. Tapi, seiring berjalannya hari, kehawatiranku tak berguna. Sampai pada hari Minggu waktu itu. Aku mengabaikan acara televisi pagi-pagi yang harusnya diminati setiap anak-anak. Kartun itu memang lucu, menghibur, tapi buatku tidak menambah wawasan sama sekali. Tapi, bapak sedang mencuci dan Mak Etek sedang belanja ke balai. Jadi aku kembali pergi ke pintu rimba sendirian. Targetku di pintu rimba hari ini adalah mencari telur burung mandar. Aku lewat ladang cabai Mak Tuo lagi. Seperti dugaan, ada Novia di sana, tapi sendirian. Aku melihatnya, dan dia melihatku. Mungkin teman-temannya masih asik menonton kartun di tivi tabung mereka masing-masing. Andai saja bapakku tidak berani berpesan kepada pemerintah daerah sini, bisa jadi dusun kami belum dialiri listrik. Datuak pun mana terpikir untuk hal semacam itu. Aku yakin di kepalanya hanya dipenuhi beternak ayam kampung dan hal-hal mistis lainnya. Aku biarkan Novia sendirian. Menyapanya pun tidak. Ini kulakukan karena prinsipku yang sudah tak mau berurusan dengan datuak dan semua sanak saudaranya. Serta juga karena teman sepermainan yang berlawanan jenis sangat tidak wajar di dusun. Lepas dari ladang cabai, aku terus menyusuri jalur setapak yang semakin padat semaknya. Jalan setapaknya hampir tidak terlihat karena rumput makin tumbuh tinggi di tengah-tengah. Kupu-kupu sedang banyak beterbangan di atas bunga-bunga yang warnanya merah itu karena semalam sudah hujan. “Nandooo! Tungguuu!” Ada suara anak perempuan dari belakangku. Itu suara Novia, aku kenal suara beratnya. Suaranya hampir seperti Mak Tuo yang hobinya merokok itu, tapi suara Novia tidak serak kalau didengar. Kuperhatikan ke jalan setapak arah aku datang tadi. Dari balik semak rapat muncul lah dia, bocah perempuan bernama Novia. Kenapa pula dia harus mengikutiku? “Kenapo ikut awak? Pulang lah!” Aku kesal. “Ikut.” Dia meminta. “Pulang!” Kataku lagi, makin kesal. “Awak ikut lah. Atau awak laporkan ke bapak.” Bapak dan anak sama saja. Sama licik dan berbahaya mulutnya. Terpaksa aku ajak Novia ikut denganku. Petualanganku di pintu rimba hari ini harus kubatasi jadinya. Kalau dia kena semak gatal, akulah juga yang repot nantinya. Apalagi kalau sampai bertemu ular. “Cari apo kau sendirian ni?” Novia sudah mulai bawel. “Berisik.” Balasku singkat. “Mau awak laporkan bapak?” Pantek! Kalau saja aku tidak harus menjaganya. Kutinggalkan Novia sendiri di sini. Kujelaskanlah hal-hal yang kupelajari di hutan, tentang kentang, kembang kol, kupu-kupu, burung, hingga bajing. Segala sesuatu yang menakutkan untuk dialami anak umur enam tahun juga kuceritakan supaya Novia takut. Supaya Novia mau pulang cepat-cepat. “Kenapa idak main dengan kawan-kawan?” Novia malah bertanya terus. Pikirlah sendiri kenapa aku tidak main dengan mereka, dengan kamu. Itu kataku dalam hati. “Kau kenapa idak main dengan kawan-kawan?” Kutanya balik. “Asik dengan kartun lah mereka tu.” Benar, kan. Kartun. Pintu rimba sudah dekat. Tapi, sesaat waktu berjalan, aku melihat ada semak yang bergoyang dengan cara tidak wajar di sebelah kiriku. Ada gerakannya yang memanjang dan lama. Sayangnya, aku tidak bisa melihat apa penyebabnya meski jarakku dan semak itu sangat dekat. Maka, kuhentikan langkahku dan Novia untuk mencari tau apa itu. Aku yakin ini bukan bunglon, karena tidak ada bunglon yang nampak. Bukan juga… “IH! IH!” Novia teriak. Itu dia! Akhirnya aku melihat makhluk itu. Matanya kuning dengan garis hitam yang mendatar. Tubuhnya panjang, kecil, dan hijau, bergerak lambat di antara batang-batang semak dan daunnya. Itu ular. Itu ular… apa namanya? “IH!! NANDOO, AYO PULANG!” Novia mulai ngeri sendiri. Hasratku seketika bercabang. Di satu sisi aku gembira Novia minta pulang. Tapi hati nuraniku berkata untuk mengamati makhluk itu lebih teliti. Sepertinya ular yang satu ini tidak berbahaya karena dia kecil. Ukuran badannya hanya sebesar jari telunjukku. Aku memilih dengan sangat instan untuk tidak mengabulkan permintan Novia. Lebih aman kusuruh dia ke belakangku. Lalu, aku bisa dengan mudah menangkap ular itu. Inilah ular pertama yang akan kutangkap dengan tangan sendiri. “Hati-hati…” Novia ketakutan. Aku pernah membaca di bukunya bapak, kalau menangkap ular, peganglah kepalanya. Selain piton dengan ukuran kepala sebesar telapak tangan, maka dia tidak akan bisa memakan manusia. Ular itu sadar dengan keberadaan kami, lalu dia bergerak menjauh dengan lambat. Aku bisa mengikutinya ke semak yang makin rapat. Sebelum kehilangan, kutarik badannya ular itu supaya mendekat. Supaya aku bisa melihat kepala dan matanya lagi. Lalu, kini kepalaku dan luar itu berhadap-hadapan. Inilah dia, leher ular itu membentuk huruf S pertanda ingin menyerang. Aku sepenuhnya siap dengan tangan kananku. Kudorong tanganku ke depan… “NANDO!!” Novia teriak. Aku kaget gara-gara Novia. akibatnya tanganku meleset dari kepala ular itu. Seketika pangkal jari jempolku digigitnya. Sakitnya seperti ditusuk beberapa jarum pentul bersamaan. Perih. Untungnya hanya gigitan yang sebentar sampai ular itu lepas lagi. Kali ini kubiarkan ular itu pergi supaya aku bisa melihat tanganku yang mengeluarkan darah. Aku tidak menangis. Hebat. Cuma, Novia dari tadi masih panik. “Itu berdarah! Ayo pulang Nando!” Apa yang harus kulakukan? Ayo ingat-ingat buku bapak… Tadi ular itu tidak membelit saat aku digigit. Berarti.. itu ular berbisa? Tenang, aku ini bukan anak cengeng. Apa lagi yang aku pernah baca dari buku-buku bapak? Gigitan ular? Apakah berbahaya? Berbahaya? Aku bisa mati kalau begitu? “Nando! Ayo pulang!” Itu suara Novia yang aku abaikan. Novia mulai menarik-narik tanganku untuk cepat pergi dari tempat ini. Tapi, badanku rasanya jadi panas… Pandanganku memutih… Aduh, ini sudah lama, jangan lagi… — Tempat putih ini. Sudah setahun aku tidak di sini sejak aku serangan epilepsi tahun lalu. Itu pun hanya sebentar. Tempat ini antah berantah. Rasanya asing sekali meski sudah pernah kukunjungi satu kali. Kulihat badanku. Aku kembali jadi orang dewasa dan telanjang. Maka, aku panik seperti pertama kalinya aku di sini. Pelan-pelan kucoba supaya bisa berpikir benar. Dimana ada baju untuk bisa kupakai? Dulu ada orang lain di sini. Seorang perempuan besar, perempuan dewasa. Siapa dia? Di mana dia? Apa yang kupikirkan? Apakah mencari baju atau mencari perempuan duluan? Tempat antah berantah ini pelan-pelan jadi berwarna. Warna hijau muncul pertama kali, dominan dan buram. Lebih penting lagi, aku sekarang mendadak mengenakan pakaian serba putih. Kemeja tak bermotif, celana panjang, sepatu pantofel formal, semuanya putih diantara warna latar hijau buram dan dominan. “Kau kenal Nando, kah?” Ada suara menggema. “Idak. Ibu awak melarang main dengan dia.” Balasan suara yang lain. Aku berbalik badan. Kini tempat antah berantah sepenuhnya berubah. Warna hijau tadi sudah menjadi warna macam-macam. Aku kenal tempat ini. Ini ladang cabai yang sering menjadi jalan pintasku untuk ke pintu rimba. Kenapa aku di sini? Siapa itu beramai-ramai? Itu anak perempuan semua? Aku sepertinya agak kenal? Mungkinkah? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku menapak mendekati mereka. Kuharap mereka bisa melihatku. Tapi sayangnya tidak. Percakapan mereka terus saja berlanjut. Dari dekat, keempat gadis kecil itu akhirnya kukenali semua, karena mereka adalah teman sekelasku, termasuk Novia di antaranya. Mereka asik bermain masak-masak di atas batu gadang. Rerumputan, air, dan daun-daun lainnya dicampur jadi satu hingga hancur. Berpura-puralah campuran daun yang mereka hancurkan itu menjadi sajian yang enak. Pertanyaan terus bertambah dalam kepalaku tanpa terpenuhi jawabannya. Kenapa mereka masih kecil sementara aku sudah besar? Kenapa aku sudah kembali di sini? Bukannya tadi aku bersama Novia di dekat pintu rimba? “Kau suka Nando, kan.” Ledek teman-teman Novia. “Indak.” Bantah Novia. “Iyo.” Balas mereka. “Indak!” Novia suka padaku? Pada diriku yang kecil dan tak punya kawan itu? Tapi dia terus menolak kalau dibilang suka padaku, kan. Tunggu, itu hanya obrolan kosong anak kecil. Lupakan saja kalau begitu. “Nando.” Ada suara lain. Aku berpaling ke arah lain. Tiba-tiba muncul sesosok perempuan yang sama dewasanya denganku dari kekosongan udara. Dia berjalan dengan langkahnya yang tegas di atas rerumputan pinggir ladang. Perempuan itu mendatangiku. Dia juga bisa melihatku layaknya aku orang normal. Tapi, lihat itu, pakaiannya berwarna-warna dengan motif yang menarik. Bajunya bagus, celananya bagus. Sepertinya itu model pakaian orang kota, bukan pakaian orang-orang dusun. “Kita pernah ketemu, ya kan?” Katanya. Aku sibuk mencerna informasi yang masuk secara beruntun. Gaya bicara perempuan dewasa ini sangat sopan. Sangat… Dewasa. “Aku udah cari kamu dua tahun ini.” Katanya lagi. “Kenapa bisa…” “Kita sempat pegangan tangan sebelum difoto. Setelah itu kita bangun di puskesmas dekat rumah.” Oh, Tuhan, dia… Niken? Dia betulan Niken? Niken anaknya om berewok? Niken kan tinggalnya di Bogor. Jauh sekali dari sini… Aku menoleh ke belakang, ada Novia kecil dan teman-temannya sedang bermain masak-masak. Aku menoleh kembali ke depan, ada Niken yang sudah sama besarnya denganku, sudah sama-sama dewasa. Padahal harusnya kami berdua juga masih kecil, kan? “Tahun berapa sekarang??!” Aku panik! “Harusnya bukan itu yang kamu tanya.” Balas Niken. “Apa…” “Aku akan ajarin kamu. Fantasi yang terjadi dalam kepala kamu.” Jawab Niken lagi. Niken sudah ada tepat di depan wajahku. Jari telunjuknya seketika menyentil keningku bersamaan saat dia menunjukkan lokasi kami sekarang. Di kepalaku, begitu? Niken dewasa lantas menyentuh badanku dengan badannya. Sebuah dekapan erat seorang lawan jenis sedang menimpa diriku. Bukan Mak Etek yang memelukku, dan bukan siapa-siapa juga dalam anggota keluarga bapak. Astaga.
Niken
BERSAMBUNG