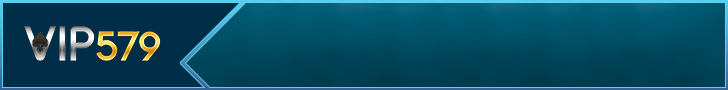My Name Elang ::
Lumayan ceritanya gan!
Sambil menunggu updetenya para maestro clotingk dgn juwita hatinya dan maestro ethar dgn tepian hatinya..Hehe ditunggu updetenya suhu Caiyo!!
PART 1
Namaku Elang. Usiaku saat ini
awal tiga puluh. Bekerja di
salah satu stasiun televisi
swasta di Jakarta. Aku punya
pengalaman yang ingin
kuceritakan dan persembahkan kepada pengunjung setia
cerita dewasa. Pagi itu awal Mei, pukul 7:00,
aku mendapat telepon yang
tak kuduga-duga di kantor.
(Memang aku biasa datang
pagi untuk menghindari macet).
“Hallo, siapa nih?” “Hai, lupa sama aku ya?”
“Iya, siapa ya?”
“Coba tebak. Masih ingat Ilen?”
“Ilen?”
“Iya. Yang tinggal di Wastu
Kencana, Bandung.” “Oh, yang anak Inggris?”
“He eh. Tapi kamu bukan dia.
Karena aku kemarin ketemu
dia di Bandung.”
“Makanya. Tebak siapa aku.
Ilen is the clue. Aku sobat baiknya. Anak Inggris juga.”
Aku mencoba mengingat-ingat
suaranya. Tapi tetap saja
tidak ingat. Iyalah, mana aku
ingat anak-anak angkatan 91.
Lain jurusan lagi. “Sombong. Lupa ya sama aku?”
“Aku nyerah deh.”
“Ini Srida.”
Srida. Emh, aku ingat dia.
“Hai! Dimana kamu sekarang.”
“Di kantor. Aku kerja di Jakarta sekarang.”
“Dimana?”
Dia menyebutkan nama sebuah
bank asing dari Amerika yang
sangat terkenal.
“Hebat kamu. Boleh dong aku ambil kredit? Di bagian apa
kamu?”
“Cuma di bagian Telemarketing.
Tapi lumayan deh.”
“Dapat teleponku dari Ilen ya?”
“He eh. Tiap pagi kutelepon dia. Dari kantor.”
“Enak banget. Di kantorku,
telepon lokal saja dibatasi.”
“Iya. Di sini sih mau interlokal
berjam-jam juga boleh. Khan
bagian tele, apalagi aku dateng pagi banget. Maklum,
numpang kakak.”
“Sama. Emh, senang sekali
dapat telepon dari kamu.”
“Lang, tidak nyangka kamu
ada di sini juga. Kemarin- kemarin sih aku ada lihat kamu
di TV. Hebat kamu.”
“Biasa saja. Lagian kenapa
baru sekarang telepon?”
“Barusan aku dapet dari Ilen.”
“Sering balik ke Bandung?” “Tiap minggu. Jumat pulang,
Minggu atau Senin pagi kembali
ke Jakarta.”
“Gila. Nggak capek?
“Abisnya bosen. Tidak punya
teman sih.” “Sekarang khan ada aku.”
“Iya deh.” Kami pun berbincang di telepon
sampai pukul 8.00. Saat dia
harus benar-benar bekerja.
Sedang jam kerja kantorku
pukul 8:30. Kami bicara banyak.
Soal pengalaman masa kuliah dulu. Kenanganku muncul
setelah telepon ditutupnya. Srida. Gadis itu teman kuliahku
di Fakultas Sastra. Hanya kami
beda jurusan. Aku di Perancis,
sedang dia di Inggris. Terus
terang dulu aku naksir dia.
Anaknya manis, pendiam, berkulit putih. Dengan berat
dan tinggi badan proporsional.
Wajahnya mirip Shinta Bella
dimixed dengan Cornelia
Agatha. Pokoknya oke banget.
Dia sejurusan dengan Ilen, teman baikku waktu Opspek
dan telah kuanggap sebagai
adikku sendiri. Dulu aku pernah
minta tolong pada Ilen untuk
membantuku mendekatinya.
Tapi aku hanya diberikan telepon dan alamat Srida saja.
(Nantinya aku tahu kalau Ilen
itu menaruh harapan
kepadaku. Pantas Ilen ‘dulu’
kayaknya menggodaku setiap
kali main ke kostku). Dulu aku pernah menelepon Srida
beberapa kali. Biasa, merayu.
Tapi dia tidak bergeming.
(Nantinya aku juga tahu kalau
dia mengira aku tidak serius,
dan menyangka aku playboy tengil. Padahal suwer; dia
benar! Hahaha!). Ya sudah
akhirnya kami nggak jadian.
Aku tetap sebagai playboy, dia
setahuku pacaran dengan
anak angkatan 90. Sebenarnya aku waktu kuliah
di Sastra itu sudah kerja di
perusahaan familiku, asli
karena kebisaanku, bukan KKN
dan juga kuliah di D3 Tehnik
Informatika swasta. Iseng dan penasaran saja untuk kuliah di
dua tempat. Apalagi di Sastra
khan rata-rata banyak
ceweknya. Jadi ya itu, playboy
kampung ini makin betah saja.
Di kampus, aku cukup populer dengan panggilan Abang. Iyalah,
aku tua-an, sudah kerja, dan
berasal dari Kalimantan. Karena
sudah kerja, sudah punya
cukup uang. Makin banyak saja
cewek-cewek yang lengket denganku. Credit card can buy
everything, man. Utamanya
pada tahun awal 90-an. So,
aku bisa dengan mudah pilih-
pilih cewek. Dan lagi tampangku
tidak malu-maluin deh buat digandeng. Tidak sombong,
korbanku sudah banyak! Aku
jahat ya. Tapi akhirnya
kutakluk juga dengan seorang
gadis, adik tingkatku. Yang
akhirnya menjadi istriku tercinta. Aku ngelantur ya? Bosen?
tidak apa-apa. Aku bingung
juga buat cerita. Aku bukan
pengarang sih. Aku cuma
mencoba menceritakan ulang
pengalamanku. Aku lanjutkan ya.
Sejak pagi itu. Srida
menelponku paling tidak tiga
kali sehari. Pagi-pagi seperti
tadi, siang saat makan siang.
Dan sore sebelum pulang kantornya. Rata-rata tiap kali
menelepon satu jam sampai
satu setengah jam. Gila ya?
teman-teman kantorku juga
bingung. Kenapa aku jadi males
makan keluar pada jam istirahat. Aku pasti hanya nitip,
atau pesen delivery saja.
Mereka mulai curiga. Apalagi
atasanku, perawan(?) tua
yang ceriwis dan nyinyir.
Beberapa bahkan langsung menebak aku selingkuh. Ooops,
lupa ceritain kalau aku itu
sebenarnya sudah tunangan
dengan Venus.
manja Srida di telepon.
Sungguh. Dia sudah berubah.
Bukan Srida yang dulu selalu
ogah-ogahan menerima
telepon. Yang tertutup dan pendiam. Dia total berubah. Dia
bahkan memanggilku sayang.
Dan tak malu-malu menyambut
rayuan dan gurauanku. Bahkan
yang agak-agak miring. Kadang
aku berpikir ini semua karena kisah lama yang terulang. Rasa
cinta yang mendadak datang
kembali. Gila, kenapa dia muncul
sekarang. Saat tanggal
pernikahanku sudah
ditetapkan. Sering juga aku merasa ini hanya perasaan
senang, mendapat kembali
kawan lama. Bosen? tidak apa-apa kalau
pembaca bosen, silakan lewati
saja cerita ini. Lucunya, sampai
berhari-hari kita telepon-
teleponan saja. Aku sibuk, dia
tidak bisa keluar kantor. Padahal jarak kantorku
dengan Kuningan (kantor
Srida) tidaklah bisa dikatakan
jauh. Paling setengah jam pakai
mobil. Srida selalu mengajak
bertemu. Tapi karena rasa cintaku pada Venus
(tunanganku) aku selalu
menolak. Srida belum
kuceritakan kalau aku sudah
bertunangan November 1997
lalu. Teleponnya, selain ke kantor juga sekali-sekali ke
rumah atau ke HP-ku. Tapi tak
pernah lama. Paling hanya
menyampaikan kesepiannya di
Jakarta yang tanpa teman itu. Saat kerusuhan 14 Mei, aku
terpaksa menginap di kantor.
Srida beberapa kali
menelponku, mengatakan dia
akan pulang cepat. Dan kalau
bisa akan pulang ke Bandung. Srida akan kembali hari Senin,
sebab kantornya memutuskan
untuk meliburkan
karyawannya. Senin tanggal 18 Mei sore aku
mendapat telepon dari Srida.
Dia mengatakan sedang berada
di RS Harapan Bunda. Ternyata
keponakannya diopname
karena menderita kelainan pada jantungnya. Dia
memintaku untuk
menjumpainya di sana. Mulanya aku tidak mau, sebab
setelah beberapa hari tidak
mendapat teleponnya,
walaupun ada rindu, aku sadar
kembali bahwa aku telah
punya tunangan dan akan menikah dalam beberapa bulan.
Namun akhirnya rayuannya
dan rasa penasaranku
membuat luluh tekadku.
Sepulang kantor, aku pun
menuju ke RSHB. Sempat celingukan karena sedikit lupa
akan rupa dan sosoknya.
Kucoba hubungi HP-nya sedang
dipakai. Akhirnya aku melihat
seorang gadis sedang duduk di
ruang tunggu apotik. Ah itu dia. Gadis itu pun melihatku.
Tersenyum manis. Aduuh,
cantiknya. Benar, wajahnya
tambah manis, body-nya lebih
kurus dari yang kuingat,
namun sangat montok. Tak puas-puas kupandangi dia.
“Elang!” Dia memanggilku.
“Hai!” Hanya itu yang sanggup
kukatakan.
Dengan segera dia berdiri
menyongsongku. Menyalamiku dan menyodorkan pipinya. Ah,
aku cukup kaget. Perasaan
dulu dia nggak begini. Mungkin
karena dia merasa telah akrab
kepadaku melalui telepon-
telepon kami. Kupandangi dia lekat-lekat. Tubuhnya hanya
dibaluti kaos tipis merk
Playboy berwarna putih,
sedang bawahannya dia
memakai rok pendek yang
menampakkan kakinya yang bagus dan panjang mulus itu.
Aku dapat melihat sekilas bra
hitam yang dipakainya,
menonjolkan sepasang buah
dada yang menantang, ranum. “Lama ya, nungguin aku?”
“Nggak juga. Kamu tidak
berubah banyak, Lang. Hanya
tampak lebih matang.”
“Kamu yang berubah.”
“Apanya?” “Semuanya. Lebih, apa ya?”
aku sempat terdiam,
“Menggiurkan.” Dia hanya
tersenyum. Dia mengajakku duduk,
kemudian mulai bercerita soal
keponakannya yang masih
balita itu. Aku mendengarkan
sambil sesekali menatap erat
wajahnya. Dalam hati, aku harus mengakui kalau dia
tambah cantik. Sungguh!
Rambutnya yang ikal dipotong
sebahu. Modern style.
Tampaknya dia sadar kalau
kupandangi. “Hei!” sentaknya.
“Apaan?” Tanyaku.
“Matamu itu.”
“Salah sendiri. Kenapa kamu
tambah cantik.”
“Sudah merayunya. Biasanya cowok kalau habis merayu lalu
minta yang nggak-nggak.”
“Tapi kalau aku yang minta
diberi khan?”
“Mintanya apaan dulu.”
“Disun.” Dia mencubitku.
“Macem-macem saja. Entar
pacarmu marah. Siapa tuh, si
kaca mata itu?”
Aku cuma diam, lalu sadar, dia
mesti tahu tentang Venus. “Venus? baik.”
“Nah itu. Mending kita telepon
Ilen sekarang.”
“Yuk!” Kugaet tangannya. Sambil berjalan tanganku
beralih, memeluk pinggangnya
yang ramping. Dia tak menolak.
Tanganku tetap di sana,
bahkan saat menelepon Ilen
dari telepon kartu. Iyalah, kalau pakai HP bisa berapa?
Interlokal khan kalau ke
Bandung. Itu saja ngabisin
kartu teleponnya sekitar 40
pulsa dan punyaku yang masih
230-an. Masalahnya, Ilen itu bawel banget orangnya.
di kantin RS. Aku sebelumnya
mengajak Srida ke caf atau
restoran, tapi dia menolak.
Lain waktu saja, katanya. Kami
bicara banyak. Tentang jalan hidup yang kami tempuh.
Tentang masa lalu. Terkadang
jemarinya kugenggam,
kuremas. Dia tak sekalipun
menghindar. Tentu saja aku
tak cerita kalau aku sudah tunangan. Setelah malam itu,
kami sering jalan berdua.
Terkadang aku menemaninya di
RS. Untungnya tunanganku
begitu percaya kepadaku, dan
memang tidak terbiasa menelponku kalau tidak
penting-penting benar. Kami saling berbagi hadiah. Dia
memberiku bermacam barang
yang berbau Coca Cola, karena
dia tahu aku maniak dengan
merchandiser dari perusahaan
minuman tersebut. Ada-ada saja surprise darinya. Aku
bahagia bersamanya. Aku pun
demikian tidak lupa akan
maniaknya dia dengan tokoh
Tazmania dari Warner Bros. Tapi hubungan kami hanya
sebatas makan, jalan, nonton,
berpegangan tangan, peluk
pinggang, dan cium pipi saja.
Bosenin kali ya? Tapi ya, aku
cukup senang. Sampai akhirnya di bulan Juni.
Aku ingat benar tanggalnya,
tanggal 13. Saat itu aku di
Bandung, dalam rangka
memperingati setahun
wafatnya ayah Venus, tunanganku. Juga ada tugas
kantor. Srida sudah ada di
Bandung sejak kemarin (aku
yang mengantarnya ke
Gambir). Dia tahu aku akan ke
Bandung. Di tengah acara peringatan, HP-ku berbunyi.
Dari layar, kutahu dia yang
menelponku.
“Hai. Ntar aku telepon. Aku
sedang di acara temanku nih”,
kataku pelan. “Nggak usah. Gini saja.
Kutunggu di Dago. Anak-anak
bikin warung tenda.
“Namanya.. (kurahasiakan). Aku
tunggu.”
“Oke.” Telepon pun kututup. Venus melihatku, bertanya,
mungkin curiga. Kujawab saja
anak-anak angkatanku
mengajak reuni. Venus percaya
saja. Dan memang dia tidak
pernah mau mencampuri urusanku dengan teman-
temanku waktu kuliah dulu.
Makanya setelah acara
keluarga selesai, aku segera
ke Dago pakai taksi. Tidaklah
sulit mendapatkan warung tenda yang dimaksud. Di sana
sudah ada Ilen dan anak-anak
Inggris lainnya. Setelah sekitar
dua jam di sana, Ilen minta
diantar pulang. Aku dan Srida
yang mengantar. Di rumah Ilen, Ilen menggoda kami habis-
habisan (sesekali dia
menyinggung soal Venus). Aku
dan Srida hanya bisa seperti
anak SMA, tersipu malu.
Segera saja kuajak Srida pulang. Dan gilanya, Srida
mengatakan ingin jalan kaki
menuju rumahnya. Aku mengira
dia bercanda. Gila! Jarak
Wastukencana (rumah Ilen)
dengan Gatot Subroto (rumahnya) khan lumayan jauh.
(Tanya deh sama yang
mengerti Bandung). Tidak tahu
berapa km, pokoknya jauh
deh. Tapi Srida meyakinkanku,
katanya dia ingin menikmati malam ini bersamaku. Banyak
pula hal yang ingin
dibicarakannya. Ya sudah,
kujabanin saja. Emang banyak
yang diceritakannya. Masa
lalunya, kisah cintanya, rahasianya, keluarganya.
Sementara aku hanya
mendengar dan sesekali
menanggapi pertanyaannya.
Aku juga berbohong padanya
(soal Venus, apalagi). [Info saja nih; waktu aku mulai
jalan dengan Venus, aku tidak
pernah berlaku ‘curang’,
sebelumnya aku layaknya
buaya yang tidak pernah
menolak bangkai. Teman-teman Venus sendiri pun protes saat
tahu Venus jalan denganku
(some of them was my victims,
honestly), tapi Venus tak
terpengaruh. Mungkin karena
itu aku bisa awet dengannya dan tidak ‘obral’ lagi. But,
dengan Srida ini aku tidak
tahulah. Why?]. Semakin dekat rumahnya, kami
berjalan semakin pelan. Satu
setengah jam ada mungkin,
kami berjalan-jalan. Karena
Swatch di tanganku sudah
menunjuk angka setengah satu pagi. Selain pelan pun, kami
semakin rapat. Dapat kucium
lembut parfum yang
dipakainya, yang keluar dari
tubuh yang terbalut stelan
hitam-hitam dan jaket Levi’s- ku. Tubuhnya lembut dan
hangat dalam rangkulanku.
Tapi ya, sekali lagi, hanya
sebatas rangkulan. Bosen, ya?
Biarin. Lima ratus meter dari
kompleks rumahnya, dia mengusulkan untuk menunggu
taksi. Aku pun mengiyakan.
Dari pada entar sendirian,
mending sekarang. Taksi
segera didapat. Kami pun naik.
Sudah hampir masuk ke kompleksnya. Kami
berpandangan. Entah
bagaimana bibir kami sudah
saling mendekat, sebelum
akhirnya bersentuhan. Lembuut sekali. Dan aku yakin
mata si sopir meloncat keluar
melihat kami dari spion. Kami
tak peduli. Terus kukulum bibir
ranumnya. Dan sungguh, aku
telah sekian lama merindukan bibir madu ini. Perlahan tapi
pasti mulailah lidah kami
bermain, saling memilin. Damn! It
was the best kiss I ever had! “Pak. Rumahnya yang mana?”
Dengan malu-malu, Pak supir
tua itu bertanya. Ooops! Kami
berdua tersentak. Lalu saling
pandang. Tersenyum. Malu-
malu. “Gimana Srida?” Tanyaku.
“Terserah kamu.” Jawabnya
dengan suara serak.
“Emh, jalan terus saja Pak”,
kataku.
“Terserah Bapak kemana, keliling Bandung juga boleh. Oh,
putar-putar deh.”
Si sopir itu pun manut.
Aku memegang tangan Srida.
Dia memandangku, kemudian
menunduk. Kupegang dagunya yang indah. Kusodorkan
wajahku. Perlahan dia
mendorongku menjauh.
Mukanya mengarah ke sopir
itu.
“Biarin.” Bisikku. Lalu ciumanku pun kulanjutkan.
Srida pasrah. Sopir itu pun
tahu diri, tidak plirak-plirik lagi.
Kami berciuman dengan penuh
perasaan [swear!]. Menikmati
setiap helaan nafas dan kehangatan yang menjalar di
sekujur tubuh kami. Kurengkuh
dia dalam pelukan. Perlahan
kurasakan kejantananku mulai
bereaksi. Terasa hangat sekali
di bawah perutku. Tanganku pun sudah beroperasi di
punggung Srida. Perlahan
turun, sampai di bokong yang
indah dan hangat. Kuremas
perlahan sepasang bongkahan
itu silih berganti. Srida mengerang perlahan. Tubuhnya
yang indah meregang. Bibirku
pun tidak lagi hanya sekedar
menikmati tiap lekuk bibirnya,
tapi telah berpindah, ke pipi,
pelipis dan keningnya. Kemudian kembali ke bibirnya. Kurasakan
tangannya meraba-raba
punggungku, dan kemudian ke
arah bokongku. Aku menekan
tubuhnya dengan tubuhku.
Bibirku turun ke dagunya, menggigit lembut. Srida
merintih. Perlahan bibirku
turun ke lehernya, sedang
tanganku beralih ke dadanya.
Meraba, meremas, dan memilin
dari balik bajunya. Bajunya yang dari bahan satin
menambah sensual bentuk
payudara Srida. Bibirku terus
menciumi leher gadis itu.
Lidahku menjilati
kejenjangannya. Seperti musafir yang kehausan.
Kuhisap, kujilati, kutelusuri
lehernya. Srida tambah tak
teratur gerakannya. Jemarinya
menarik rambutku, nyaris
menjambaknya. Aku yakin dia sudah benar-benar
terangsang. Tanganku pun
turun, membelai perutnya yang
datar. Bermain-main sejenak di
situ. Lalu dengan pasti
menyentuh kehangatan di antara kedua pangkal
pahanya. Sebentuk daging
lembut yang ditutupi celana
dari bahan sandwash itu
memancarkan hangatnya. Srida
melenguh perlahan. Oh, aku sungguh menikmati erangannya
itu. Lalu tangan kananku menuju
bagian belakang tubuhnya. Dari
sela-sela celananya tanganku
masuk, meraih. Pertama-tama
kurasakan pinggiran celana
dalamnya yang berenda. Kejantananku seolah berontak.
Sesaat kemudian jemariku
telah berada di dalam panty
Srida. Oooh, lembutnya tubuh
gadis ini. Bentuknya bagus
sekali. Terasa lembut menyentuh tanganku yang
kasar. Srida mengerang, kali ini
dia menggigit leherku untuk
menekan suaranya. Kuremas-
remas daging lembut itu.
“Oh, Elang. Aku cinta padamu.” Tubuhnya meregang kembali,
seperti kucing selepas tidur.
Aku sudah tidak sabar.
Tanganku kutarik keluar.
Meraba-raba hingga ke
dadanya. Perlahan membuka dua kancing atas baju Srida.
Nafas gadis itu terengah-
engah, seolah meronta, ketika
ujung jari-jariku menyentuh
tepi bra yang dikenakannya.
Nafasku pun sudah tak beraturan. Secara naluriah,
tanganku pun mencoba meraih
payudara kanannya, terasa
nikmat dan hangat ketika jari
tengahku menyentuh puting
susunya. Oh, sempurnanya tubuh ini. Saat bibirku perlahan
turun ke arah payudaranya,
tiba-tiba kedua tangan Srida
mendorongku. Lalu meraih
bajunya yang telah kusut
masai. “Berhenti, Lang.” Parau sekali
suaranya, “Jangan. Tidak di
sini.”
Aku pun tersadar. Astaga.
Benar-benar naluri. Perlahan
Srida mengancing kembali hemnya. Aku pun mengusap
bibirku, menghilangkan goresan
merah dari situ. Masih
kurasakan manis bibir dan
lipstiknya di situ. Aku
tersenyum, Srida juga. “Maaf. Aku terbawa perasaan”,
bisikku.
“He eh”, angguknya.
Lalu kami baru ingat kembali.
‘Ya ampun kami di dalam taksi’.
“Dimana kita, Pak?” Tanyaku ke sopir.
“Di Braga, Pak”, jawabnya,
kentara sekali malu-malu.
“Kita kembali ke tempat tadi
Pak.” Kulirik argo taksi GR itu
sudah 14 ribu. Gila. Berapa lama ya Pak Tua ini dapat
tontonan gratis. Aku agak
menyesal juga.
“Baik Pak.” Lalu Pak Tua itu pun
mengantar kami ke kompleks
perumahan Srida. Atas
permintaan Srida, kami hanya
mengantarnya di depan
kompleks (ngertilah, Srida tidak mau sopir itu tahu
rumahnya). Lalu aku pun
pulang ke hotel Horison. Bersambung . . . . .
Besoknya, pagi-pagi sekali
Srida telepon ke HP-ku. Tanpa
‘say hello’ dan sejenisnya, dia
hanya berkata; “Gila kamu,
Lang. Aku orgasme dua kali.”
Telepon ditutup sebelum aku menjawab. Aku hanya
tersenyum puas, lalu kembali
terlelap. Pukul sebelas siang aku dan
Venus sedang di Gani Arta,
sebuah pabrik yang banyak
menjual bahan brokat untuk
kebaya. Untuk pakaian
seragam sanak famili di pernikahan kami nanti. Sedang
asyik-asyiknya Venus memilih
bahan, HP-ku yang dititipkan
kepadanya berbunyi. Dia
mengangkatnya. “Hallo.. Elang? Sebentar ya.
Maaf, dari siapa ini? Srida.
Sebentar.”
Venus memberikan telepon
kepadaku. Dengan segera aku
meraihnya, dan berbicara kepada Srida. “Hi. How are
you?”
“Baik. Tadi itu Venus ya?” Srida
bertanya, agak kaku.
“Bukan.” Berbohong.
“Dimana kamu?” “Sedang menuju ke Jakarta,
numpang sama Mas Bambang.”
“Oh.”
“Kamu dimana?”
“Di Ujung Berung.”
“Ngapain?” “Jalan-jalan saja.” Bohong lagi.
“Gila. Masa aku sudah kangen
sama kamu.”
“Sama.”
“Ntar ketemu ya di Jakarta.”
“He eh.” Telepon pun ditutup. Aku baru
sadar sorot mata curiga dari
Venus. “Siapa?”
“Teman. Yang kemarin ketemu
waktu reuni.”
“Namanya?” “Tadi bilangnya siapa?”
“Sri apa gitu.”
“Srida.” Aku tidak dapat
berbohong lagi.
“Perasaan tidak ada anak
jurusan kita dulu yang bernama Srida.”
“Anak Inggris. Temennya Ilen”,
kataku.
Venus kenal Ilen dan pernah
kuajak ke rumahnya.
“Oh..” Venus tampaknya ingat sesuatu.
“Bukannya dia cewek yang
dulu kamu taksir?”
“Iya.”
“Ngapain dia telepon kamu?”
Curiga hadir lagi di tatapan Venus.
“Iseng saja. Dia ternyata kerja
di Jakarta juga. Kemarin
kebetulan ketemu. Emh, jangan
curiga gitu dong.” Kurengkuh
Venus dalam pelukan. “Siapa yang curiga? Tapi awas
saja ya macem-macem.”
“Ngancem nih?” Ledekku.
“Iya.”
“Don’t worry, she got a
boyfriend.” Lalu sambil mengecup pipinya, aku berbisik,
“Aku cuma cinta kamu, Venus-
ku.”
Venus pun ‘normal’ lagi. Sorenya setelah mengantar
Venus ke stasiun KA (dia mesti
kerja besok, di sebuah hotel
yang sangat terkenal di
Jakarta. Sedang aku masih
dinas di Bandung). Saat itu khan sedang Piala Dunia. TV-ku
khan mengadakan siaran
langsung, caf to caf di hotel
Horison, aku berencana ke
rumah Ilen. Dengan Nokia 6110,
kuhubungi dia. “Hai. Aku ke sana, ya.”
“Abang? Kirain sudah tidak
mau ke sini. Mentang-
mentang.”
“Apaan? Aku ke sana ya.”
“Gimana Srida?” “Cuma teman kok.”
“Venus?”
“Barusan aku nganterin dia
pulang. Aku belum, masih ada
acara di sini. Piala dunia di
Horison.” “Boleh dong ikutan. Nginep di
sana?”
“Iya.”
Sesampai di rumah Ilen, cewek
mungil tapi berdada cukup
besar itu langsung memelukku erat dan menarikku ke sudut
ruang tamunya.
“Hai. Tadi aku ditelepon Srida.
Gila, sekarang dia jatuh cinta
sama kamu, Bro.”
“Cerita apa dia?” “Nggak. Dia cuma tanya-tanya
soal kamu.”
“Kamu cerita apa saja?”
“Aku bilang kamu sudah
tunangan November kemarin.”
“Apaa?” Nyaris tersedak aku. “Lhoo? Ada yang salah?”
“Ileen. Ember kamu ya?”
“Gimana sih? Abang khan benar
sudah tunangan dengan Venus.
Ditanya tadi katanya cuma
teman. Si Srida pun demikian. Katanya teman.”
“Lalu. Ah! Kamu tidak tahu
masalahnya.”
“Apaan sih? Bingung aku.” Ilen
terdiam sejenak,
“Oooh. Abang, Abang. Jangan main api.”
“Lalu, apa kata Srida. Waktu
kamu bilang aku sudah
tunangan?”
“Tidak ada. Tapi aku bilang
sama dia kamu mau ke sini. Dia bilang entar saja dia telepon
lagi.”
“Mati aku.”
“Emangnya ada apa sih?” Maka aku pun bercerita pada
Ilen. Kejadian yang terjadi
sejak pulang dari rumahnya
kemarin. Memang, aku terbiasa
berterus terang pada Ilen.
Sejak kuliah dulu kami sering berbagi kisah dan isi hati. Ilen
memandangku tidak percaya.
Terkadang dia tertawa,
terkadang tersenyum.
Terkadang dia mencubitku,
terkadang cekikikan. Terkadang pun menelan
ludahnya.
“Gila kamu, Bang!” komentarnya
setelah ceritaku selesai.
“Yah, mau dibilang apa?”
“Jadi benar? Dia sampai orgasme dua kali?”
“Katanya sih.”
“Gila. Gila. Gila.” Ilen menggeleng
kepalanya, kembali menelan
ludah.
Kusadari suaranya berubah agak serak.
“Kamu terpengaruh, Len?” Aku
tersenyum mesum.
“Mau nyobain?”
Dan cubitannya yang
menyakitkan pun hinggap di lenganku.
Telepon dari ruang
keluarganya berbunyi. Ilen
segera ke sana, karena tidak
ada orang di rumahnya.
Tak lama kemudian dia sudah ada di sampingku, sambil
tersenyum-senyum. “Srida?”
Tebakku.
“He eh.”
“Apa katanya?”
“Waktu kubilang kamu ada di sini. Dia cuma bilang katakan
kepada Elang, jangan macem-
macem sama aku. Dia marah
Bang. Dan, kedengaran
suaranya serak. Mungkin dia
menangis.” “Wah gawat, Len.”
“Iya. Dia bilang juga kalau kamu
jangan lagi menghubungi dia.”
“Kenapa tadi tidak kau panggil
aku?”
“Srida melarangku.” Aku segera menghubungi
nomor teleponnya lewat
handphone. Terdengar tanda
telepon telah tersambung,
namun segera saja busy tone.
Tampaknya Srida melihat dari CLI kalau aku yang menelepon,
dia tidak mau menyambutnya.
Ilen memandangku dengan
pandangan menyesal.
“Sudahlah. Nanti saja aku
telepon lagi.” Teleponku berbunyi. Aku
mengharapkan itu Srida. Tapi
bukan, dari Didot, sobatku
yang jaga di Horison. Dia
memintaku untuk segera
kembali ke hotel. Ada yang harus dicek ulang untuk acara
live Piala Dunia itu.
“Len. Aku harus ke Horison.
Jadi mau ikut?”
“Boleh. Tapi rumah nggak ada
orang nih?”
Pas saat itu, bel pintu
berbunyi. Ilen membukakan
pintu. Ternyata kakak dan
iparnya yang datang. Maka Ilen
pun bisa pergi denganku.
Karena aku lumayan akrab dengan keluarga Ilen, Ilen
diijinkan untuk menginap di
Horison. Tahu sendiri, piala
dunia khan siarannya malam.
Dengan segera Ilen
mempersiapkan dirinya. Saat hendak mandi, kularang dia.
Nanti saja di hotel. Dalam perjalanan dengan taksi
ke hotel Ilen dan aku banyak
diam. Sesekali dia tampak
tersenyum, kalau kutanya dia
hanya bilang ingat soalku dan
Srida di dalam taksi. Beberapa kali juga kucoba hubungi Srida
di telepon. Kali ini teleponnya
dimatikan. Hanya ada voice mail
saja. Aku ogah kalau harus
ngomong dengan mesin. Di hotel, kukenalkan Didot
dengan Ilen. Kusarankan Didot
untuk pindah ke kamarku,
sedang Ilen menggunakan
kamarnya. Didot protes,
dengan berbisik dia bilang dia ada kenal cewek LPK Ariyanti
(lumayan terkenal dengan
perkinya). Ya sudah, aku
akhirnya mengajak Ilen untuk
memesan kamar lagi. Tapi Ilen
bilang tidak perlu, dia biar sekamar denganku. Aku
memandangnya sejenak,
meyakinkannya. Dia cuma
mengangguk, dan bilang, “Aku
percaya kamu, Lang.” Didot
mengedipkan matanya kepadaku. Dasar otak ngeres.
Dia emang gila sih, pacarnya
bejibun, padahal anaknya
sudah SMA. Bahkan ada
pacarnya yang lebih muda dari
anaknya di Jakarta sana. Itulah gawatnya kalau suami
istri pisah kota. Istri Kang
Didot ini kerja di Telkom
Bandung. Ngelantur ya? Aku
lanjutkan. Sore sampai malam, kami
hanya duduk-duduk berempat.
Gaetan Didot sudah ada di situ.
Lumayan cakep dan seksi.
Namanya Sarita. Rupanya si
Didot mengiming-imingi gadis ini dengan janji akan
mengenalkannya pada Raam
Punjabi. Aku hanya tertawa
dalam hati. Lagu lama
karyawan stasiun TV, ya itu.
Boro-boro kenalin dengan bos Multivion itu, akhir-akhirnya
di’jual’ ke seorang manajer di
kantorku yang botak dan
bejat (halo ED! Masih belagak
seks maniac?). Malam setelah acara ‘live’
selesai dan beres
mengemaskan barang-barang
yang mesti dibawa pulang ke
Jakarta, kami kembali ke
kamar masing-masing. Si Didot menawarkan viagra kepadaku.
(Waktu itu belum banyak yang
jual di Indonesia. Dia dapat dari
seorang boss besar suatu
perusahaan terkenal di
Indonesia yang orangnya suka nyanyi. Didot is (kalau malem)
one of his bodyguard). Aku
cuma bilang, sinting. Ilen ini
adikku. Si Didot cuma nyengir-
nyengir saja sambil pesan
kalau terdengar erangan dan teriakan dari sebelah kamarku,
mohon dimaklumi saja. Dan
benar. Tidak sampai sepuluh
menit di dalam kamar, Ilen dan
aku sudah mendengar
gedubrak-gedubruk dari kamar sebelah. Dinding kamarnya tipis
amat hotel ini. Ilen hanya
memandangku, membelalakan
matanya, dan tersenyum
kepadaku.
“Hush! Anak kecil.” Aku mendelik.
Seperti sudah kuceritakan
tentang Ilen ini, anaknya
memang mungil. Tingginya
paling-paling 155 cm, kulitnya
kuning langsat khas Sunda. Wajahnya manis. Enno Lerian
kalau gede mirip dia deh. Tidak
ada yang istimewa, kecuali
dadanya yang ‘ruar biasa’!
“Enak saja anak kecil.”
“Emang sudah gede?” “Sudah dong! Nggak lihat nih?”
Dia menunjuk tubuhnya yang
bersalut kaos Esprit hitam,
tepat ke arah dadanya.
“Lihat, lihat. Tapi khan itu bisa
dibuat-buat. Jangan-jangan spons kamu sumpalin di situ.”
“Kurang asem.”
Sementara itu dari kamar
sebelah terdengar gerungnya
Didot dan erangan Sarita. Gila!
“Tambah seru tuh, Bang.” Cekikikan Ilen terdengar.
“Sudah jangan didengerin.
Entar..”
“Apa? Kepengin?”
“Ileen. Bocor ya? Sana mandi.
Cuci kepalamu biar dingin.” “Iya deh. Aku mandi dulu.”
Emang kemeriahan di
pertandingan tadi bikin
keringat lengket ke badan. Ilen
ke kamar mandi. Sementara
aku menghempaskan tubuh ke spring bed. Ada dua tempat
tidur di situ. Aku mengambil
yang kanan. Lalu kuraih HP-ku.
Mencoba menghubungi Srida.
Kali ini ada jawaban.
“Hallo.” “Heeh.” Jawaban dari sana
ogah-ogahan. Suaranya serak.
Mungkin sisa tangis. “Srida.
Kenapa teleponnya tidak aktif
terus?”
“Aku tidur.” “Emh. Kamu marah ya?”
“Tidak. Apa hakku buat
marah?”
“Aku mau jujur deh. Tapi tidak
bisa ditelepon. Bagaimana kalau
Selasa sore kamu jemput aku di Gambir?”
“Nggak deh. Aku tidak mau
ketemu kamu.”
mangkel, marah. Kucoba
telepon lagi, tapi setiap masuk
terdengar busy tone. Srida
benar-benar tak ingin
dihubungi. Mangkelku menjadi- jadi. Di ruang sebelah masih
terdengar lenguhan dan
jeritan, juga bunyi ranjang
yang memukul-mukul dinding.
Didot memang ‘gelo’. Tapi aku
tidak tertarik untuk menikmati suara-suara aneh di sebelah.
Biarin saja dia bertempur.
Perlahan-lahan mataku
terpejam. Sesaat kemudian aku
merasa telah tertidur. Entah
karena capek fisik atau lelah pikiran. Sebuah sentuhan
ringan membangunkan lelapku. “Bang. Bang. Kok malah tidur?
Nggak mandi dulu?” Ilen
membangunkanku. Tubuhnya
terbalut bathrobe yang
kegedean. Seger banget
kelihatannya. “Eh. Aku ketiduran.” Melirik
jamku, sudah tiga puluh menit
berlalu.
“Mandi sana. Kok wajahmu
suntuk gitu?”
“Nggak. Cuma tadi aku telepon Srida, dia benar-benar
memutuskan hubungan kami.”
“Sudah. Sekarang gantian,
mandi! Guyur kepala dengan air
dingin. Hilangkan cerita Srida
dari otakmu.” Ilen melemparkan handuknya
kepadaku. Lalu gadis itu
menuju meja rias. Duduk di
kursi kecil di depannya.
Menatap kaca. Ada sesuatu
yang lain yang kutangkap di wajah yang terpantul di sana.
Ilen menyilangkan kakinya,
selintas terlihat pahanya yang
putih mulus. Otakku menjadi
tegang. Selirikan kutahu dia
sempat menangkap pandanganku. Tapi dia tidak
bereaksi. Aku segera berdiri
dari tempat tidur.
Menyilangkan handuk ke
pinggangku, sambil melepaskan
501 yang kupakai. Setelah itu kubuka kemeja dengan
lambang stasiun TV-ku.
Terpampang jelaslah dadaku
yang bidang dengan bulu-bulu
di sana, dan pahaku yang
kekar dan penuh bulu pula. Bulu-bulu hitam itu tambah
kontras dengan kulitku yang
bisa dikatakan putih
kecoklatan. Saat melangkah ke
kamar mandi, kusadari tatapan
mata Ilen. Menelan ludah. “Kagum Len?” Godaku.
Dia hanya memonyongkan
bibirnya. Matanya menyipit.
Dengan gerak seperti kilat
kusambar bibirnya dengan
bibirku. “Gotcha!” Teriakku setelah
menarik kepalaku. dia
menyumpah-nyumpah.
“Sinting!”
Aku berlari ke kamar mandi.
Saat aku gosok gigi ada bau samar di sekitar wastafel. Bau
yang khas. Apa ya? Tapi aku
tak ambil pusing. Langsung aku
menuju ke bath tub, tapi tidak
mengisi airnya. Aku mau
shower-an saja. Sedang asyik- asyiknya aku ber-shower ria.
Terdengar ketukan di pintu
kamar mandi yang terkunci.
“Bang. Sorry. Kebelet pipis nih.”
Terdengar suara Ilen. “Bentar.”
Aku mengecilkan shower. “Tidak kuat nih.”
“Tapi aku bugil, Len. Gila kamu!”
“Gini deh, Abang buka pintu,
lalu masuk kembali ke dalam
bath tub. Tutup tirainya. Aku
sebentar saja. benar nih. Nggak kuat lagi.” Ilen
berteriak-teriak, “Aduuh..!”
“Oke, oke. Bentar.” Meloncat aku dari dalam bath
tub, membuka kunci, lalu
kembali ke sana. Kali ini
kututup rapat-rapat tirai
plastik yang berwarna putih.
Agak terbayang sih, tapi tidak kelihatan banget dari luar. Ilen
masuk, kuperhatikan masih
memakai bathrobe-nya. Dia
duduk di toilet. Langsung
terdengar suara seperti
gorengan dimasukkan ke dalam minyak panas. Dia tidak
mengada-ada. Benar-benar
ingin pipis. Kuusir lagi pikiran
anehku. Lalu menghidupkan lagi
pancurannya. Membilas sisa-
sisa busa sabun cair. Air hangat yang mengucur,
menghantam lembut kepala,
tubuh dan kakiku. Enak
banget. Terutama di sela-sela
selangkanganku. Ugh! Sensasi
itu terus terasa. Air yang mengalir itu membuat
kejantananku tiba-tiba
terbangun. Tanpa sadar
tanganku menyentuh si
buyung. Ugh! Tiba-tiba aku
tersadar. Bau tadi! Bau yang tercium samar di dekat
wastafel tadi. Itu bau harum
kewanitaan. Hah! Ilen? Dia tadi
masturbasi? Mungkin. Mungkin
dia tidak tahan mendengar
suara dari kamar sebelah. Nakal ya, Ilen sekarang. Pasti
dia duduk di toilet, memain-
mainkan kelembutannya
dengan tangan. Mengerang
dan mengejang sendirian. Gadis
nliar! Membayangkan itu, adikku tambah mengeras. Ugh!
Sekonyong-konyong tirai
disibakkan. Aku melompat,
kaget. Tanganku kulepaskan
sambil membalikkan badan. Di
hadapanku berdiri Ilen. Polos. Bathrobe-nya diletakkan di
wastafel. Mata gadis itu
menatap kejantananku. Reflek
aku menutupinya. Tapi
kepalanya yang indah itu masih
muncul dari sela-sela jemariku. Ilen menggerakkan wajahnya,
menyusuri tubuhku. Ke atas,
ke perut, dada, dan wajahku.
Tersenyum memandangku.
Sebuah senyum yang tak biasa
kuterima darinya. Bersambung . . . .