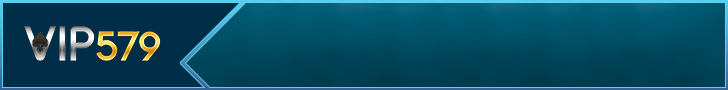Berdosakah mencintainya?
Sinar mentari yang menyegat tak menyurutkan langkahnya untuk segera menemui orangtuanya. Dalam kerapuhan jiwanya, ia terus menggerakkan tubuhnya ke tempat pembaringan terakhir mereka yang terkasih. Spanduk bertuliskan TPU Muslimin tersebut menari-nari di atas kepalanya. Langkah wanita muda itu kian tak bertenaga. Air matanya senantiasa terlahir dari ke dua belah mata indahnya. Wajahnya memerah menahan sakit batinnya, juga panasnya sinar mentari yang tak bersahabat.
Air matanya kian deras mengalir ketika ia telah berada di hadapan makam orang tuanya. Ia tersungkur dalam lutut lemahnya. Di antara makam orangtuanya, ia menangis sejadi-jadinya. Tangisannya agaknya dapat mengusik ketenangan penghuni makam lainnya.
“Ibu…, orang kaya itu menyakiti hati Annisa!” teriaknya seraya menunjuk ke suatu arah entah ke mana.
“Hati Nisa sakit karena lidahnya. Apa salah Annisa, Bu? Di mana salahnya? Apakah jatuh cinta salah, Ibu? Berdosakah bila wanita miskin ini mencintai pria seberharga putranya? Kalau semua itu adalah sebuah kesalahan dan dosa yang nyata, maka putrimu ini tetap akan jatuh cinta dan mencintainya, Ibu. Bagiku, ini bukanlah sebuah kesalahan ataupun dosa. Aku hanya tidak tahu diri saja,” kadunya tak tertahankan.
“Ibu, tidak bisakah sekejap saja datang padaku? Mengecupku, memelukku erat, menguatkanku yang rapuh kini. Hatiku mempercayai bahwa Ibu selalu melakukannya dengan cara yang takku tahu. Tapi, tubuhku ini tak mempercayainya sebelum aku benar-benar dapat merasakannya. Tidak bisakah, Bu?” tuturnya sesak lalu merebahkan kepalanya di atas nisan Ibunya “Fatimah binti Suherman”.
Wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera bangkit, lalu beralih menghadap makam ayahandanya. Secarik kertas berharga hampir saja terlupakan olehnya. Padahal hal itulah tujuan awalnya datang menyambangi kedua orangtuanya.
“Ayah…” sapanya berkaca-kaca. Semua perasaan ada dalam kalbunya.
“Lihat Ayah! Nisa berhasil. Putrimu berhasil. Ayah berhasil. Kita berhasil, Ayah. Coba lihat, Ayah!” ucapnya seraya memperlihatkan selembar kertas hasil UKDI ( Ujian Kompetensi Dokter Indonesia)-nya penuh kebanggaan.
“Sekarang putrimu ini adalah seorang dokter. Dokter… Annisa… Fatarani…,” Annisa mengeja namanya.
“Begitulah semua orang akan memanggilku. Mereka akan memanggil putri Ayah begitu. Lihatlah baik-baik, Ayah! Impian kita sedikit demi sedikit terwujud, Ayah. Perhatikan seksama, Ayah!” pintanya menyesak dada.
“Seharusnya sudah sejak hasil ini Annisa terima 15 hari yang lalu, Annisa datang kemari. Seharusnya Annisa segera memberitahu Ayah, kan? Annisa salah, Ayah. Maaf Ayah. Annisa masih harus disibukkan dengan persiapan internship dan hal lainnya.” Annisa memaparkan penjelasannya detail.
“Oya, Ayah. Annisa ditempatkan di Riau. Jauh ya, Yah? Subhanallah, Yah. Annisa bareng lagi penempatannya dengan Zahara. Mungkin hanya beda desa saja,” ceritanya kemudian.
Annisa mengukir senyum kecil di ujung ceritanya. Ia tak menyangka masih dapat bersama dengan sahabatnya itu, lagi. Semua itu tentunya bukanlah sebuah kebetulan semata. Ia percaya bahwa semua itu adalah takdir yang telah ditentukan Rabb-nya.
“Semua ini karena Ayah. Selain karena Annisa ingin hidup di dunia kesehatan ini, Annisa juga melakukan semua ini karena Ayah,” sebut Annisa.
“Tak boleh ada orang sakit yang tak terjamah pengobatan selama Annisa mengetahuinya. Annisa akan berusaha semampu Annisa, Ayah,” ikrar Annisa.
“Sungguh menyedihkan hanya mampu mengurusi orang yang dicinta yang jatuh sakit tanpa bisa mengupayakan apapun. Seperti Ayah dulu.” Annisa mengenang masa lalunya.
“Maafkan Annisa, Ayah!” ucap Annisa tercekat.
“Dulu, Annisa tak mampu mengupayakan pengobatan yang terbaik untuk Ayah. Maaf!” Annisa diam, berhenti bercerita, hanya tangisnya yang terdengar.
“Ayah…” panggil Annisa lembut di tengah gemuruh hebat dalam dadanya, lalu pembicaraanya mengarah ke topik lain. Air matanya mengalir lagi.
“Ayah, Pak tua itu jahat sekali. Ia menghempaskan harga diri Annisa. Di matanya Annisa tak ada harganya, menghina Annisa seenaknya. Tanpa sadar ia telah menghina Ayah pula. Ia menghina setiap kucuran keringat, air mata, darah, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan Ayah. Semua hal yang Ayah dan Ibu berikan untuk Annisa, dengan mudahnya ‘si Tua Bangka’ kaya raya itu meludahinya. Sakit sekali rasanya hati ini, Ayah,” papar Annisa dengan nada suara meninggi.
“Datanglah sekali saja, Yah! Datang dan ada di sisiku sekali ini saja,” pinta Annisa menyesak dadanya.
“Annisa tak yakin mampu menghadapi ini seorang diri,” ucapnya lemah, melemahkan dirinya.
“Annisa sungguh mensyukuri nikmat Allah atas perasaan cinta yang disisipkan-Nya di hati ini atas Ayah, Ibu, Zahara, keluarga baru Annisa dan yang lainnya. Tetapi, Annisa mengkufuri cinta atas pria itu,” tergugu Annisa menyuarakan isi hatinya.
“Tiap kali Annisa bertanya-tanya, mengapa cinta yang kukufuri dan ingin kusirnakan bisa datang, tumbuh dan hidup dalam hatiku dengan suburnya. Mengapa perasaan yang hanya akan mendatangkan sakit bagiku, baginya, dan orang lain yang tak merestuinya, Allah izinkan ada di sini?” tanya Annisa lirih, seraya menekan pelan dada kirinya.
“Wahai Allah! Aku tak bermaksud menyalahkan-Mu. Aku juga tak ingin berpikir buruk terhadap keputusan-Mu atas hidupku. Aku hanya minta agar Engkau membantuku agar aku mampu berdamai dengan diriku sendiri. Bantulah aku berdamai dengan hatiku ini, Allah!” nafasnya sesak mengutarakan pintanya pada Sang Penguasa.
“Ya Allah! Jika cintaku ini hanya akan membawa petaka baginya maka musnahkanlah kenangan atasku, cintanya padaku dan keinginanya terhadapku. Buat saja dia lupa bahwa aku pernah ada dihidupnya. Buatlah kehadiranku dalam hidupnya tak ada artinya. Buatlah agar dia melupakan aku yang mencintainya seperti kecintaanku pada diriku sendiri. Aku mohon, Ya Allah!” pinta Annisa berderai air mata.
“Tuhanku terkasih, haramkanlah air mata kesedihan hinggap di hati dan di pipinya. Bahagiakanlah dia, Allah. Di manapun dia berada, apapun yang dia lakukan, dengan siapapun dia, maka buatlah dia bahagia, Allah. Lindungilah dia dari ketakutan dan kesedihan. Aku mohon!” doa Annisa kembali menyesak dadanya.
“Bahagiakan dia, Allah! Karena Engkau Yang Mengkehendaki aku mencintainya hingga ku cintai dia karena-Mu, maka bahagiakanlah dia. Bahagiakan pria itu, Allah!” lanjutnya makin menyesak.
Annisa menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Terbayang wajah pria yang dicintainya dalam diamnya itu, hingga makin pilu hatinya.
“Aku berlindung kepada-Mu dari kedukaan hati karena makhluk-Mu. Ridhokanlah aku terhadap apa yang telah menjadi ketetapan-Mu terhadapku Allah,” pinta Annisa untuk kebaikan dirinya. Annisa mengusap wajahnya yang basah, lalu tersenyum getir, memandang ke kepala nisan orang tuanya.
“Annisa tidak apa-apa, Ayah. Ayah dan Ibu tak perlu mencemaskan Annisa,” jawabnya seolah-olah orang tuanya bertanya tentangnya sebelumnya.
“Allah kuasa mempergilirkan suka dan duka dalam kehidupan makhluk-Nya. Jika Allah berkehendak maka duka karena kehilangannya akan diganti-Nya dengan cinta yang lebih baik dari seseorang yang terbaik atas izin-Nya,” ujar Annisa mengimani kekuasaan Tuhannya.
“Ayah…, Ibu…, kalau dipikir-pikir dia memang benar. Dia benar sekali!” ucap Annisa membenarkan kata-kata berbisa dari lisan Pak Muchtar. “Hanya saja aku yang miskin ini, tak sudi ada yang mengataiku begitu, meskipun begitu keadaannya, lanjut Annisa berusaha melindungi harga dirinya.
“Ayah…, Ibu…, sungguh akan benar-benar membahagiakan, jika kalian dapat hadir di acara wisuda Annisa besok. Datanglah, Yah, Bu. Annisa ingin kalian ada.”
***
Tirai malam telah digelar dan nyanyian kegelapan pun tengah didendangkan. Seorang anak manusia nan jauh di bawah kerlap-kerlip bintang dan sinar bulan purnama yang terang benderang, sedang memikirkan sesuatu yang menyita waktu dan menguras pikirannya. Ia berusaha mengambil keputusan dan membulatkan tekad akan perkara hatinya yang hanya diketahui oleh Tuhannya, Rasulnya, bulan serta gemintang yang senantiasa menemaninya menanti, hingga saat-saat yang dinantinya tiba. Tak lama lagi, waktu itu akan dijelangnya. Tatapannya jauh sekali pada dunia di balik gemintang dan bulan dalam keadaan tandan tua itu.
Adindanya yang cerewet mengembalikannya ke dunia nyata dikarenakan kehadirannya yang tiba-tiba. Zahara langsung mengambil posisi di samping Khairul, melepas rindu pada Khairul yang telah lama jauh dari jangkauannya.
“Ayo, Mas! Lagi ngapain? Lagi menghitung bintang, ya?” candanya cepat.
“Husshhh… kamu ini! Memangnya Mas tidak punya kerjaan apa!” bantah Khairul tak terima.
“Trus Mas lagi apa? Kenapa memandangnya jauh sekali ke atas sana? Sedang mencari penampakan bidadari?” Zahara mencecar Khairul dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jeda.
“Percuma Mas! Jika itu tujuan Mas, maka akan sia-sia saja. Karena bidadari itu ada di samping Mas sekarang,” Zahara menjawab sendiri pertanyaannya.
“Hahaha…” tawa Zahara puas.
“Kamu ini!” balas Khairul geram. Khairul mengelus-elus kepala Zahara, membuat jilbab adiknya berantakan.
“Aduh Mas…!” keluh Zahara.
“Ara ini udah gede, dokter pula. Jangan dielus begitu lagi kepala Ara, Mas! Memangnya Ara si Catty, kucing anggora Mas itu,” Zahara protes.
“Mas tau kamu udah gede. Siapa sangka pula si cerewet ini sekarang udah jadi dokter. Tapi, kamu tetap aja ngegemesin seperti Catty,” terang Khairul.
“Ya…ya…ya… Ara tahu Mas. Kalau Ara ini cantik, manis, mungil dan menggemaskan,” cerocos Zahara membanggakan diri.
“Huuu…Pedenya!” ejek Khairul.
Mereka diam. Khairul mengangkat wajahnya kembali ke langit malam yang indah itu. Zahara memperhatikan saudaranya lekat. Matanya berkaca-kaca, cepat-cepat disekanya ujung-ujung matanya. Menahan diri dan hatinya untuk tak mencari tahu yang sebenarnya dirasa saudara terkasihnya.
“Mas sedang apa di sini? Lagi mikirin apa sih?” tanya Zahara serius.
“Tidak! Bukan apa-apa!” jawab Khairul enggan mengaku.
“Subhanallah, Mas! Aku inikan adikmu. Kenapa disembunyikan dari dr. Zahara Dwi Septina Wahab ini? Ayolah! Katakan saja ,” bujuk Zahara. “Ara tahu, Mas sedang berbohong.
Khairul tersenyum kecil membenarkan dugaan adiknya. “Baiklah! Kamu benar, Ra. Memang ada sesuatu yang Mas pikirkan,” jawab Khairul tenang.
“Apa?” tanya Zahara serius sungguh-sungguh ingin tahu.
“Rahasia!” jawab Khairul singkat tanpa beban dengan wajah jahil.
“Iiihh… Mas ini, buat penasaran saja,” ungkap Zahara kesal lalu menepuk pundak Khairul kencang menumpahkan kekesalannya.
“Aaauu…” Khairul mengerang pedih, mengelus pundak kanannya pelan.
“Ya sudahlah! Kita bahas yang lain saja,” Zahara mengalah.
“Besok Mas ikut, kan?” tanya Zahara mengalihkan topik pembicaraan.
“Iya donk dokter Zahara Dwi Septina! Mas, ingin menjadi saksi hari bersejarah kamu dan Annisa,” ungkap Khairul santai lalu mengurai senyum di bibirnya.
“Ahh…” Zahara menghela nafas panjang.
“Masih panjang perjalanan adikmu ini untuk menjadi seorang spesialis anak, Mas. Setelah ini masih ada internship dan PTT(Pegawai Tidak Tetap),” sebut Zahara menceritakan beban pikirannya.
“Ara ingin liburan,” Zahara mengungkapkan hajatnya.
Zahara merentangkan tangannya, menghela nafasnya panjang. “Aahh…! Alhamdulillah! Lega rasanya Mas. Bangga rasanya bisa menyelesaikan studi S1 ku ini dan lulus dengan pujian. lanjut Zahara Cumlaude! Cumlaude!” membanggakan diri.
“Rasanya semua jerih payah Ara bersusah payah dengan dunia perkuliahan yang super ribet ini, terbayar sudah. Masih terlalu dini untuk berpuas diri, sebenarnya. Meskipun begitu, Ara bersyukur karena Allah memudahkan ilmu ini bagi, Ara. Meskipun bukan sebaik Annisa yang berhasil menjadi lulusan terbaik, paling tidak hasilnya cukup membuat adikmu ini melayang hingga ke langit ke tujuh, Mas,” cerita Zahara riang.
“Oya, Mas tahu tidak bagaimana perasaan Ara saat terjun langsung menangani pasien saat koass. Waktu itu usai shubuh, jantung Ara terus bedebar-debar tak karuan. Pengalaman mengagumkan apalagi yang akan menghampiri Ara nanti? Subhanallah! Perasaan yang sangat luar biasa. Hebat, Mas! Saat gadis manis mungil usia 12 tahun yang menderita kanker usus itu mencoba tersenyum padaku…,” Zahara kembali pada salah satu sejarah paling mengharukan dalam hidupnya itu.
“Subhanallah! Senyum manis yang coba diukir oleh bibir kering dan wajah pucat itu takkan terlupakan selamanya, Mas. Gadis kecil itu pasien pertama Ara di hari pertama adikmu ini koass,” ucap Zahara haru dengan mata berkaca-kaca.
“Berikanlah tempat yang indah di sisi-Mu untuk Tami, Allah!” doa Ara dalam kalbunya.
“Ketika masih kuliah dulu, Ara banyak ngeluhnya. Menyesali diri mengapa memilih kedokteran sebagai jurusan studiku. Namun karena gadis kecil itu, Ara sadar, kalau dunia ini memanglah yang terindah untuk Ara, Mas. Subhanallah!” lanjutnya memamerkan kebahagiaannya, kembali memuji Tuhannya.
“Untung saja sahabatku Annisa! Kalau tidak, mungkin Ara masih setia berkutat dengan buku-buku tebal yang bikin pusing kepala itu, Mas. Jangankan untuk lulus tahun ini, mungkin sekarang ini Ara masih koass atau mungkin lebih parah dari itu. Gelar Sarjana Kedokteran saja mungkin belum,” Zahara mengestimasi kemungkinan terburuk. “Mas tahukan bagaimana malasnya, Ara?”
“Jika sebuah materi, sulit masuk ke kepalaku ini, maka Ara akan lebih memilih tidur,” Zahara mengakui kebiasaan buruknya.
“Huuffftt…! Mas tahu tidak, bagaimana si Annisa itu memarahi Ara? Dia menceramahi Ara, bahkan lebih parah dari Umi. Dia berceloteh tak mau henti hingga Ara mengerjakan semua tugas-tugas. Dia tidak mau berhenti sebelum Ara menguasai paksa semua materi itu. Bagaimana bisa tidur?” keluh Zahara.
“Terkadang Ara merasa bahwa Ara ini adalah cucunya. Cerewet sekali Mas!” sebut Zahara sambil seleng-geleng kepala.
“Katanya do the best and you will get the best. So perfectionist! “Ya! Dia memang begitu. Kalau bisa mendapatkan 1000, kenapa hanya menginginkan 999. Kalau ada peluang menjadi yang pertama maka jangan memilih untuk jadi yang kedua. Letakkan tujuanmu pada tingkat tertinggi. Jika memang tidak bisa menjadi yang pertama, maka berbedalah!” Zahara menirukan kalimat yang pernah disampaikan Annisa padanya.
“Iiihh… Ngeri!” gumam Zahara seraya menggigikan tubuhnya seperti melihat hantu.
“Standarnya tinggi, Mas. Terkadang terkesan keras bahkan pada dirinya sendiri. Bukan, bukan!” Zahara membenarkan kalimatnya.
“Dia memang keras. Keras kepala sekali malah. Jadi, berhati-hatilah dengan wanita satu itu!” Zahara memberikan nasehat eksklusifnya.
“Jika tidak punya apa-apa, maka menyerah sajalah! Menurut penilaian Ara, hanya pria gila yang akan mendapat perhatiannya.”
“Lantas bagaimana dengan pria-pria yang mendekatinya?” tanya Khairul serius dengan nada suara yang diusahakannya setenang angin.
Zahara memperhatikan wajah saudaranya seksama. Wajah tenang saudaranya seketika berubah begitu serius, begitu ingin tahu. Hati Zahara pedih menyadari kebenaran isi hati Khairul yang baru diketahuinya dan kini raut wajahnya menjelaskan segalanya. Zahara berusaha menguapkan pedihnya, mencoba untuk bersikap sewajarnya seolah-olah tak ada yang diketahuinya.
“Kebanyakan dari mereka minder duluan, Mas. Mundur teratur saja. Jikapun ada yang berani mencoba, usaha mereka entah mengapa pupus begitu saja, patah ditengah. Sementara sebagian lainnya, cinta dalam hati saja, Mas,” jelas Zahara.
Zahara tertawa kecil mengingat pria-pria yang berusaha mendekati Annisa. “Lumayanlah penggemar Annisa, Mas. Tapi, tidak sebanyak penggemar Zahara. Maklumlah, Mas! Kembang kampus! Hahaha…!” Zahara melepas tawanya, mengulang kepercayaan dirinya yang berlebihan.
“Dia sangat menjaga jarak dengan pria, Mas. Sedangkan Ara, sedikit lebih membuka persahabatan dengan pria. Tapi, tetap dengan batasan-batasan yang wajar,” Zahara meluruskan kata-katanya agar Khairul tak salah mengerti.
“Ara juga takut mendapat laknat Allah jika Ara melakukan yang tidak diinginkan-Nya. Begitulah!” Zahara mengakhiri ceritanya.
“Sekarang ceritakan tentang London, Mas! Apa hebatnya London itu, hingga mampu menahan Mas, bahkan hampir menggenapi tahun ke sembilan menetap di sana, jika tak dijemput paksa Abi dan Umi. Apa hebatnya memang negara itu, Mas? Sepertinya Mas betah sekali di sana. Apa wanita-wanita di sana ada yang menarik hati Mas hingga tak mau pulang?” tanya Zahara atunsias.
Khairul menatap adiknya penuh kasih, tersenyum hangat, kemudian melayangkan pandangannya ke langit malam, mengenang masa-masa yang dilaluinya di negeri rantaunya itu.
“Hmm… bagaimana, ya? Cantik sih. Cantik-cantik sekali malah. Hanya saja tak ada yang membuat Mas tertarik, Ra. Mereka cantik ala barat dengan pakaian yang kekurangan bahan di mana-mana. Mas paling tidak suka wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya pada dunia. Menyedihkan sekali rasanya wanita-wanita itu. Hampir seluruh auratnya telah dipertontonkannya. Kasihan suami mereka, Ra, hanya dapat sisanya,” nilai Khairul.
“Mas suka wanita yang cantik ala islam. Bukan berarti di sana tidak ada muslimah, Ra. Ada. Tapi, sekali lagi. Tak ada yang mampu membuat Mas tertarik,” cerita Khairul tenang.
Khairul diam, ditolehnya sejenak Zahara yang tak beralih memandangnya sejak ia mulai bercerita. Ia mengukir senyum andalannya, lalu kembali melempar pandangannya ke langit malam dan melanjutkan ceritanya.
“Kamu kan tahu, setelah selesai studi MBA, Mas ditawari pekerjaan di salah satu perusahaan dunia di sana. Hitung-hitung sebagai tambahan modal sebelum membantu Abi di perusahaan nanti. Bekerja dengan orang-orang hebat yang mengajarkan ilmu-ilmu berharga yang tidak Mas dapatkan di bangku kuliah. London luar biasa! I miss London!” ungkap Khairul.
“Sekali waktu, Mas berkeliling ibukota Inggris itu. Ketika masih ada Fauzi, jalan-jalan sama Fauzi. Setelah dia balik ke Indonesia dua tahun lalu, maka Mas pergi dengan Richard teman kerja Mas, terkadang juga pergi sendiri. Menikmati empat musim berganti setiap tahunnya dan disetiap pergantian musim pula, Mas berdoa, semoga dimusim berikutnya dapat menikmatinya bersama kamu, Umi, Abi, dan…” Khairul menahan lidahnya untuk tak menyebutkan satu nama yang lama disembunyikan hatinya, lalu berusaha secepatnya menguasai keadaan.
“Oya, kamu suka salju, kan Ra? Udah pernah ketemu salju asli, belum? Belum pernah, ya?” goda Khairul.
Zahara manyun. Ia tak dapat membantah pernyataan yang begitu menyakiti harga dirinya itu. Khairul menjepit mulut manyun adiknya dengan tangan kanannya, lalu melempar lagi pandangannya ke langit malam yang begitu memanjakan matanya itu.
Zahara kembali memperhatikan saudaranya yang kembali memandang jauh ke langit malam. Ia beranggapan bahwa Khairul sedang menyusun bintang-bintang guna membentuk satu gugus bintang baru membentuk nama orang yang disembunyikannya itu. Seketika mata Zahara perih, begitu pula dengan hatinya.
“Mengapa aku terlalu banyak tahu?” tanyanya lirih dalam hati.
“Bagaimana denganmu, Ra? Apa tidak ada pria yang berhasil menyita sedikit waktu adikku ini?” Khairul berusaha mengulik perkara hati adiknya yang tak pernah sedikitpun dibuka Zahara padanya.
Zahara diam sesaat, gantian dia yang melayangkan pandangannya ke langit malam, lalu kembali pada Khairul di sampingnya.
“Sejauh ini hanya rasa kagum saja yang Ara punya atas pria yang kelihatannya luar biasa itu, Mas. Sejauh ini belum ada pria yang berhasil menyita waktu Ara yang berharga hanya untuk memikirkannya. Apalagi harus mempertimbangkannya atau membayangkan masa depan dengannya,” tambah Zahara seadanya, mengeluarkan watak kerasnya yang tersamarkan oleh sikap periang dan manjanya.
Khairul memperhatikan air muka adiknya yang santai tak berbeban.
“Sepertinya yang keras pada diri sendiri itu bukannya Annisa, tapi kamu Dik,” Khairul menanggapi.
“Bukannya begitu, Mas. Memang belum ada saja pria yang berhasil menggetarkan hati Ara,” Zahara membela diri.
“Hmmm… kamu mau tidak, Mas kenalkan dengan seseorang?” tawar Khairul.
“Boleh. Siapa?” jawab Zahara terbuka.
“Bagaimana dengan Fauzi?” lanjut Khairul.
“Kak Oji ! Kalau Kak Oji, Ara kan sudah tahu,” balas Ara seperti tak mengerti maksud Khairul.
“Apa kamu tidak menyadarinya, Ra?” tanya Khairul menyelidik.
“Apa?” tanya Zahara datar dengan wajah bodohnya itu.
“Sahabat Mas itu diam-diam menyukaimu. Kamu tidak sadar?” jelas Khairul.
“Hmmm… Ara tahu, Mas. Tapi, Ara tidak mau tahu. Ara tidak suka pria pengecut. Apa susahnya mengatakannya pada Ara, Mas. Ara bukanlah monster yang akan menelannya. Seandainyapun Ara adalah seorang monster penyuka daging dan darah manusia, seharusnya dia tetap mengatakannya pada Ara. Pengecut! Bodoh! Ara benci pria pengecut yang bodoh,” jelasnya dengan wajah mengeras.
Khairul menelan ludah mendengar penuturan Zahara yang jauh dari perkiraannya, hingga ia tak mampu memberikan tanggapan apapun.
“Haahhh…” Zahara menghela nafas keras.
“Besok Ara wisuda, Mas. Apa Mas seperti ini juga sebelum wisuda?” ucap Zahara tiba-tiba, melupakan pertanyaan Khairul yang sedikitpun tak ingin dipikirkannya, apalagi sampai menganggunya.
“Zahara degdegan, Mas. Ara saja degdegan begini. Lantas bagaimana dengan Annisa yang akan memberi sambutan besok? Ahh… Ara tak mampu membayangkannya.” Zahara geleng-geleng kepala.
Khairul tersenyum indah, mengenggam tangan adiknya, menyemangatinya, pun melupakan pembicaraan mereka barusan. “Tidak apa-apa. Nikmati saja! Perasaan seperti ini mungkin akan kamu harapkan untuk terulang kembali dikemudian hari. Jadi, dinikmati saja,” saran Khairul yang sudah berpengalaman dengan perasaan itu. Khairul mengelus-ngelus lagi kepala Zahara.
“Mas!” Zahara berang.
“Mas rindu padamu, Kecil (panggilan sayang Khairul untuk Zahara sebab tubuhnya yang kecil),” papar Khairul.
“Ara tahu, Mas! Ara ini ngangenin,” jawab Zahara begitu percaya diri. Khairul mengelus-elus lagi kepala Zahara mengulangi hal yang tak disukai adiknya itu.
“Hentikan, Mas! Jilbab Ara berantakan!” cerocosnya kesal, mengkerut wajah Si Kecil dibuatnya.
“Oya, Mas. Zahara masih ada waktu empat minggu lagi sebelum internship ke Riau. Ayo kita ke Inggris, Mas!” ajak Zahara tak terduga.
“Ahh…malas! Mas juga baru balik dari sana!” jawab Khairul tak menyenangkan hati lawan bicaranya.
“Ayolah. Mas! Mas belum memberi Ara hadiah kelulusan, kan? Ara minta hadiah, Ara. Mas harus jadi tourgaet Ara. Kita keliling Inggris. Kalau Mas bosan dengan Inggris, kita ke Negara Eropa lain saja. Terserah Mas saja mau ke mana, yang penting ada saljunya, Mas. Ya?” bujuk Zahara lagi.
“Selama Mas di London, tak pernah sekalipun Ara ke sana, apalagi ke Negara Eropa lain. Paling jauh juga Arab Saudi waktu Umroh bareng Umi, Abi sama Annisa. Di sana cuma ada gurun pasir, Mas. Ngak ada salju, Mas…” Zahara merengek.
“Zahara pengen liat dan pengen tahu gemana rasanya salju turun, Mas. Ya?” Zahara memohon.
“Hmmm…” Khairul menundukkan kepalanya, seperti sedang memecahkan teka-teki tingkat dewa, kemudian mengangkat kepalanya.
“Baiklah! Coba tanya Abi dan Umi dulu. Kalau boleh, kita pergi!” sebut Khairul membesarkan hati Zahara.
Zahara sumringah. “Oke! Nanti Ara bujuk, Abi! Kalau Abi sudah setuju, Umi juga nanti ikut setuju. Semangat!” cetus Zahara menyemangati dirinya. Zahara memikirkan cara terbaik untuk membujuk Abinya agar mendapat izin guna melegalkan keinginannya.
“Hmmm…, Ra, meskipun nanti kita jadi pergi, sepertinya kita juga tidak akan berjumpa salju. Sekarang kan bukan musim dingin, Ra. Di sana sedang musim semi, Ra. Gemana dong?” ucap Khairul menyirnakan rasa bahagia Zahara.
Zahara menggigit bibirnya menahan kesal. Tangan kanannya segera di arahkannya ke pangkal lengan Khairul. Sekuat tenaga melancarkan cubitannya.
“Aauuu…!” erang Khairul.
“Maaf! Maafkan Mas, Ra?” sebut Khairul merasa bersalah, pun berharap jari-jari kecil Zahara segera berhenti mencubit pangkal lengannya. “Kalau memang mau pergi, Mas akan jadi tourgaet kamu yang setia. Oke?” imbuh Khairul berusaha mengembalikan mood baik adiknya.
“Batal! Tujuan utama Ara ingin ke sana itu karena ingin melihat salju. Kalau tidak ada salju, maka jadi tidak menarik lagi,” ungkap Zahara kesal.
Khairul mengelus-elus pangkal tangannya yang pedih. “Eropa juga indah meskipun sedang tidak turun salju. Ayolah! Jangan cemberut!” bujuk Khairul.
“Ara mau ke sana jika sedang turun salju saja. Jika tidak ada salju, maka tidak jadi, Mas. Batal!” ucap Zahara bersikeras. Khairul terdiam, tak berani mengusik dr. Zahara Dwi Septina lagi.
***